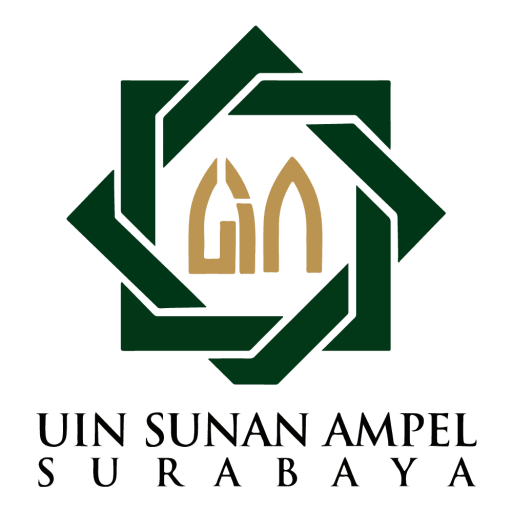Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
“Hai, Apa kabar? Bagaimana perjalanan sampai ke Hawaii?” Demikian pertanyaan-pertanyaan pembuka itu terlontarkan. Dari seorang perempuan. Namanya, Hannah Smith. Salah seorang panitia Konferensi Human Dignity and ASEAN. Di kampus Brigham Young University-Hawaii, Amerika Serikat. Kala itu adalah acara welcoming dan dilanjutkan dengan dinner, Selasa (22 April 2025). Konferensi sendiri berlangsung selama tiga hari, 23-25 April 2025. Kami pun para peserta internasional dari berbagai negara menyambut baik sapaan keramahan perempuan jelang paruh baya itu. Satu persatu peserta disalaminya. Dan satu persatu terlibat dalam percakapan singkat. Sebagai pertanda kehangatan penyambutan.
Nah, setiap kali melakukan sapaan dan perkenalan diri kepada setiap tamu konferensi itu, tak lupa dia selalu melanjutinya dengan kalimat berikut ini: “Perkenalkan juga, ini anak saya.” Dia ucapkan kalimat itu sambil menunjuk ke arah anaknya yang selalu berada di sampingnya. Itu dia lakukan ke hampir semua orang. Satu persatu. Lalu, dia melengkapi informasi mengenai anaknya itu dengan sejumlah kalimat pendek sebagai bagian dari perkenalan mengenai diri sang anak. Kuamati sang ibu bersama sang anak seperti itu dari satu meja peserta konferensi ke meja lainnya.
Nah ini yang menarik: setiap kali sang ibu menyebut namanya sambil menengok ke dirinya, sang anak lalu tersenyum. Dia lepaskan senyuman itu kepada setiap orang yang disapa oleh sang ibu. Bahkan bukan hanya senyum. Dia juga menganggukkan kepala. Bahkan sedikit menyertakan rundukan tubuhnya. Kepada setiap orang yang disalami dan dikenalkannya dia kepada sang tamu itu. Saat berpindah dari satu tamu ke tamu lainnya, sang anak itu juga melakukan hal yang sama: melepaskan senyum, menganggukkan kepala, dan sedikit merundukkan tubuh.
Kucatat betul dalam ingatan kejadian di atas. Hanya, tak mungkin kuabadikan kejadian itu dalam bentuk foto atau video. Karena aku terikat oleh kode etik bersosialisasi di ruang publik. Salah satunya, identitas atau apapun tentang diri anak tidak bisa diekspos luas. Itu meskipun sudah mendapat izin dari orang tuanya. Aku patuh pada kode etik itu. Aku hormat pada adab ruang publik itu. Agar tak ada yang dirugikan oleh apapun dari yang kuproduksi atas kejadian itu. Khususnya sang anak yang usianya kira-kira antara 8 sampai 10 tahun. Terhitung masih cukup kecil.
Aku terpesona sekali dengan kejadian itu. Pertama, sang ibu membawa sang anak untuk masuk ke ruang sosialisasi diri yang lebih tinggi nan luas. Dia tak mementingkan dirinya semata. Untuk menunjukkan keramahan dalam penyambutan tamu. Tapi, dia ajak serta sang anak untuk masuk ke ruang sosialisasi lebih luas kepada para peserta konferensi dari berbagai negara di dunia itu. Kedua, sang anak menunjukkan adab dan perilaku layaknya orang dewasa yang sudah mengerti ukuran dan makna derajat kesantunan yang tinggi kepada sesama. Apalagi, yang dihadapi oleh sang anak itu adalah orang dewasa yang fisik, warna kulit, dan tampilannya tak seperti yang biasa dia temui di lingkungan terdekatnya yang berasal dari kalangan kulit putih dan berkewargenegaraan Amerika.
Karena itu, ku merasa penting untuk mengambil pelajaran dari praktik hidup ibu dan anak dalam sosialisasi penyambutan tamu konferensi internasional di atas. Minimal, ada tiga pelajaran penting di situ. Pertama, ajarkanlah adab perilaku kepada anak sejak sedini mungkin. Jangan menundanya hingga anak sudah menginjak remaja. Apalagi dewasa awal. Itu walaupun prinsip lanjutan juga berlaku: tak ada kata terlambat mengajarkan akhlaq dan adab kepada anak. Seorang ibu yang bernama Hannah Smith di konferensi internasional di Hawaii, Amerika Serikat, di atas telah mengajarkan bahwa pembelajaran adab sudah dilakukan kepada anak sedini mungkin. Bahkan, pembelajaran itu sudah menggunakan sarana sosialisasi fisik yang berskala publik luas.
Adab memang berbasis kultur. Suka atau tidak suka. Saat kultur berbeda, bisa berbeda pula ekspresi adab itu. Inilah yang menjelaskan mengapa hukum Islam pun juga mengepresiasi kultur lokal. Karena di sana ada urusan moral. Tapi, meskipun begitu, ada derajat adab yang berlaku universal. Lazimnya menunjuk kepada prinsip utama berikut: penghormatan kepada kemanusiaan. Derajat adab yang berlaku universal itu justru mewujud untuk menjunjung tinggi derajat kemanusiaan (human dignity) itu sendiri. Prinsip penghormatan kepada kemanusiaan yang demikian ini berlaku efektif terlepas seberapa besar dan tinggi tingkat perbedaan kultur yang memayungi perwujudan adab itu.
Saat kepentingannya bertemu pada penghormatan atas human dignity di atas, maka perbedaan kultur apapun bisa dikalahkan oleh kepentingan untuk menjaga adab itu. Pada titik inilah, semua anak manusia memiliki kepentingan yang sama. Yakni, menjaga, mempertahankan, dan bahkan meningkatkan marwah atau derajat kemanusiaan mereka. Sebab, saat ada praktik abai terhadap penjunjungan tinggi atas marwah atau derajat kemanusiaan itu, maka sejatinya kita sebagai manusia sudah kehilangan jati diri yang sebenarnya. Alih-alih, kepentingan material nan profan lebih menguat pada diri banyak komponen anak manusia daripada kewajiban untuk menjaga martabat kemanusiaan itu sendiri.
Oleh karena itu, belajar dari kultur manusia yang beragam sangatlah penting. Belajar adab lintas kultur juga sangatlah penting. Itulah yang bisa kutangkap dari bagaimana perempuan yang bernama Hannah Smith di atas mengajak serta sang anak laki-lakinya itu untuk berlatih kesantunan kepada para peserta konferensi internasional yang berasal dari berbagai negara di atas. Pertemuan konferensi internasional dijadikan sebagai sarana sosialisasi adab pada sang anak. Oleh sang ibu itu, si anak lelakinya tak hanya dibiarkan berada di forum konferensi internasional itu begitu saja. Melainkan diajaknya berkenalan ke semua peserta dengan berbagai praktik kesantunan seperti yang kujelaskan di atas. Itu dilakukan di tengah perbedaan budaya yang hampir bisa dipastikan ada. Karena mereka berasal dari lintas budaya dan lintas batas budaya negara.
Bagaimanapun, karena berasal dari lintas negara dan bahkan kawasan di dunia, kultur mereka yang berada di forum konferensi internasional itu pasti tak sama. Tapi, justeru karena kultur yang tak sama itu, Hannah Smith tampak terdorong untuk mengajak serta sang anak untuk bersosialisasi dengan para peserta lintas kultur lintas negara di atas. Dengan begitu, adab multikulturalisme sudah mulai dia semai ke dalam diri sang putera. Dengan demikian pula, adab di keluarga yang secara internal telah dia tanamkan disempurnakan dengan sosialisasi internasional ke peserta lintas budaya dan batas negara di atas. Tentu dengan cara seperti itu, sang anak bisa semakin menyempurnakan konsep dan praktik adabnya secara multikultural.
Sebagai pelajaran kedua, jadikan kesempatan berada di ruang publik sebagai panggung untuk mensosialisasikan diri anak kepada kalangan lebih luas. Semakin terbukanya aktivitas dan mata pencaharian (mode of production) orang tua, semakin luas pula ruang mereka beraktivitas di ruang publik. Nah, kecenderungan ini tak boleh membuat keberadaan mereka semakin terjauhkan dari intensitas pendampingan mereka terhadap anak sendiri. Karena itu, situasi semacam itu juga harus bisa dimanfaatkan untuk memperkuat nilai dan ruang pendidikan adab oleh orang tua kepada anak-anaknya.
Apa yang dilakukan Hannah Smith terhadap sang putera dalam rangkaian penyelenggaraan konferensi internasional di atas jelas menunjukkan bahwa perempuan itu ingin membangun prinsip begini: bahwa sibuk di luar tak harus kehilangan peran sebagai orang tua dalam menanamkan nilai dan adab kepada anak. Dia tampak ingin menjawab kesalahan praktik di sejumlah kalangan bahwa terbatasnya waktu kebersamaan dengan anak di rumah semakin memperburuk penanaman adab kepada sang anak. Keterbatasan waktu kerap menjadi bulan-bulanan. Menjadi kambing hitam.
Hannah Smith telah membalikkan semua itu. Dia tetap mampu menjadikan kesibukannya di luar rumah sebagai kesempatan emas baginya untuk memperkuat pendidikan adab. Bagaimana pendidikan adab bisa berlangsung dalam situasi itu? Melalui apa yang disebut dengan social exposure. Yakni, menjadikan kesibukan di luar rumah sebagai kesempatan untuk memperkuat jam terbang anak untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama. Bahkan dengan lingkungan sosial yang berbeda generasi. Secara lebih luas. Bahkan lebih lanjut dalam kasus Hannah Smith dan sang putera di atas, jelas tergambar bahwa sang putera akhirnya bisa bersosialisasi dan berinteraksi dengan gugusan individu lintas budaya dan lintas batas negara.
Social exposure di atas sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengalaman sosial sang anak untuk mengembangkan dan sekaligus memperkuat nilai keadaban yang diajarkan oleh orang tua di rumah. Social exposure dimaksud seakan menjadi lahan subur bagi sang anak untuk memenuhi kebutuhannya dalam pembenihan dan sekaligus penumbuhan nilai keadaban tertentu ke dalam dirinya. Sebab, sekali lagi, adab tumbuh di atas budaya tertentu. Budaya dimaksud tak berada di ruang kosong. Pasti memerlukan lingkungan sosial tertentu untuk tumbuh dan berkembang.
Karena itu, hubungan antara social exposure, budaya, dan pengalaman sosial sangatlah erat. Ketiganya berkelindan untuk menjadi sebuah instrumen penting bagi tumbuh dan berkembangnya sebuah nilai keadaban dalam diri individu. Termasuk dan terutama dalam diri anak yang menurut sifat pertumbuhannya masih dinamis. Konkretnya begini: saat social exposure dan budaya bertemu dan bergerak secara efektif dalam ikatan hubungan yang kuat, maka bisa dipastikan bahwa pada diri anak yang berada di dalamnya akan muncul pengalaman sosial yang kuat pula.
Nah tugas orang tua, sekali lagi, adalah menjaga agar hubungan antara social exposure, budaya, dan pengalaman sosial berada dalam ukuran kebaikan tertentu. Jangan ada unsur keburukan di antara ketiganya. Atau yang bisa menghalangi tumbuhnya kebaikan. Sebab, saat social exposure dan budaya bertemu dan bergerak secara efektif dalam ikatan kebajikan tertentu, maka yang akan muncul adalah pengalaman sosial yang baik. Nah, pengalaman sosial yang baik inilah yang dibutuhkan oleh sang anak untuk menumbuhkan dan sekaligus memperkuat nilai keadaban tertentu ke dalam dirinya.
Karena itu, tugas orang dewasa atau orang tua adalah menciptakan lingkungan sosial yang baik bagi anak agar tercipta social exposure dan terwujud budaya yang kondusif bagi tumbuhnya pengalaman sosial yang baik dalam diri sang anak. Juga, tugas orang tua lainnya adalah perlunya membawa anak untuk memiliki pengalaman sosial yang baik dengan masuk ke dalam social exposure yang baik nan efektif pula. Nah, kewajiban ganda seperti ini harus disadari dan dilakukan oleh orang tua dalam menunaikan kewajibannya dalam membesarkan sang anak. Itu semua dibutuhkan agar adab bisa ditransfer dan kemudian dikembangkan dalam diri sang anak.
Sebagai pelajaran ketiga, jangan pernah membuat acara dengan melarang keikutsertaan anak di dalamnya. Kecuali acara kenegaraan yang memang mempersyaratkan kekhidmatan formal. Selebihnya, jangan ada pelarangan. Bahkan termasuk dalam hal peribadatan. Libatkanlah sebisa dan sebiasa mungkin anak dalam kegiatan bersama secara efektif. Kata “efektif” ini harus kusebut untuk memberi catatan bahwa pelibatan itu baik, tapi harus dilakukan dengan segala pertimbangan dan skema untuk menjaga nilai kebermanfaatan dalam penyelenggaraannya.
Menjauhkan anak dari kegiatan bersama berarti mempersempit ruang social exposure mereka ke dalam kehidupan sosial yang luas. Padahal, anak harus mendapatkan pengalaman baik yang luas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama. Kepentingannya adalah untuk pendidikan adab, seperti yang kuuraikan sebelumnya. Dengan pengalaman sosial yang baik itu, akan tumbuh kesadaran beradab di ruang publik. Sekaligus juga akan muncul harapan, ekpektasi, dan mimpi besar dalam diri anak untuk bisa sukses di masa mendatang dalam keberadaannya bersama sesama. Ukurannya adalah sesukses atau bahkan mungkin lebih sukses dari yang dia amati dalam proses sosialisasi dan interaksi sosial yang dia ikuti.
Inilah yang menjadi konteks mengapa orang dewasa tak sepatutnya menjauhkan anak dari aktivitas ruang publik. Termasuk melarang mereka untuk ikut serta atau hadir dalam kegiatan atau acara-acara bersama di ruang publik. Tentu dengan catatan seperti yang kusebut sebelumnya juga bahwa orangtua atau orang dewasa harus menjamin bahwa anak berada dalam lingkungan sosial yang baik dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya adab dalam dirinya. Karena itulah, pelibatan anak dalam aktivitas bersama, seperti yang kusebut di atas, harus dilakukan secara efektif.
Dalam bentuk konkretnya, pelibatan anak secara efektif bermakna seperti ini: bukan hanya melibatkan semata, lalu orang tua membiarkan mereka terlepas dari pengawasan dan pendampingan. Bukan. Bukan itu sama sekali. Alih-alih, bentuknya adalah mengikutsertakan anak dalam kerangka pendidikan adab. Dengan begitu, keberadaan anak dalam situasi sosialisasi dan interaksi sosial di ruang publik digerakkan oleh semangat untuk memberi pengalaman yang positif bagi kepentingan penumbuhan dan pengembangan adab sang anak.
Kalau keberadaan mereka di ruang publik dilakukan pembiaran oleh orang tua, maka tak akan pernah ada pergerakan untuk pendidikan adab anak. Tanpa ada pendampingan yang efektif, pendidikan adab tak akan pernah tercipta. Alih-alih, anak akan terekspos ke pengalaman sebaliknya. Musibah justru mulai lahir saat anak lebih banyak terekspos ke pengalaman buruk untuk kepentingan perilaku anak. Akibatnya, adab hanya akan makin menjauh dari anak. Karena anak sendiri semakin berjarak dari nilai adab. Akibat pengalaman sosial yang buruk. Penyebabnya adalah eksposur sosialnya yang justru cenderung menguat ke cakupan keburukan dalam kehidupan bersama dengan sesamanya.
Dalam pengalaman Hannah Smith bersama putranya di atas, memperkenalkan anak dan memberikan informasi sejumlah perihal dasar tentangnya adalah salah satu cara yang dilakukan Hannah Smith untuk membawa anak bersosialisasi ke level yang lebih luas. Khususnya kepada para peserta konferensi internasional yang hadir. Kebetulan, karena acaranya konferensi internasional, maka audiens yang hadir dan dia salami semua itu adalah para akademisi dan aktivis kemanusiaan dari berbagai penjuru dunia. Kebetulan saja begitu. Namun, membawa anak untuk bersosialisasi ke kalangan yang lebih luas, terlepas apapun latar belakangnya, menjadi sarana penting untuk membelajarkan adab kepada anak-anak.

Mengapa sosialisasi penting bagi pendidikan adab? Sederhana sekali jawabannya. Pendidikan adab itu, seperti kuuraikan di atas, membutuhkan social exposure. Membutuhkan jam terbang. Bentuknya adalah pengalaman sosial dalam berinteraksi dengan sesama. Semakin tinggi social exposure, makin terbuka pula ruang untuk pengembangan adab. Semakin tinggi jam terbang dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama, makin luas pula medan penguatan adab pada diri anak. Tinggal, pekerjaan orang dewasa adalah memberikan ruang yang baik bagi tumbuhnya social exposure itu. Agar anak bisa tersosialisasi dan terekspos ke pengalaman baik dalam hidupnya.
Di sinilah, nasehat Mbah Sunan Bonang, wong kang soleh kumpulono, juga berlaku bagi pendidikan adab. Kalimat hikmah itu berarti dalam Bahasa Indonesia “bergaullah dengan orang shaleh”. Anak memang harus tersosialisasi dan terekspose ke dalam lingkungan yang baik. Agar pengalaman hidupnya juga baik. Karena itulah, nasehat Mbah Sunan Ampel di atas juga mengandung pesan agar orang tua juga menyediakan ruang sosial yang baik bagi tumbuhnya adab anak. Jangan abai pada lingkungan sosial anak. Alih-alih, libatkan mereka ke dalam pengalaman sosial bersama kebajikan sesama. Agar tumbuh kuat social exposure mereka yang kondusif dan efektif bagi terciptanya pengalaman yang positif menuju terciptanya adab yang baik.