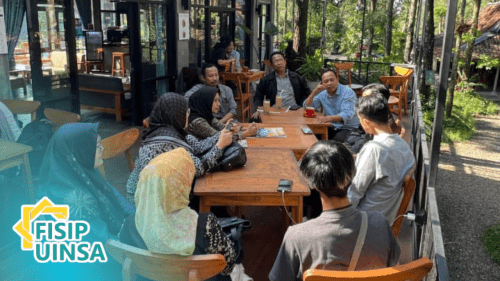Oleh: Agus Syarifudin Efendi, M.A.
 Kepulangan jamaah haji ke tanah air selalu menjadi momen istimewa yang tak hanya bermakna religius, tetapi juga sosial dan kultural. Bagi masyarakat Indonesia, kepulangan ini dirayakan dengan penuh suka cita, bukan hanya karena anggota keluarga telah kembali dengan selamat, tetapi karena momen ini membawa serta nuansa spiritual yang memperkaya kehidupan bersama. Rumah para haji seketika menjadi ruang silaturahmi, tempat berkumpulnya para tetangga, sahabat, dan kerabat untuk berbagi doa, cerita, dan keberkahan.
Kepulangan jamaah haji ke tanah air selalu menjadi momen istimewa yang tak hanya bermakna religius, tetapi juga sosial dan kultural. Bagi masyarakat Indonesia, kepulangan ini dirayakan dengan penuh suka cita, bukan hanya karena anggota keluarga telah kembali dengan selamat, tetapi karena momen ini membawa serta nuansa spiritual yang memperkaya kehidupan bersama. Rumah para haji seketika menjadi ruang silaturahmi, tempat berkumpulnya para tetangga, sahabat, dan kerabat untuk berbagi doa, cerita, dan keberkahan.
Namun, di balik semua euforia penyambutan itu, ada makna yang lebih dalam yang patut direnungkan. Gelar haji bukanlah sekadar status spiritual atau simbol sosial, tetapi juga panggilan untuk menghayati kembali nilai-nilai tauhid yang telah diwariskan sejak masa Nabi Ibrahim. Dalam ibadah haji, jejak perjuangan dan pengorbanan keluarga Ibrahim bukan hanya dikenang, tetapi dihayati dalam laku ibadah yang membentuk ulang kesadaran diri. Inilah saat yang tepat untuk menelusuri kembali tradisi keimanan Ibrahim dan merefleksikan arah hidup kita sebagai umat Islam.
Haji: Ritual, Silaturahmi, dan Spirit Komitmen
Pada minggu-minggu ini, umat Islam Indonesia akan menyambut kepulangan para jamaah haji yang telah selesai menunaikan rukun Islam kelima. Ini merupakan momen yang membahagiakan karena para jamaah haji akan bertemu kembali dengan keluarga, tetangga, dan kolega setelah menjalani perjalanan spiritual ke Tanah Suci. Tahun ini, jumlah jamaah haji Indonesia mencapai 221 ribu orang. Dengan angka sebesar itu, momen kepulangan haji tentu memiliki dampak sosial dan emosional yang luas bagi masyarakat.
Dalam budaya masyarakat kita, kepulangan jamaah haji tidak sekadar menjadi kembalinya individu dari perjalanan ibadah, melainkan juga memicu gelombang silaturahmi yang hangat. Para hajah dan haji disambut penuh sukacita. Rumah mereka menjadi pusat kunjungan, bagaikan sarang lebah yang ramai dikunjungi oleh kerabat, tetangga, hingga kolega. Selain saling mendoakan dan berharap berkah, kepulangan ini kerap menjadi ajang berbagi cenderamata atau makanan khas seperti kurma dan air zam-zam.
Namun, lebih dari itu, menyandang gelar haji atau hajah berarti memikul komitmen moral untuk menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh. Komitmen ini seharusnya tercermin dalam sikap dan tindakan sehari-hari yang membawa kemaslahatan. Gelar haji mabrur bukan sekadar pengakuan sosial, tetapi penanda kualitas ruhani yang berakar pada kesungguhan dalam meneladani ajaran Nabi Ibrahim.
Keluarga Ibrahim dan Arah Kemanusiaan Kita
Dalam konteks ibadah haji, sosok Nabi Ibrahim tidak bisa dilepaskan. Al-Qur’an menyebut jalan hidupnya sebagai millah Ibrahim—sebuah tradisi keimanan yang rasional, mendalam, dan penuh kasih sayang. Kisahnya memperlihatkan bahwa pencarian Tuhan melalui akal sehat membawa manusia pada ketundukan terhadap Dzat yang Mahatinggi. Nabi Ibrahim bukan hanya menentang penyembahan berhala karena alasan teologis, tetapi juga karena bertentangan dengan hukum akal budi.
Meski menolak keyakinan kaumnya, Ibrahim tidak menaruh kebencian. Ia bahkan tetap menyayangi ayahnya yang pembuat patung berhala. Dari sini, kita belajar bahwa keteguhan tauhid tidak mesti menghilangkan kasih. Inilah yang menjadikan ajaran Ibrahim disebut sebagai agama hanif—lurus, bijak, dan penuh welas asih.
Dalam kehidupannya, Nabi Ibrahim senantiasa memohon agar diberi kebijaksanaan dan tetap berada di jalan kebenaran. Salah satu doa yang paling menggambarkan kerendahan hati dan keteguhan spiritualnya adalah:
“Rabbi habli ḥukman wa alḥiqni biṣ-ṣāliḥīn”
“Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku hikmah, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.”
Doa ini adalah cerminan dari keinginan mendalam untuk menjadikan hidup sebagai ladang kebijaksanaan, bukan sekadar ibadah formalitas.
Tradisi tauhid ini kemudian diwariskan kepada anak-cucu Ibrahim: Nabi Ishak, Ismail, Musa, Isa, hingga Muhammad saw. Maka, tidak berlebihan bila ia disebut sebagai bapak para nabi. Lebih dari sekadar kisah, perjuangan keluarga Ibrahim menjadi fondasi spiritual dan moral umat Islam. Melalui ritual haji, kita diajak menapaktilasi jejak Ibrahim—dari pembangunan Ka’bah, kisah Siti Hajar dan Ismail di padang tandus, hingga peristiwa penyembelihan yang mengharukan.
Keluarga Ibrahim adalah simbol kemanusiaan yang bertumpu pada iman, pengabdian, dan pengorbanan. Siti Hajar dan Ismail yang ditinggalkan di tengah padang gurun menunjukkan bahwa kasih ibu dan kebergantungan kepada Allah menjadi kekuatan sejati dalam menghadapi kecemasan. Sementara itu, kesiapan Ibrahim mengorbankan putranya menjadi simbol keikhlasan bahwa segala yang kita miliki sejatinya hanyalah titipan.
Maka, meneladani keluarga Ibrahim berarti mendidik diri untuk menjadi pewaris tradisi tauhid. Bukan sekadar dalam bentuk ritual, tetapi juga dalam kesadaran etis dan spiritual kita sebagai manusia. Dengan memahami makna perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan mereka, kita akan terdorong untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan kita—baik sebagai individu, keluarga, maupun bagian dari umat. (ed. FyP)
Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya