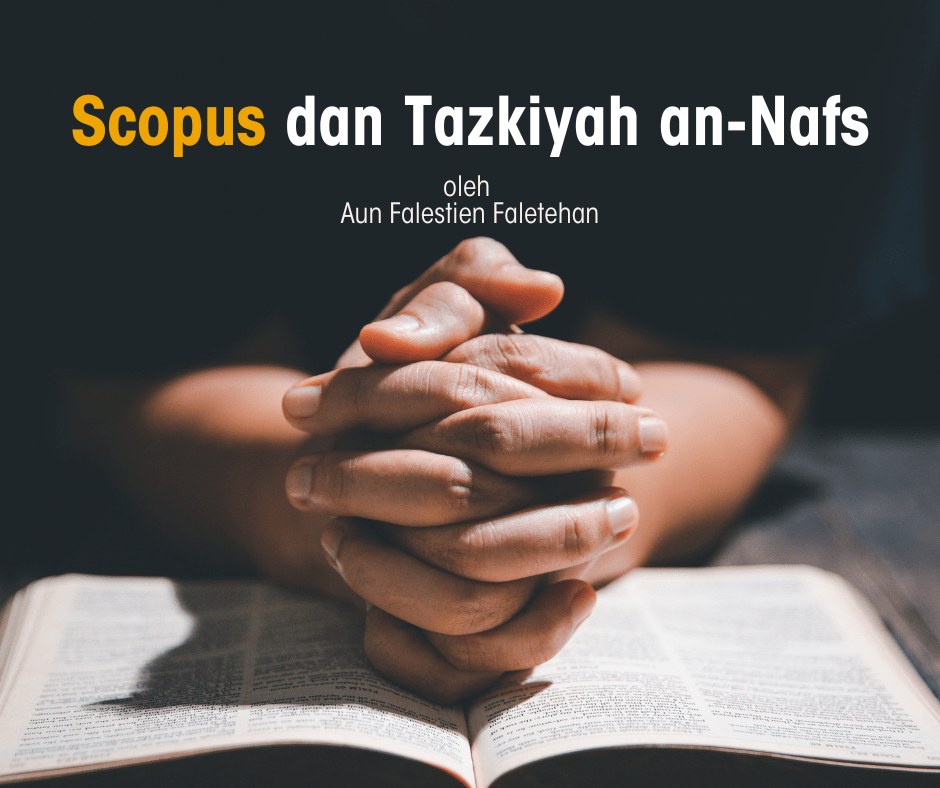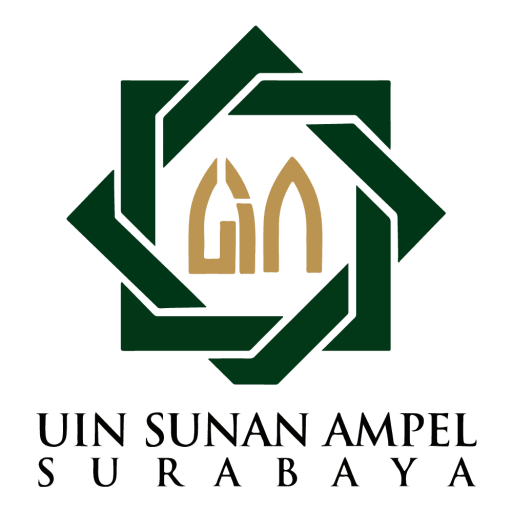Scopus dan Tazkiyah an-Nafs
oleh
Aun Falestien Faletehan
Kata kunci ‘Scopus’ jika disandingkan dengan ‘Indonesia’ kerap melahirkan drama—kadang serius, kadang komedi. Ini sebenarnya sudah bisa ditebak, mengingat usia kedewasaan intelektual akademisi kita masih dalam proses pertumbuhan. Di era yang sama ketika Oxford University telah menjadi pelopor pengembangan ilmu pengetahuan global, kita masih sibuk memelihara romantisme kejayaan Majapahit. Padahal, Oxford sudah berdiri jauh sebelum Majapahit dibangun. Jadi ya wajar, perbedaan waktu dan kedewasaan itu memengaruhi cara kita merespons ilmu. Kita memang sedang berproses. Kita memang sedang menempuh perjalanan panjang menuju ekosistem akademik yang lebih matang.
Scopus adalah produk modern dengan reputasi tinggi dalam mengkurasi dan menilai karya ilmiah. Saat ini, Scopus telah mengindeks lebih dari 46.000 jurnal dan prosiding konferensi dari berbagai disiplin ilmu. Ia menjadi rujukan utama untuk reputasi akademik global.
Karena Scopus sering dijadikan ‘tujuan akhir’ publikasi, mestinya dicapai lewat proses yang baik. Banyak konferensi, seminar, riset besar, yang semuanya bermuara ke satu kata: published. Tapi semua itu jadi sia-sia kalau akhirnya justru membuka aib intelektual sendiri. Kalau sudah terlanjur terbit di jurnal predator, susah menghapus jejak digitalnya. Anak cucu kita bisa menertawakannya nanti.
Secara logika sederhana: jika Scopus adalah impian besar semua akademisi, mungkinkah dicapai dengan cara instan? Saya tidak bicara soal jurnal abal-abal, tapi jurnal bereputasi tinggi. Pengalaman di kampus-kampus luar negeri menunjukkan bahwa publikasi yang bagus butuh proses panjang. Di sana, mayoritas dosen sudah akrab dengan penolakan dari editor, meskipun mereka hidup dalam kultur riset yang matang, punya resource dan fasilitas yang mumpuni, dan tidak terjebak dalam beban mengajar seperti kita di sini.
Rata-rata dari sepuluh manuskrip yang ditulis, mungkin hanya enam atau tujuh yang akhirnya terbit. Itupun setelah direvisi berkali-kali dan berpindah dari satu jurnal ke jurnal lain. Jadi, kadang heran ketika lihat dosen di Indonesia—sudah sibuk ngajar, aktif di luar, terjebak birokrasi, tidak akrab dengan bahasa Inggris, jarang baca artikel ilmiah mutakhir, gaptek dengan tren metode riset, minim pengalaman publikasi—tapi tiba-tiba begitu gampangnya bilang, “Ayo, kita submit ke Scopus semester ini.” Individu seperti inilah yang mudah jadi korban jurnal predator.
Kita perlu menanamkan mindset bahwa menulis artikel itu adalah sarana menyebarkan ilmu yang bermanfaat, bukan sekadar mengejar ‘published segera’. Submit harus disertai harapan mendapat masukan dari reviewer.
Tazkiyah an-nafs—penyucian jiwa—berperan besar di sini. Dalam tradisi sufisme, tazkiyah berarti proses membersihkan diri dari nafsu duniawi dan mengarahkan hati untuk kembali kepada Allah. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa “ilmu tanpa keikhlasan adalah hijab yang menyesatkan.” Bila niat menulis hanya karena jabatan, maka ketika jabatan itu diraih, semangat menulis akan padam.
Kita perlu turunkan ego. Jangan merasa manuskrip kita pasti bagus. Keberadaan reviewer sengaja dibuat, karena untuk menunjukkan kelemahan tulisan kita. Tugas reviewer itu kalau tidak mencari kelemahan, ya untuk meningkatkan artikel yang sudah bagus. Jadi, kritik selalu muncul. Di negara maju, profesor senior pun biasa melakukan revisi berkali-kali. Karena mereka tahu, setiap karya bisa diperbaiki melalui masukan orang lain.
Allah Maha Tahu kapasitas dan niat kita. Dia akan menempatkan manuskrip kita pada tempat terbaik jika kita terus berusaha. Saya masih ingat kata-kata dosen saya di Amsterdam, setelah manuskrip saya ditolak berkali-kali: “Tenang saja. Itu biasa. Manuskripmu nanti akan menemukan rumahnya sendiri.”
Beberapa jurnal Scopus itu ‘abadi’, terutama jurnal flagship yang dikelola dengan serius, karena mereka berniat untuk mengapresiasi dan menjaga artikel ilmuwan sepanjang masa. Namun, untuk mencapai tingkat tersebut, prosesnya tidaklah cepat. Ada kolega yang bahkan membutuhkan waktu hingga 10 tahun—mulai dari draft awal hingga terbit—untuk satu artikel, menunjukkan betapa panjang dan seriusnya perjalanan publikasi di jurnal-jurnal semacam itu.
Karena itu, jadikan Scopus sebagai bagian dari ‘suluk intelektual’ kita. Pastikan kita benar-benar berkontribusi—bukan sekadar titip nama. Penulisan artikel seharusnya mencerminkan kualitas diri kita. Revisi dari reviewer adalah nasehat yang membersihkan. Al-Ghazali menyebut, “Orang yang tidak mau dinasehati adalah orang yang telah mati hatinya.”
Sebagai muslim, niatkan tulisan kita sebagai amal jariyah. Biarkan tulisan itu mengalir seperti air. Air akan selalu menemukan jalannya. Tak perlu mengemis sitasi. Tugas kita hanya menyampaikan, dakwah ilmiah.
Kalau diniatkan sebagai jariyah, bersihkan seluruh prosesnya, mulai dari etika riset, kejujuran dalam kepenulisan, hingga niat akhir untuk menyebarkan ilmu, bukan sekadar naik pangkat. Dalam catatan Ibn ‘Ataillah dalam Al-Hikam, “amal yang bersih dari hawa nafsu lebih bernilai di sisi Allah, meski kecil di mata manusia.”
Sayangnya, Scopus kadang hanya jadi modus. Modus eksploitasi mahasiswa. Modus menaikkan branding diri. Modus menaikkan pangkat. Modus pemeringkatan kampus. Nama yang sejatinya melambung tinggi seperti burung tajam berwawasan luas, Scopus umbretta atau Hamerkop (Bangau kepala palu), malah diseret-seret jadi alat manipulasi sistem. Banyak dosen kini mengejar publikasi hanya demi akreditasi, pangkat, atau insentif. Bukan karena ingin membagikan ilmu, atau mendekatkan diri pada nilai-nilai kebenaran. Maka, wajar jika sebagian dari kita menyebutnya sebagai era ‘taqarrub ilâ Scopus’— sebuah ‘ibadah’ menuju indeksasi dan pengakuan formal.
Namun mari kita jujur sejenak. Apakah benar ini esensi dari keilmuan? Apakah memang tujuan pendidikan tinggi hanya untuk menjadi mesin publikasi? Apakah pencapaian kita diukur semata dari seberapa banyak kutipan atau quartile jurnal?
Scopus seharusnya membentuk pribadi yang bersih. Proses review yang panjang adalah suluk spiritual. Penolakan adalah cermin bahwa kita masih punya kekurangan. Revisi adalah pembersih hati. Ketika kita disuruh memperbaiki kesalahan ketik satu huruf pun, itu bagian dari proses pembersihan.
Dan pada akhirnya, ketika artikel kita terbit, itulah ujian berikutnya: apakah kita bisa menahan diri dari ujub dan riya. Di titik ini, hati-hati. Diseminasi hasil riset bisa dengan mudah berubah jadi pamer. Citra keilmuan bercampur dengan ego personal: akun Scopus, H-index, sitasi—semua jadi jebakan.
Dalam tradisi sufisme, orang yang paling tinggi maqam-nya justru yang paling rendah hatinya. Jalaluddin Rumi bilang, “Semakin penuh bejana, semakin tenang airnya.” Maka, semakin tinggi prestasi akademik, seharusnya semakin rendah hati.
Terbit di Scopus seharusnya jadi kewajiban ilmuwan biasa, bukan sesuatu yang diagung-agungkan. Jangan menilai pemilik akun Scopus sebagai manusia spesial. Jangan pula pemiliknya merasa spesial. Terus berkarya, dan bersikap biasa-biasa saja.
Jadikan artikel Scopus kita sebagai pancaran pribadi yang ingin menyumbang ilmu secara etis, dengan niat bersih, untuk kemaslahatan bersama. Biarkan Allah, Sang Maha Kreatif, yang membalasnya.
Namanya juga suluk. Terbit di Scopus itu lama, capek, penuh ujian, banyak menderita. Tapi bukankah suluk memang jalan yang mendaki?
Kampus yang sungguh-sungguh menuju predikat kelas dunia tak cukup hanya membangun gedung dan gelar, tapi harus mendidik dosennya untuk berani menempuh medan yang terjal: memilih jurnal yang ketat, bukan yang sekadar mudah terbit. Karena jalan pintas tak pernah menghasilkan perjalanan panjang yang berarti.