
Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
Petang itu, Jumat (02 Agustus 2024), ku duduk di serambi ndalem kasepuhan. Dan, di dalam rumah yang sangat dihormati sebagai kediaman peninggalan Hadlratusy Syekh KH Hasyim Asy’ari itu, sedang berkumpul sejumlah masyayikh. Termasuk pimpinan inti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Jelang pembukaan konferensi wilayah NU Jawa Timur. “Njenengan diminta untuk men-screening siapa pimpinan NU yang boleh masuk,” begitu perintah kuterima dari Mas Taufiq, asisten Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf. Maka, petang itu aku melaksanakan tugas untuk memilah siapa yang boleh dan tidak untuk masuk mengikuti rapat dengan masyayikh dan pimpinan PBNU itu.
Di tengah kutunaikan tugas itu, suara adzan isya’ pun memanggil. Berbondong-bondonglah para santri memenuhi masjid utama Pondok Pesantren Tebuireng itu. Mereka semua berkemeja serba putih. Bersarung. Dan tentu saja bersongkok. Khas santri pesantren di kalangan nahdliyin. Dalam waktu beberapa menit saja, masjid pun sudah hampir penuh. Tanpa dikomando, para santri itu memenuhi shaf depan terlebih dulu. Baru kemudian shaf di belakangnya. Begitu pula seterusnya. Sehingga mereka tampak tertib sekali. Sangat rapi. Barisan jama’ah pun terlihat sangat teratur karenanya.
Ada pemandangan menarik yang kudapati. Saat semua melaksanakan shalat isya’ secara berjamaah, ada beberapa orang yang berdiri siaga di bagian paling belakang masjid. Mereka adalah santri senior yang sedang mendampingi dan mengawasi santri-santri lainnya melaksanakan ibadah shalat isya’ berjamaah itu. Di antara mereka yang berdiri itu, ada satu lelaki dewasa awal yang memegang sapu pel. Di sisinya tersedia sebotol air bersabun. Semacam sanitiser begitulah. Lalu, lelaki itu menaburkan air bersabun itu ke sejumlah bagian lantai masjid. Selanjutnya, dia lakukan pembersihan lantai masjid itu. Selesai satu sisi, dia bergerak ke sisi lainnya.
Kuamati terus lelaki dewasa awal itu. Saat semua santri melaksanakan shalat jamaah isya’, dia berkhidmat untuk membersihkan lantai masjid itu. Sesekali dia berhenti, mengamati para santri melaksanakan ibadah shalat berjamaah itu. Lalu, dia bergeser ke sisi-sisi lantai masjid yang kosong dari jamaah. Dia pun kemudian mengepel sisi-sisi lantai masjid itu. Hingga seluruh lantai masjid di bagian belakang tampak bersih dan enak dipandang. Bahkan diinjak pun terasa bersih sekali. Kaki tak ada kotor-kotornya.
“Pantesan tadi saat aku berada di serambi masjid itu, ada basah dikit-dikit. Lalu lantai sangat bersih. Adem dan enak dilewati. Karena tak kotor sama sekali,” gumamku dalam hati. Dan aku pun lalu menemukan jawabannya. Semua itu karena ada petugas khusus yang selalu ngepel lantai masjid. Bahkan tak hanya sembarang ngepel. Petugas itu juga menggunakan air bersabun untuk membersihkan dan mengepel lantai itu. Air bersabun itu berwarna merah jambu (pink) dan diletakkan ke dalam botol bekas air mineral, seperti tampak pada gambar di bawah ini.

Ternyata lelaki dewasa awal itulah yang melakukan tugas ngepel masjid itu. Dia menjaga kebersihan lantai masjid. Dengan komitmen yang tinggi sekali. Bahkan, dia pun tetap siaga untuk mengepel lantai masjid utama Pondok Pesantren tebuireng itu walaupun dia harus merelakan waktu shalat berjamaahnya bersama para santri lainnya terlewat. Itu bukti komitmennya yang tiada tara. “Pantes saja lantai masjid itu sangat bersih, karena ada petugas khusus yang selalu siap siaga dengan sapu pel dan air bersabun untuk mengepel lantai masjid itu.” Begitu simpulku pada jawaban terhadap rasa penasaranku atas bersihnya lantai masjid itu.
Melihat pemandangan menarik di masjid utama Pondok Pesantren Tebuireng itu, ingatanku melayang jauh ke Masjidil Haram. Ada pasukan kebersihan yang selalu siap siaga menjaga kebersihan masjid. Bahkan, mereka tidak bergerak sendirian. Melainkan berkelompok. Dalam kelompok itu, para petugas kebersihan membagi diri ke dalam tugas kecil. Ada yang membawa alat pel. Bahasa popularnya, mopping machine. Ada juga yang membawa air bersabun. Ditempatkan dalam jerigen. Dan ada lainnya yang melaksanakan kerja pengepelan lantai masjid. Dari satu sisi ke sisi lainnya. Hasilnya? Semua lantai Masjidil Haram bersih sekali. Tak ada kotor-kotornya. Masjid utama Pesantren Tebuireng di atas juga sama begitu.
Akupun tertegun. Pikiranku melayang. Membayangkan lelaki yang bertugas membersihkan dan menjamin kebersihan lantai masjid utama Pondok Pesantren Tebuireng di atas telah melakukan materialisasi dari konsep bersih yang membersihkan (atau thahir muthahhir). Bukan saja bersih pada dirinya, tapi sekaligus membersihkan sekitarnya. Dalam Bahasa Arab, kata thahir dan muthahhir terbentuk dari akar kata (atau jidzrul kalimah; atau base word) yang sama, yakni, “th” (ط), “h” (ه), dan “r” (ر). Akar kata tersebut kemudian membentuk sebuah kata kerja (fi’l) yang bisa berwujud thahura (dalam pola tsulatsi mujarrad; tiga huruf semata) dan thahhara (dalam pola tsulatsi mazid; tiga huruf bertambahan).
Kata thahir adalah bentuk ism fa’il yang secara derivatif berasal dari fi’l atau kata kerja thahura (artinya “bersih”). Kata kerja thahura sendiri masuk ke dalam kategori fi’l lazim. Kata kerja intransitif. Yakni kata kerja yang untuk memiliki dan menunjukkan maknanya tak butuh obyek (maf’ul bih). Maknanya biasanya kembali kepada relasi antara kata kerja (fi’l) itu dan agensinya (fa’il). Kalimat yang sangat popular dalam kajian gramatikal Arab yang berbunyi “Ja’a Zaid” adalah contoh partikular lainnya. Terjemahannya, Zaid datang. Nah, makna itu muncul dalam relasi antara kata kerja “ja’a” dan agensinya “Zaid”. Makna “Zaid datang” bisa langsung terbentuk dari relasi antara kata kerja “ja’a” dan agensinya “Zaid” itu, dan tak harus butuh lainnya.
Berbeda halnya dengan kata muthahhir. Kata ini merupakan ism fa’il yang terbentuk dari fi’l atau kata kerja thahhara (artinya “membersihkan”). Meskipun asalnya saat berwujud thahura termasuk kategori fi’l lazim, kata kerja tersebut bisa diubah untuk menjadi fi’l muta’addi atau kata kerja transitif dengan mengubah polanya menjadi thahhara, seperti disebut sebelumnya. Dengan perubahan pola menjadi thahhara itu, kata kerja tersebut untuk bisa memiliki dan menunjukkan kesempurnaan maknanya memerlukan adanya obyek atau maf’ul bih. Orientasi maknanya keluar dari cakupan diri agensinya.
Mirip dengan kata kerja thahhara yang merupakan hasil perubahan berbasis jenis kata tsulatsi mazid dari fi’l lazim, kata kerja lain dalam Bahasa Arab yang masuk ke dalam kategori transitif atau fi’il muta’addi namun terambil dari tsulatsi mujarrad adalah dlaraba (artinya “memukul”). Kalimat yang sering dicontohkan dalam berbagai karya gramatikal Arab berbunyi “Dlaraba Zaid ‘Amran”. Artinya “Zaid memukul ‘Amran”. Kata kerja dlaraba ini masuk kategori fi’il muta’addi yang untuk kesempurnaan maknanya membutuhkan obyek, meskipun jenisnya tsulatsi mujarrad atau tiga huruf semata.
Aha!!! Dengan mengaitkan kisah lelaki pembersih lantai masjid utama Pondok Pesantren Tebuireng dengan uraian gramatikal di atas, aku pun lalu terpanggil untuk melakukan refleksi diri. Bayanganku, lelaki bersama tugas yang dilakukan di masjid utama Pondok Pesantren Tebuireng itu adalah figurisasi atas integritas diri dalam penunaian amanah publik. Lalu, apa pelajaran yang bisa diambil dari keberadaan lelaki petugas bersih-bersih dan kerja pembersihannya pada lantai masjid itu? Aku mencatat ada empat pelajaran penting dalam kaitan itu.
Pertama, bagaimanapun, harus ada orang yang punya visi, peran, dan kontribusi besar bagi terjaganya ruang publik yang baik dan bersih. Orang dengan karakter seperti ini terefleksikan dalam tindakannya. Lebih teknis lagi, orang dimaksud merealisasikan karakter tersebut dalam penunaian tugas dan kewajibannya di tengah-tengah yang lain. Tentu makin banyak orang dengan karakter tersebut, makin baik pula bagi kehidupan bersama. Tapi hadirnya seseorang yang memiliki memiliki visi, peran, dan kontribusi besar bagi terjaganya ruang publik yang baik dan bersih adalah awal yang baik bagi penciptaan komunitas kebajikan serupa. Karena, yang dibutuhkan untuk terciptanya komunitas kebajikan dimaksud adalah adanya role model. Untuk lahirnya role model ini,hadirnya figur yang memiliki karakter dimaksud adalah prasyarat awal saja.
Bahkan, dalam tataran tertentu, figur dimaksud melakukan sacrifice atau pengorbanan untuk menjadi “tukang bersih-bersih” di tengah kehidupan masyarakat. Lelaki dewasa awal yang bertugas mengepel lantai masjid utama Pesantren Tebuireng di atas rela tidak ikut serta melaksanakan shalat isya’ dalam jamaah yang sedang dilangsungkan di masjid itu. Dia lebih berkomitmen untuk menjaga kebersihan masjid. Dia rela melakukan shalat jamaah isya’ di luar jamaah itu. Tentu itu adalah bentuk sacrifice dimaksud. Tentu itu adalah wujud pengorbanan itu. Bukan untuk dirinya. Tapi untuk kebersihan dan kenyamanan semua jemaah yang ada di masjid itu.
Dia lakukan semua itu untuk menjaga bersihnya ruang publik (public sphere). Yakni, ruang yang, dalam definisi standarnya, menjadi tempat orang-orang atau individu-indvidu yang berbeda-beda dalam gugusan individu untuk dapat berkumpul, berbincang, bermusyawarah, dan berbagi apa saja yang mengenai diri mereka. Ada kebebasan berekspresi di dalam ruang itu. Hingga Habermas (The Structural Transformation of the Public Sphere, 1991:33-34) sebagai pengembang teori itu pun mengilustrasikan situasi salon di Perancis sebagai salah satu contoh di mana “pikiran tidak lagi melayani atasan (patron)” dan “opini menjadi terbebas (emancipated) dari ikatan ketergantungan ekonomi (the bonds of economic dependence).”
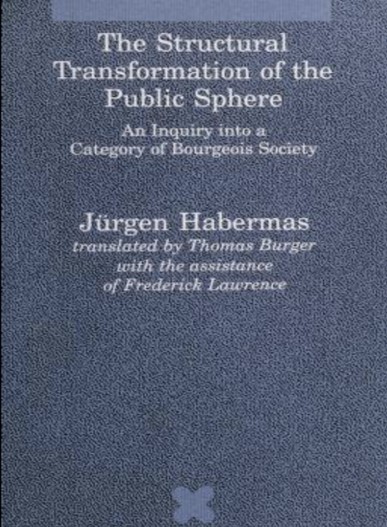
Kedua, bersih saja tak cukup. Harus disempurnakan dengan membersihkan. Itu karakter role model kebajikan di ruang publik. Meminjam bahasa thaharah atau bersuci, tak selalu air yang suci (thahir) itu menyucikan (muthahhir). Untuk kepentingan bersuci, air yang dibutuhkan bukan hanya yang suci tapi sekaligus juga menyucikan. Dalam bahasa nilai integritas, bukan hanya orang yang bersih yang dibutuhkan publik. Tapi orang yang bersih dan sekaligus memiliki kapasitas untuk membersihkan. Apa saja yang dibersihkan? Ya apa saja dalam dirinya dan lingkungannya yang bisa mengotori ruang publik.
Itu karena, cakupan nilai suci itu baru berorientasi internal. Nilai kemanfaatannya terbatas untuk diri pemiliknya. Hanya untuk diri sendiri. Tapi, kalau nilai menyucikan, orientasinya ke dalam dan keluar. Bahkan, orientasi keluarnya bisa lebih kuat daripada orientasi ke dalam diri sendiri. Karena orang yang menjadi figur muthahhir (karakter menyucikan) pasti lebih ingin menunjukkan kelebihan dirinya dengan memberikan nilai kemanfaatan yang besar kepada lingkungannya.
Hanya, untuk bisa sampai kepada derajat menyucikan, memang syaratnya seseorang harus suci terlebih dulu. Tak akan bisa memiliki kapasitas untuk menyucikan jika diri sendiri tak suci. Tak akan bisa memiliki kemampuan untuk membersihkan jika diri sendiri tidak bersih. Maka, jangan pernah bermimpi untuk memiliki derajat kecakapan untuk menyucikan saat diri tak atau belum suci terlebih dulu. Karena itulah, karakter menyucikan datang sebagai proses ekspansi dari kapasitas suci dalam diri.
Ketiga, membersihkan itu tak bisa dilakukan sendirian. Harus ada dukungan bersama. Bentuknya, harus dilakukan secara bersama-sama dengan selainnya. Karena itu, tahapan lanjutan dari kebutuhan untuk menciptakan kapasitas membersihkan adalah diperlukannya ekosistem sosial kebajikan bagi tumbuhnya karakter bersih yang membersihkan itu. Figur bersih yang membersihkan, seperti diuraikan pada poin pertama sebelumnya, memang sangat dibutuhkan untuk menjadi role model kebajikan bagi terciptanya ruang publik yang bersih. Tapi, untuk kepentingan maksimalisasi hasil, ekosistem sosial kebajikan bagi tumbuhnya karakter bersih yang membersihkan itu menjadi kebutuhan yang cenderung mutlak.
Mengapa begitu? Nilai persis dengan biji. Ia butuh lahan subur untuk tumbuh dengan baik. Bercocok tanam yang baik harus diawali dengan pemilihan lahan subur yang baik. Karena, lahan subur yang baik menjadi modal bagi cocok tanam. Lalu, keterampilan menanam menjadi modal berikutnya. Kecakapan untuk memilih pupuk dan melakukan pemupukan adalah bagian sentralnya. Termasuk kecakapan untuk melindungi biji yang telah ditanam dari serangan hama. Itu semua adalah ekosistem cocok tanam yang baik.
Serupa dengan cocok tanam, nilai karakter bersih yang membersihkan juga membutuhkan ekosistem sosial kebajikan. Ia butuh lahan subur, keterampilan menanam, kecakapan memilih pupuk dan melakukan pemupukan, serta kecakapan perlindungan nilai karakter bersih yang membersihkan dari serangan perihal yang bisa mengotorinya. Itu artinya, karakter bersih yang membersihkan tak cukup dilakukan sendirian. Perlu ekosistem sosial kebajikan untuk proses tanam dan penguatan nilai karakter itu agar kuat hidup dan berkembang di tengah masyarakat.
Keempat, agar nilai bersih bisa bergerak untuk berkapasitas membersihkan, dibutuhkan seperangkat alat untuk mendorong dan merealisasikannya. Persis seperti lelaki yang bertugas membersihkan dan mengepel lantai masjid utama Pondok Pesantren Tebuireng dengan menggunakan air bersabun seperti dijelaskan di awal tulisan ini. Karena itu, maka nilai bersih yang membersihkan harus mendapatkan instrumentasi. Karena untuk bisa sampai pada derajat dan memiliki kapasitas membersihkan, nilai bersih tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Ia butuh alat untuk menggerakkannya.
Nah, jabatan dan atau kewenangan publik memang amanah. Itu nilai spiritual yang melekat padanya. Tapi, dari sisi posisi strategis yang dimiliki, jabatan dan kewenangan publik adalah alat atau instrumen penting yang bisa menggerakan nilai bersih untuk bisa memiliki kapasitas membersihkan. Tentu dengan tujuan untuk menujukkan nilai kemanfaatannya yang besar nan luas ke luar diri pribadi. Karena itulah, sangat lacur jika ada pemegang amanah publik gagal menerjemahkan prinsip bersih yang membersihkan. Sangat ironis jika ada orang yang sedang diberi jabatan gagal menunaikan posisi strategisnya untuk menciptakan dan memperkuat bersihnya ruang publik, di antaranya karena dia sendiri gagal menjadi pribadi yang bersih.
Keempat pelajaran penting di atas saling berkelindan untuk menunjuk kepada adanya integritas diri. Bagian sentral dari integritas itu adalah nilai kemanfaatan yang ditebarkan ke luar diri. Maka, bersih yang membersihkan bukanlah slogan yang hanya manis untuk dibicarakan dan dikampanyekan. Ia adalah nilai hidup yang harus ditunaikan. Agar hidup penuh kemaslahatan. Setiap nafasnya dipenuhi dengan keberkahan. Karena pelakunya selalu hadir dengan nilai kemanfaatan. Yakni nilai positif hidup yang bukan hanya dirinya saja yang mengharapkan. Tapi juga masyarakat luas yang selalu merindukan.
















