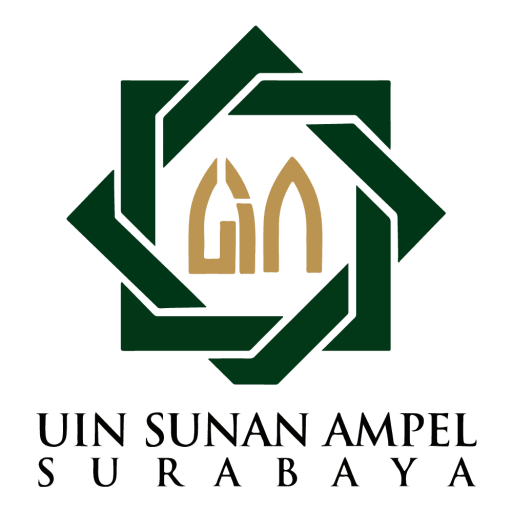Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
Seseorang bertanya kepadaku, “Mana yang lebih sulit, menciptakan sistem atau membangun mentalitas baru?” Pertanyaan itu dia munculkan usai membaca tulisanku sebelumnya yang berjudul Setelan Pabrik (lihat URL: https://uinsa.ac.id/blog/setelan-pabrik). Kala itu, yang mengilhami tulisanku yang kusebut terakhir itu adalah pertanyaan seorang kawan yang lain juga. Seperti kutulis di paragraf pembuka tulisanku sebelumnya itu, begini pertanyaan seorang kawan itu kala itu: “Apa yang paling sulit dalam pengalaman Anda memimpin beragam lembaga?” Pertanyaan itu lalu kontan kujawab: “Membangun mentalitas baru.”
Nah, pertanyaan “Mana yang lebih sulit, menciptakan sistem atau membangun mentalitas baru?” di paragraf awal tulisan ini lahir sebagai respon lanjutan atas pertanyaan sebelumnya pada tulisanku sebelumnya itu juga. Mendengar pertanyaan itu, aku pun kala itu langsung teringat Hadits Nabi ini: Bu’itstu li utammima makarim al-akhlaq.” Begini terjemahannya: “Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlaq [manusia].” Begitulah Nabi mengajarkan tentang pentingnya akhlaq mulia. Dan, akhlaq mulia inilah yang kini juga dikenal dengan nama lain: mentalitas mulia.
Maka, meminjam ungkapan hikmah kenabian itu, istilah makarim al-akhlaq menunjuk kepada mentalitas mulia itu. Maka pula, kehadiran Nabi Muhammad SAW di tengah umat berurusan dengan penyempurnaan mentalitas baru ke arah yang lebih mulia. Anggitan ini diilustrasikan dalam Hadits di atas dengan kata li utammima yang berarti “untuk menyempurnakan”. Penggunaan diksi ini di antaranya untuk menegaskan bahwa setiap diri memiliki mentalitas tersendiri. Karena bagaimanapun kondisinya, setiap diri sudah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial dan budaya tersendiri sejak dari dini. Dan, mentalitas itu lahir dari lingkungan sosial dan budaya dimaksud. Karena itu, peran penyempurnaan mentalitas dari kehadiran Nabi Muhammad SAW seperti yang disebut dalam Hadits di atas bisa dalam bentuk mengoreksi, memperbaiki, dan bahkan mambangun ulang.
Karena itu, terhadap pertanyaan seperti yang kukutip di awal tulisan di atas, aku pun langsung menunjuk ke Hadits Nabi tersebut sebagai inspirasi jawaban. Mengapa kontan dan langsung kuingat Hadits itu? Karena yang kudapati dalam pengalaman penyelenggaraan jabatan publik tak jauh-jauh dari substansi Hadits itu. Bahkan, substansi sentralnya cenderung persis, seperti yang dikandung oleh redaksi Hadits dimaksud. Sehingga, dari pengalaman praktis lapangan itu, aku pun semakin paham rahasia di balik redaksi Hadits dimaksud. Ada substansi dasar tapi bersifat hulu bagi penciptaan ruang publik yang baik. Yakni, mentalitas diri.
Untung Ada Agama!
Mentalitas diri memang soal nilai. Dan sumber nilai bisa apa saja. Beragam rupa. Sebut saja beberapa di antaranya. Ada keluarga. Ada pula masyarakat umum. Atau bahkan kini ada media sosial. Bisa pula adat. Bisa juga gabungan dari semua itu. Tapi, agama masih menjadi sumber nilai utama. Dan karena itu, agama harus mendasari setiap bangunan mentalitas diri. Sebab, bukan saja agama selalu melakukan abstraksi aspek material hidup, melainkan juga mengajari kita semua untuk bergerak visioner dan berorientasi jangka panjang. Kepentingan jangka pendek memang tak dinafikan, tapi kepentingan jangka panjang menjadi orientasi utama. Visi dan orientasi jangka panjang ini menjadi nilai dasar hidup dari ajaran agama.
Di sinilah, perlu disebut: “Untung ada agama!” Karena, agama membawa ajaran tentang nilai itu. Dan nilai itu menjadi tuntunan hidup yang mulia. Maka, hidup tak akan pernah tersungkur jika agama menjadi sumber nilai kehidupan. Tugas pemimpin publik memang melakukan teknokrasi atas nilai itu (lihat tulisanku sebelumnya “Adab di Atas Jabatan”, URL: https://uinsa.ac.id/blog/adab-di-atas-jabatan). Kepentingannya agar nilai bisa efektif sebagai moral publik melalui praktik penciptaan tata kelola yang baik. Tapi tugas semua diri adalah untuk selalu dekat dengan nilai yang dipesankan oleh agama. Karena itu, jauh dari agama sama dengan menjauhkan diri dari kemuliaan. Jika itu yang terjadi, maka engkau sama saja dengan menjauhkan diri dari mentalitas mulia.
Mungkin ada yang bertanya kritis atau bahkan nyinyir seperti ini: “Aah, bener nih agama berperan untuk menjaga kemuliaan di ruang publik?” Apalagi biasanya pertanyaan julid ini dibarengi dengan penyajian pengalaman lapangan bahwa banyak kaum beragama yang terjerat praktik pengkhianatan amanah. Pertanyaan-pertanyaan yang kritis demikian ini sah-sah saja. Karena memang tantangan kaum beragama adalah saat muncul kontras antara keyakinan dan praktik riil di lapangan. Saat yang terjadi dalam fakta lapangan semakin jauh dari nilai keyakinan yang diajarkan agama yang diyakini, maka efektifivitas nilai agama menjadi pertanyaan besar.
Namun, pertanyaan-pertanyaan kritis di atas harus disertai dengan argumen balikan begini: yang beragama dan berkeyakinan kuat saja bisa tersungkur, apalagi yang tidak atau minimal jauh darinya. Tentu saja, potensi tersungkurnya bagi yang disebut terakhir jauh lebih besar. Karena itu, tetap saja nilai agama penting. Tetap saja bisa dikatakan “Untung ada agama!” seperti kusebut sebelumnya. Problemnya bukan pada agama itu sendiri. Tapi, pada pelaku agama yang perilakunya berlawanan, menyimpang, atau bahkan mengkhianati nilai yang diajarkan agama yang diyakini.
Di sini, nasehat Nabi Muhammad SAW menggariskan standar nilai yang penting: لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ. وَ لاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ. وَ لاَ يَشْرَبُ اْلخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ. Begini terjemahannya: “Tidaklah berzina seorang yang berzina ketika dia berzina itu dalam keadaan iman. Dan tidaklah mencuri seorang pencuri ketika mencuri itu dalam keadaan iman. Dan tidak pula seorang peminum khamr (minuman keras) ketika meminumnya itu dalam keadaan iman.” Hadits ini mengirimkan pesan penting bahwa standar keimanan seseorang bisa diukur dari perilakunya. Klaim keimanan tak berarti apa-apa saat praktik riilnya dalam keseharian tak menunjukkan sama sekali nilai keimanan itu. Maka, Hadits ini menggariskan pentingnya sinkronisasi antara keyakinan dan praktik nyata. Sebab, pada kondisi sinkron itulah terletak mentalitas diri.
Kapan Mentalitas Runtuh?
Pertanyaannya adalah, kapankah mentalitas diri runtuh ke dalam keburukan, atau bahkan kejahatan? Jawabannya adalah: saat ada vested interest yang menguat atas kepentingan umum. Istilah vested interest ini menunjuk kepada kuatnya kepentingan personal atas sebuah amanah publik. Kepentingan personal ini berarti kepentingan internal diri sendiri atau keluarga. Bisa saja ada unsur lain di luar keluarga yang masuk, tapi semuanya demi keuntungan dan kepentingan personal dimaksud. Kepentingan personal ditempatkan di atas segalanya. Bahkan, bisa menendang jauh kepentingan umum. Padahal jabatan yang dipegangnya adalah konsekuensi dari amanah publik yang harus ditunaikan untuk kepentingan umum.

Adapun frase “amanah publik” yang disebut di paragraf di atas bisa berupa jabatan fungsional, dan bisa pula jabatan struktural. Bisa di instansi pemerintahan. Bisa pula di luar instansi pemerintahan. Hanya, tentu instansi pemerintahan adalah contoh paling mudah untuk menunjuk tempat bersemayamnya amanah publik itu. Intinya adalah bahwa semua jabatan yang diamanahkan oleh negara atau publik masuk ke dalam kategori amanah publik dimaksud. Maka, saat menjabat atau sedang memegang jabatan, siapapun berarti sedang mengemban amanah publik. Menunaikan jabatan berarti memuliakan amanah publik. Mengkhianatinya berarti mencederai amanah publik itu.
Dalam konteks inilah terletak argumen mengapa kebijakan publik harus menyusu kepada kebajikan umum. Contoh paling konkret adalah kebijakan yang bisa dirumuskan seperti berikut ini: “Jangan pernah melakukan kesalahan pada tiga hal: keuangan, kepegawaian, dan main perempuan!” Mengapa tiga hal ini menjadi isu sentral? Jawabannya sederhana. Karena ketiganya menjadi indikator paling konkret mengenai integrity. Penciptaan kebajikan umum mempersyaratkan integrity ini sabagai komponen pembentuk utamanya. Indikator konkretnya adalah terjauhkannya kesalahan pada tiga bidang tersebut dari praktik penyelenggaraan amanah publik.
Konsep integrity itu sendiri menunjuk kepada satunya kata dan perbuatan “dalam kebajikan”. Frase “dalam kebajikan” ini harus dimasukkan ke dalam rumusan mengenai integrity ini karena masih terbukanya peluang bagi kondisi satunya kata dan perbuatan tapi konteks dan kepentingannya justru dalam keburukan atau kejahatan. Dengan kata lain, tak semua kondisi satunya kata dan perbuatan selalu berada dan menunjuk kepada kebajikan. Tentu “kebajikan” yang dimaksudkan oleh konsep integrity di sini melampaui kebajikan personal dengan menunjuk kepada kebajikan umum.
Lalu Tugas Kita Apa?
Maka, ada dua tugas penting yang harus ditunaikan oleh masing-masing individu dalam usaha untuk terciptanya kebajikan umum. Tentu konteksnya adalah dalam kehidupan bersama. Pertama, jangan pernah menyepelekan perihal yang tampak kecil. Sebab, kecil saat dilakukan secara berulang, akan segera memunculkan kebiasaan. Saat kebiasaan sudah menjadi gerak dan nafas hidup, maka hidup tak akan bisa jauh-jauh dari kebiasaan itu. Jika sudah begitu, maka kebiasaan itu akan segera menjadi karakter. Saat kebiasaan itu buruk, maka yang menguat pada diri adalah karakter buruk. Sebaliknya, saat kebiasaan yang muncul baik, maka yang akan menguat pada diri seseorang adalah karakter baik.
Untuk itu, terjemahan konkret lanjutannya begini: Jangan menyepelekan kebajikan walaupun kebajikan itu mungkin atau tampak kecil. Karena meskipun kecil, kebajikan itu saat masing-masing individu sudah memberi atensi kepadanya akan membentuk jejaring kebajikan. Hanya soal waktu dan kesempatan, jejaring kebajikan itu akan menguat. Saat sudah menguat, maka jejaring kebajikan itu akan segera membentuk ekosistem kebajikan. Nah, saat ekosistem kebajikan sudah terbentuk, kebajikan publik tercipta dengan sendirinya. Dan begitu pula yang terjadi pada keburukan. Jangan pula menyepelekan keburukan walaupun keburukan itu mungkin atau tampak kecil. Alasan logis dan argumen prosesnya sama dengan uraian kebajikan di atas.
Intinya adalah bahwa kebajikan atau keburukan pasti dimulai dari ukuran dan atau skala yang kecil. Dalam ungkapan lainnya, mentalitas diri dimulai dari yang kecil. Setiap diri hendaknya tidak mengesampingkan nilai yang tampak kecil. Ukuran dan skala yang kecil itu akan membesar saat dipraktikkan dalam perilaku secara berulang. Apalagi, perilaku itu lalu mengundang ke dalamnya keterlibatan banyak pihak. Maka, hasilnya sudah bisa ditebak: akan menguat sebuah mentalitas diri. Jika nilainya buruk, maka buruk pulalah mentalitas diri itu. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, jika tak mampu berbuat kebajikan dalam amanah publik, jangan menyebar keburukan kepada yang lain. Kepentingannya agar institusi tak terjerembab ke dalam kubangan keburukan oleh mentalitas buruk individu-individu di dalamnya.
Tugas kedua, jangan pernah berhenti pada penciptaan sistem tata kelola semata. Alih-alih, sempurnakan dengan pembangunan mentalitas mulia. Dulu memang aku meyakini pentingnya sistem. Pentingnya bekerja by system. Sebab, yang dipersandingkan adalah bekerja by person. Tapi, kini setelah menjalani amanah sebagai pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang mengelola puluhan ribu mahasiswa dan seribuan pegawai, pilihan bekerja by person dan bekerja by system tak lagi memadai. Tak lagi mencukupi. Tak lagi bisa dipertahankan sebagai pilihan yang ideal. Sebab, transformasi dari bekerja by person ke bekerja by system masih menyisakan satu persoalan lagi. Aku menyebutnya “persoalan” karena posisinya justru bisa membuat sistem menjadi idle. Bisa membuat sistem menjadi lumpuh. Minimal ngadat.
Nah, satu persoalan dimaksud adalah mentalitas diri. Ya, mental kerja yang dimiliki oleh semua yang berada dalam cakupan struktur pengelolaan tugas pekerjaan. Bekerja by person memang memiliki kelemahan mendasar. Tata kelola model itu membuat ketergantungan pada sosok pemimpin terlalu besar. Saat sosok pemimpin itu ada di lokasi pekerjaan, penunaian tugas pekerjaan oleh para pegawai bisa tinggi. Saat tidak, lumpuh pulalah penunaian tugas pekerjaan itu. Tentu, tata kelola seperti ini sangat bermasalah bagi ikhtiar membangun mutu kerja dan capaian kinerja sebuah institusi.
Sebagai respon atas kelemahan itu, bekerja by system menjadi sebuah tawaran solusi atas tata kelola yang lebih baik. Dengan tata kelola model yang demikian, sebuah institusi tak lagi mengandalkan kehadiran sosok pimpinan. Tak bergantung pada figur pimpinan. Sebab, figur dan sosok pimpinan itu sudah dilembagakan ke dalam sebuah sistem yang dibangun untuk mewadahi kepentingan transformasi tata kelola ke arah yang lebih baik itu. Pada titik inilah, bekerja by system bisa diharapkan menjadi solusi atas tata kerja yang baik dan efektif yang gagal dipenuhi oleh model tata kerja by person.
Juga, dulu aku meyakini betul pentingnya bekerja by system di atas sebagai respon aktif terhadap model tata kelola kerja by person di atas. Tapi, kini usai mengalami sendiri amanah jabatan sebagai pemimpin tertinggi sebuah lembaga besar yang bernama perguruan tinggi, model tata kelola pekerjaan by person dan by system tersebut harus disempurnakan kembali. Harus dilakukan perbaikan agar tercipta penyempurnaan. Karena ternyata, ikhtiar terukur hingga sampai pada model tata kelola pekerjaan by system pun masih bisa tertawan. Masih bisa lumpuh. Masih bisa terhenti.
Lalu, apa dan bagaimana yang harus dilakukan untuk menyempurnakan model tata kelola pekerjaan by person dan by system di atas? Ini jawabannya: Pembangunan mentalitas kerja nan mulia. Mentalitas kerja nan mulia ini memang ada urusannya dengan by person. Tapi, sejatinya, mentalitas kerja itu merupakan hasil gabungan dari substansi tata kelola pekerjaan by person dan by system. Ia bisa juga disebut sebagai level ketiga setelah model tata kerja by person dan by system. Sebab, mentalitas mulia memang berurusan dengan person, tapi keberadaannya harus kompatibel dengan kerangka yang dibangun untuk beroperasinya tata kelola by system secara efektif.
Argumennya sederhana. Mentalitas kerja bisa membuat sistem bekerja dengan maksimal. Juga bisa membuat sistem itu terhenti, tertawan, dan bahkan lumpuh. Saat mentalitas rapuh, sistem yang telah diciptakan untuk tata kelola tugas dan pekerjaan by system itu tidak akan berjalan efektif. Mentalitas kerja yang demikian telah terdesak oleh cara kerja by person yang terlalu mengemuka. Saat mentalitas kerja yang mulia, tinggi, dan kuat berkembang baik pada setiap diri, maka tata kelola tugas dan pekerjaan by system tersebut akan dapat berjalan dengan efektif.
Mengubah Mentalitas
Karena itu, orang modern bilang: Success is not changing the reality, it is changing mentality behind reality. Sukses itu bukan soal mengubah realitas, melainkan soal mengubah mentalitas di balik realitas. Mengubah realitas bisa dengan menciptakan sistem. Dan bisa saja hal itu disebut sebuah kesuksesan. Tapi sukses yang demikian tak akan bisa bertahan lama jika mentalitas di balik realitas itu tak ikut serta berubah. Karena itu, mengubah mentalitas diri ke arah yang lebih baik menjadi tugas tersisa setelah mengembangkan model tata kelola by system. Tentu, membangun mentalitas baru dimaksud dilakukan dengan menyusu kepada kebajikan umum. Mengingat sistem dibutuhkan untuk menjamin tercapainya kebajikan umum, maka mentalitas diri yang dikembangkan juga harus berorientasi sama.
Di sinilah, mentalitas mulia mempersyaratkan kebajikan umum dinomorsatukan dari selainnya. Meminjam bahasa ushul fiqh, al-maslahah al-‘ammah harus ditempatkan di atas segalanya dari al-maslahah al-fardiyah. Dalam ungkapan orang Barat, civic virtues harus diposisikan di atas private virtues. Prinsip itu harus ditegakkan untuk menjauhkan diri dari runtuhnya mentalitas ke dalam kubangan keburukan dan kejahatan. Menguatnya kepentingan personal atau vested interest menandai awal dari keruntuhan mentalitas diri itu. Atas dasar itu, tata kelola by person memang penting ditingkatkan ke level yang lebih tinggi melalui penciptaan tata kelola by system. Tapi, semua itu baru akan bisa sempurna saat pembangunan mentalitas diri nan mulia bisa mencapai kata tuntas.