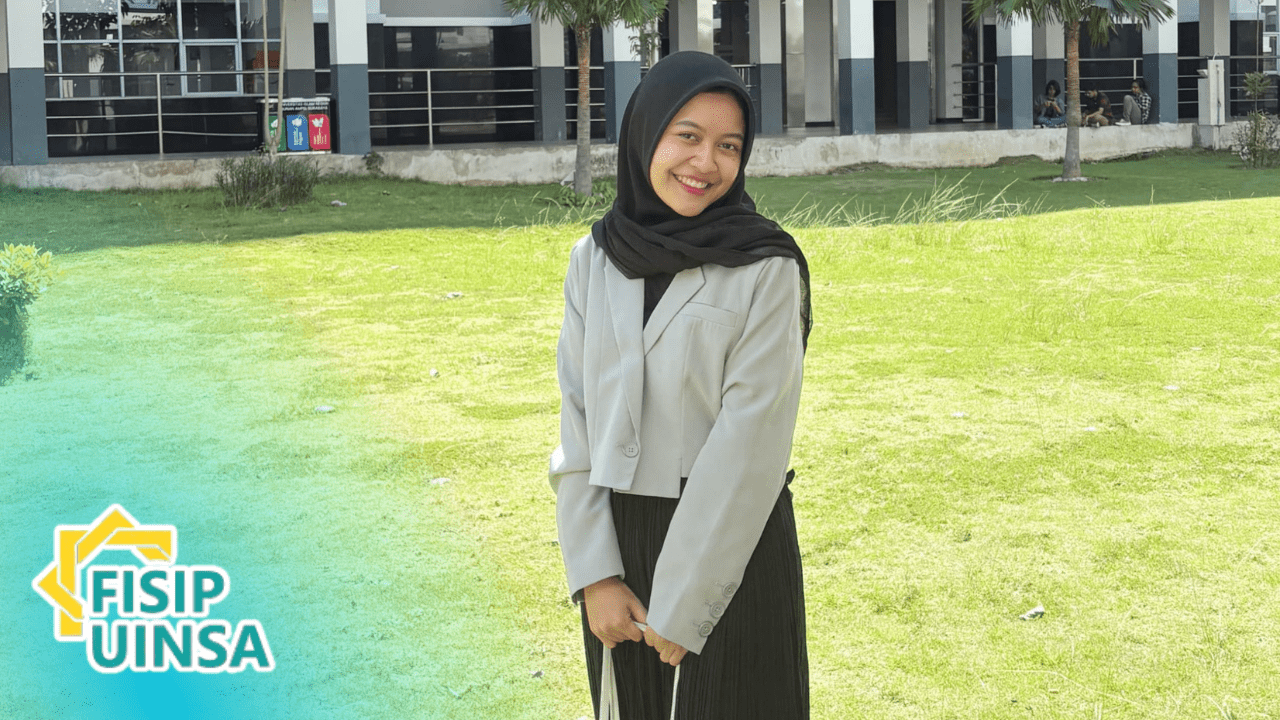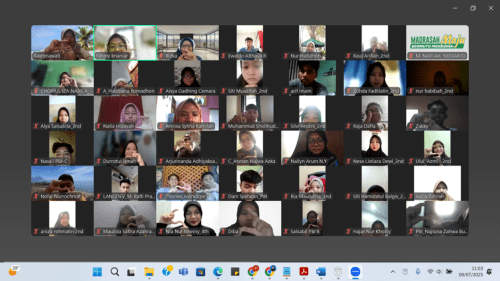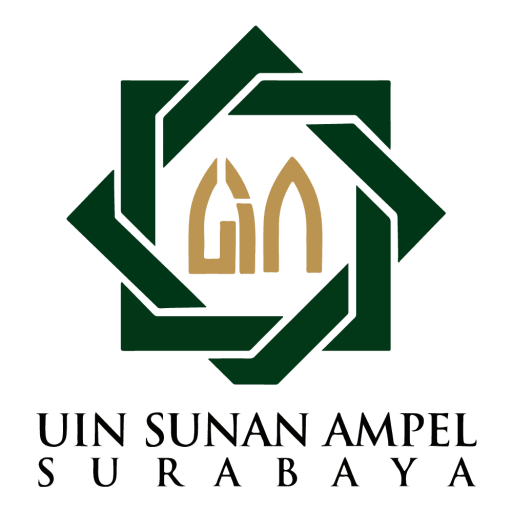Oleh: Dinda Ayu Sa’ada Tillah
Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah berlangsung sejak lama di berbagai belahan dunia. Beragam upaya telah ditempuh oleh pemerintah guna menanggulangi persoalan ini. Salah satu strategi yang kerap digunakan adalah pemberian bantuan sosial (bansos). Bansos sendiri hadir dalam berbagai bentuk dan disalurkan kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu. Tujuan utama dari kebijakan ini ialah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan melalui bantuan ekonomi bersifat sementara.

Kendati bansos merupakan langkah positif dalam jangka pendek, kenyataannya tidak serta-merta menjadi solusi yang mampu mengatasi akar kemiskinan. Di sisi lain, implementasi bansos justru berpotensi melahirkan konflik baru, seperti ketegangan antarwarga dan ketimpangan dalam distribusi. Lebih dari itu, dalam praktiknya bansos seringkali dijadikan alat politik untuk meraup dukungan, terutama menjelang kontestasi pemilu. Sebagai contoh, distribusi bansos menjelang Pemilu 2024 meningkat secara drastis dibandingkan saat masa pandemi, yang menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas program ini dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. (Kompas.tv, 01/02/2024)
Ketergantungan masyarakat terhadap bansos kian menguat saat bantuan tersebut dianggap sebagai hak tetap, bukan sebagai dukungan sementara. Menurut teori strukturasi Anthony Giddens, masyarakat merupakan agen, sedangkan lingkungan sosial menjadi struktur yang memengaruhi perilaku. Dalam konteks bansos, kebijakan ini membentuk struktur sosial yang mendorong masyarakat untuk bersikap pasif dan menggantungkan diri kepada pemerintah. Jika bansos terus diberikan tanpa strategi pemberdayaan yang konkret, maka kemandirian masyarakat akan semakin luntur dan menghambat upaya mereka untuk memperbaiki kondisi hidup secara mandiri.
Hal ini menimbulkan siklus kemiskinan yang terus berulang. Ketika masyarakat tidak terdorong untuk berupaya secara mandiri dan hanya mengandalkan bantuan, maka peluang untuk keluar dari kondisi tersebut semakin kecil. Lama-kelamaan, situasi ini akan menyebabkan demotivasi, yaitu berkurangnya semangat dalam memperbaiki kehidupan karena terlalu bergantung pada bantuan dari luar. Imbasnya, produktivitas masyarakat menurun, daya saing terhadap pasar kerja menipis, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika ekonomi melemah.
Apabila pemberian bantuan sosial dilakukan terus-menerus tanpa adanya upaya pemberdayaan yang sistematis, maka data penurunan kemiskinan yang tercatat hanya bersifat semu. Badan Pusat Statistik (BPS) memang mencatat bahwa tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan menjadi 8,57 persen per September 2024, turun 0,46 persen poin dari Maret 2024 dan 0,79 persen poin dari Maret 2023. Namun, angka ini tidak bisa langsung diartikan sebagai keberhasilan dalam mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Yang dibutuhkan adalah peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, bukan ketergantungan terus-menerus terhadap bantuan.
Pernyataan ini juga ditegaskan oleh Menteri Sosial yang menyoroti meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap bansos. Ia menekankan bahwa rendahnya angka “graduasi” dari kondisi rentan menandakan adanya masalah dalam sistem yang ada, di mana masyarakat mulai kehilangan semangat untuk mandiri. (Kompas.tv, 12/11/2024). Hal ini menjadi indikator mundurnya capaian pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian. Fenomena ini juga tampak dalam dinamika politik menjelang Pemilu 2024, ketika salah satu pasangan calon mengusung program Makan Siang Gratis, yang mendapat perhatian luas dari masyarakat, terutama kalangan rentan yang menggantungkan harapan pada bantuan semacam ini.
Sayangnya, kebijakan populis semacam ini dapat berdampak pada pergeseran anggaran dari sektor penting lainnya. Contohnya, pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi belanja negara hingga Rp 306,7 triliun, di mana salah satu sektor yang terkena dampaknya adalah pendidikan (Kompas.com, 13/02/2025). Pengurangan anggaran pendidikan jelas akan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia, padahal kualitas SDM merupakan kunci penting dalam memutus rantai ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Selain itu, perlu dipahami bahwa kemiskinan di Indonesia hadir dalam berbagai bentuk. Pertama, kemiskinan absolut, yakni kondisi di mana pendapatan seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Kedua, kemiskinan relatif, yang terjadi ketika seseorang memiliki penghasilan di atas garis kemiskinan, namun masih jauh di bawah rata-rata standar hidup masyarakat sekitarnya. Kemiskinan jenis ini umumnya disebabkan oleh distribusi pembangunan yang tidak merata. Ketiga, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, budaya malas, rendahnya kreativitas, dan gaya hidup konsumtif. Terakhir, kemiskinan struktural, yang timbul karena ketimpangan akses terhadap sumber daya akibat ketidakadilan sosial, budaya, dan politik. (Darwis, 2022)
Semua bentuk kemiskinan tersebut membutuhkan pendekatan solusi yang tidak sekadar bersifat karitatif, melainkan lebih ke arah pemberdayaan yang komprehensif. Ketergantungan terhadap bansos yang digunakan untuk kepentingan politik harus dihentikan jika ingin menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif.
Beberapa penyebab kemiskinan di Indonesia antara lain adalah distribusi sumber daya yang timpang antara daerah perkotaan dan pedesaan, rendahnya kualitas pendidikan yang berimbas pada kemampuan kerja yang minim, tingginya angka pengangguran, serta budaya dan lingkungan sosial yang membentuk pola pikir pasif. Maka dari itu, pendekatan yang lebih berkelanjutan dan memberdayakan sangat diperlukan.
Rendahnya kemandirian masyarakat dapat diatasi dengan peran pihak eksternal, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, yang mampu menggali serta mendorong potensi masyarakat. Salah satu cara yang efektif adalah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan mereka secara mandiri. Strategi ini mencakup tiga aspek utama: enabling (menciptakan lingkungan pendukung), empowering (memperkuat kapasitas masyarakat), dan protecting (melindungi kelompok rentan).
Lebih lanjut, kewirausahaan sosial juga menjadi solusi yang menjanjikan karena memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Konsep ini diperkenalkan oleh Bill Drayton melalui organisasi Ashoka, yang menekankan bahwa tujuan kewirausahaan sosial bukan hanya keuntungan ekonomi, tetapi juga manfaat sosial. Contohnya, usaha kecil berbasis keterampilan lokal seperti kerajinan, olahan pangan, atau produk pertanian yang bernilai tambah. Strategi ini relevan dengan teori strukturasi Giddens, di mana masyarakat tidak hanya tunduk pada struktur sosial, tetapi juga bisa menjadi agen perubahan yang membentuk ulang struktur itu sendiri.
Kesimpulannya, pengentasan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan distribusi bansos semata. Yang lebih penting adalah menciptakan sistem pemberdayaan yang mendorong masyarakat untuk mandiri dan berdaya saing. Pemerintah harus mengarahkan fokusnya pada penguatan pendidikan, keterampilan, dan peluang ekonomi sebagai pilar utama untuk menciptakan masyarakat yang benar-benar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. (ed. FyP)
Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Sosiologi semester 2 FISIP UINSA Surabaya