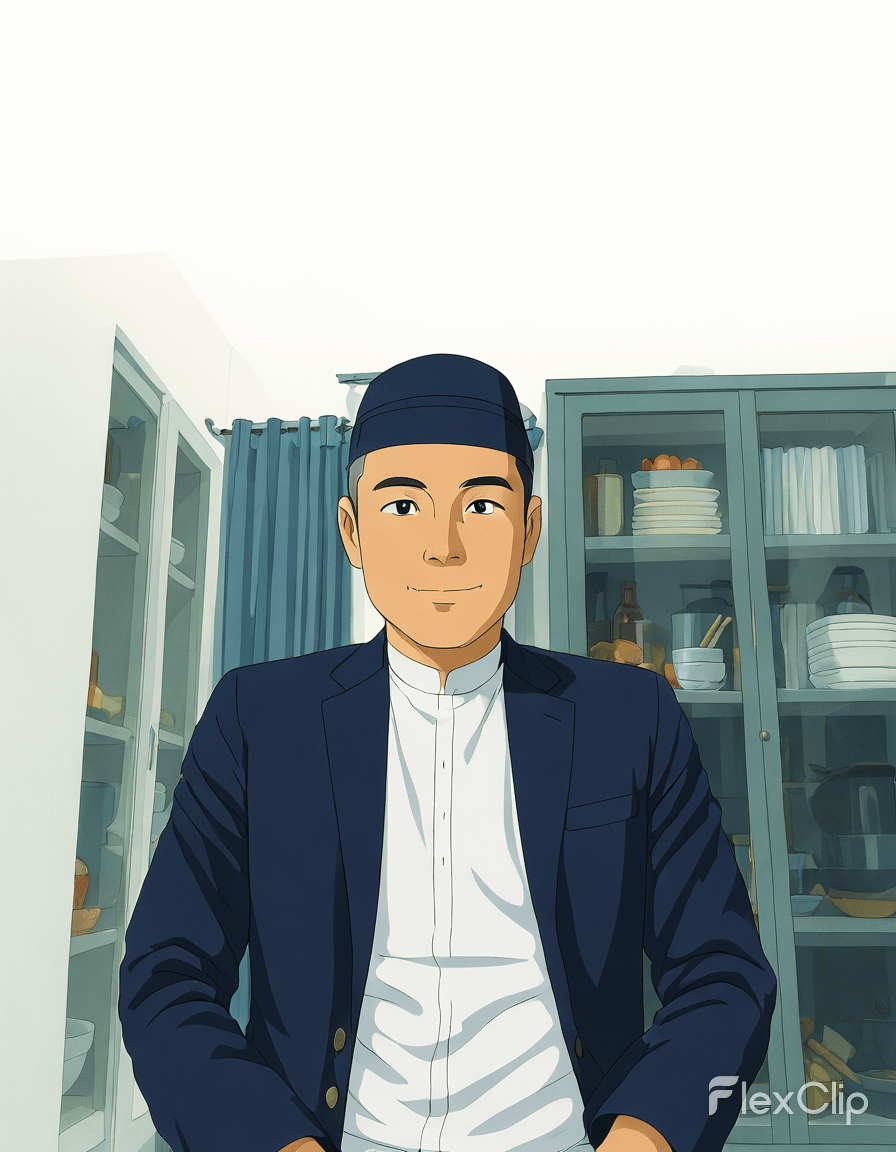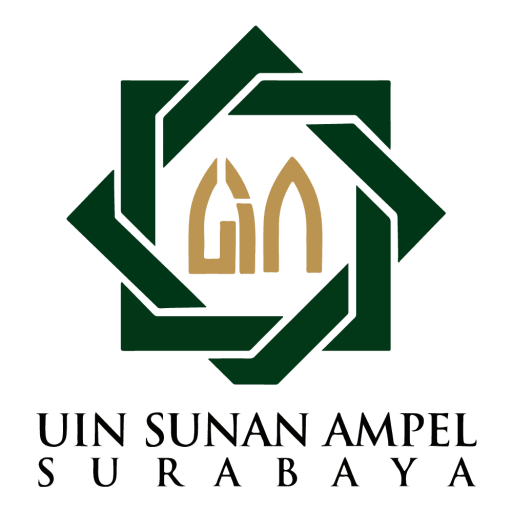Muchammad Helmi Umam, S.Ag., M.Hum.
Setelah sekian lama mendampingi diskusi mahasiswa di luar Prodi Filsafat, masih saja ada kekhawatiran bahwa belajar filsafat bisa mengancam aqidah. Tampaknya masih juga sama, di kalangan masyarakat Muslim, terutama di sebagian kalangan pesantren, belajar filsafat masih dianggap jalan yang menyesatkan. Stigma ini tumbuh dari kekhawatiran bahwa mempelajari filsafat dinilai hanya mengedepankan akal di atas wahyu sehingga dapat menggoyahkan iman dan menjerumuskan pada pemikiran yang bertentangan dengan syariat. Padahal, dalam sejarah Islam, tokoh-tokoh besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibnu Rushd hingga Al-Ghazali terbukti telah menggunakan jalan filsafat untuk memperdalam keimanan. Efeknya, ketakutan ini justru menghalangi potensi kebanyakan muslim dan santri untuk memperkaya intelektualitas Islam secara kritis dan rasional. Karena faktor ini pula, minat calon mahasiswa terhadap Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam masih mengambang.
Berikut adalah 5 alasan sederhana bahwa belajar filsafat di UIN justru akan menguatkan keyakinan dan meningkatkan pemahaman keagamaan.
Pertama, filsafat sering disalahpahami sebagai hanya latihan berpikir kritis (epistemologi) tanpa batas. Padahal, di dalam filsafat juga terdapat sistem keyakinan tetang hakikat (ontologi), sistem penilaian, dan sistem tindakan (aksiologi) yang dibangun secara mendalam. Filsafat bukan hanya seni bertanya, tapi juga seni hidup—karena semua konsekuensi berfikir kefilsafatan justru menuntun manusia pada cara memahami nilai, kebenaran, dan tindakan yang bermakna. Mengabaikan aspek-aspek ini berarti mereduksi filsafat menjadi semata-mata permainan akal, padahal ia sejatinya adalah panduan menyeluruh untuk memahami realitas dan hidup secara bertanggung jawab.
Kedua, Sekalipun berpikir kritis dianggap sebagai jalan utama dalam berfilsafat, ia tetap tak mampu menggoyahkan kebenaran hakiki yang ditanamkan dalam fitrah manusia: keberadaan Tuhan, keteraturan Alam, dan kemuliaan Manusia. Pikiran bisa meragukan segalanya, seperti yang Descartes tunjukkan, namun justru keraguan itulah yang menegaskan bahwa yang pasti hanya proses berfikirnya manusia (yang meragukan), bukan kepastian hasilnya. Kebenaran ontologis tidak lahir dari hasil berpikir, melainkan mendahuluinya—ia bersifat a priori, dibisikkan oleh Nur Ilahi kepada hati yang jernih. Maka, iman bukan level yang dilawan oleh akal, tapi justu menjadi landasan akal.
Logika yang jernih justru menegaskan bahwa dalil keberadaan Tuhan itu memadai, sebab adanya manusia yang berpikir adalah sesuatu yang pasti. Namun, karena kualitas berpikir itu sendiri meragukan, maka berpikir tak bisa dijadikan satu-satunya pijakan dalam mencari kebenaran. Jika eksistensi Tuhan dianggap tak bisa dipastikan, maka secara adil kita juga harus mengakui bahwa ketiadaan-Nya pun sama-sama tak bisa dipastikan. Maka tampak jelas, berpikir saja hanya membawa manusia berputar dalam lingkaran keraguan yang tak berujung. Di sinilah letak keadilan logika sederhana: bahwa keyakinan akan Tuhan dan kebenaran ontologis justru lebih kokoh daripada keraguan yang terus-menerus.
Ketiga, filsafat sejak awal bukanlah alat untuk melawan iman, melainkan untuk melayaninya—seperti yang terlihat dalam tradisi intelektual semua agama besar: Kristen, Buddha, Hindu, dan tentu saja Islam. Di UIN, filsafat tidak diajarkan untuk menggugat keyakinan, tetapi justru untuk memperdalamnya, agar kita tidak hanya percaya, tapi juga mengerti mengapa kita percaya. Kritisisme dalam filsafat bukan untuk meruntuhkan, melainkan untuk mengokohkan, agar ibadah lahir dari pemahaman yang baik, bukan hanya kebiasaan yang diturunkan. Filsafat yang sejati menuntun hati menuju cinta yang sadar, bukan ragu yang liar. Karena iman yang kokoh bukan yang menolak akal, tapi yang mengajak akal untuk ikut bersujud.
Filsafat sungguh-sungguh memang bukan musuh iman, tapi justru ilmu yang telah lama dikembangkan dalam tradisi agama-agama besar dunia untuk memperdalam, mempertahankan, dan membela keyakinan. Di Kristen misalnya, ada semboyan “credo ut intelligam” (aku percaya agar aku memahami), yang menyiratkan bahwa iman titik tolak menuju pemahaman rasional atas kebenaran ilahi. Ada juga semboyan, “fides quaerens intellectum” (iman yang mencari pengertian), menunjukkan bahwa iman sejati mendorong manusia menggunakan akalnya demi memahami Tuhan lebih mendalam. Pemikiran Islam yang dikembangkan di UIN menempatkan akal (‘aql) dipahami sebagai instrumen yang melayani iman (wahyu). Para pemikir besar seperti al-Ghazali dan Ibn Sina di antaranya, memastikan bahwa akal bekerja untuk memperkokoh dan memahami kebenaran ilahi, bukan menggantikannya. Konsep ini sejalan dengan prinsip ‘ratio subserviens fidei’, di mana akal tunduk pada wahyu. Wahyu menerangi, sedangkan akal menerangkan.
Keempat, kekuatan berpikir memang menjadi dasar dalam belajar filsafat, tetapi itu hanyalah sepertiga dari keseluruhan jalan keilmuan yang ditempuh. Di balik logika dan analisis, filsafat juga menuntut kepastian ontologis—yaitu pemahaman yang mantap tentang hakikat Tuhan, manusia, dan alam—serta panduan hidup yang bernilai secara aksiologis. Di UIN, mahasiswa filsafat tidak dibiarkan hanyut dalam relativisme berfikir, karena aqidah mereka dipayungi oleh keyakinan yang mutlak dan tradisi keilmuan Islam yang kukuh. Justru dari sinilah mereka didorong untuk menjadikan kekuatan berfikir dalam filsafat bukan sekadar teori, melainkan menjadi living philosophy—filsafat yang menghidupkan, membimbing kehidupan sehari-hari, dan memperkuat spiritualitas. Filsafat di UIN bukan untuk diakhiri dengan banyak perdebatan pada hal-hal yang tinggi, tetapi untuk menjadikannya lebih lebih matang dan lebih bermakna dalam aplikasi hidup sehari-hari. Belajar filsafat di UIN tidak hanya agar lihai berargumen, tetapi juga agar cakap dalam kehidupan bermasyarakat. Para sarjana filsafat UIN divisikan menjadi kelompok penggerak yang kuat dalam menopang kekuatan masyarakat Islam, ketertiban sosial, pendidikan, budaya, politik, serta isu-isu kemanusiaan yang terus berkembang.
Kelima, Kurikulum yang dikembangkan di Prodi Aqidah dan Filsafat Islam UINSA misalnya, dirancang secara integral, memadukan keilmuan Aqidah Islamiyah yang kuat dengan pemahaman mendalam terhadap Filsafat Islam. Keilmuan Filsafat Islam sendiri dihadirkan sebagai hasil kolaborasi antara apresiasi terhadap warisan intelektual para filsuf Muslim dan kemampuan analisis kritis dari tradisi Filsafat Barat. Karena itu, belajar filsafat di UIN memberikan dua keuntungan besar sekaligus: terjaminnya akidah keislaman dan dikuasainya dua tradisi filsafat dunia, Filsafat Islam dan Filsafat Barat. Ini tentu menjadi satu keistimewaan yang belum tentu diperoleh jika mahasiswa mempelajari filsafat di perguruan tinggi umum atau perguruan non-keagamaan seperti UIN.