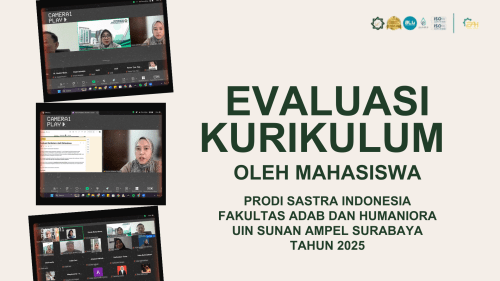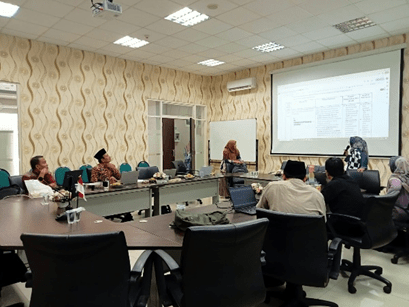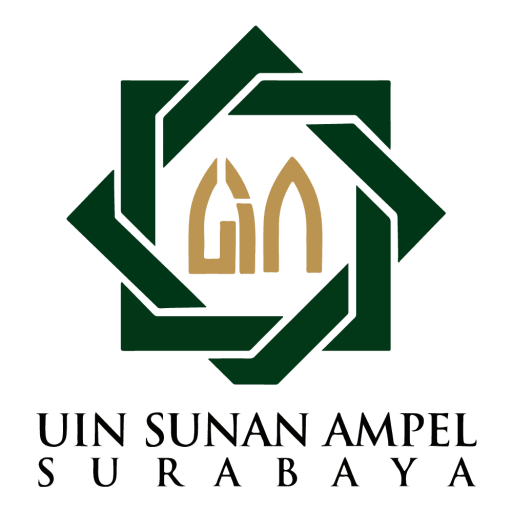Perubahan kebijakan merupakan suatu keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan, karena pada dasarnya kebijakan publik dirancang untuk merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang. Dalam perspektif teori Multiple Streams Framework yang dikemukakan oleh John W. Kingdon, perubahan kebijakan terjadi ketika tiga arus utama yakni arus masalah, arus kebijakan, dan arus politik—bertemu dalam suatu momen yang disebut policy window. Teori ini memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami dinamika kebijakan di Indonesia, termasuk dalam sektor penyelenggaraan ibadah haji. Dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, kebijakan haji mengalami berbagai perubahan signifikan yang tidak jarang menimbulkan kontroversi, terutama dalam aspek pengaturan kuota jemaah, proporsi pembiayaan, serta mekanisme pengambilan keputusan. Perubahan-perubahan tersebut tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga merupakan cerminan dari respons pemerintah terhadap tekanan global pascapandemi COVID-19, kebutuhan penyesuaian fiskal nasional, dan dinamika politik antar aktor kebijakan di tingkat domestik. Kompleksitas perubahan ini menjadi sorotan publik karena menyentuh langsung aspek teknis maupun emosional dalam penyelenggaraan ibadah haji, yang selama ini memiliki sensitivitas tinggi di masyarakat.
Dari aspek proses, kebijakan pengaturan kuota dan biaya penyelenggaraan ibadah haji pada periode tersebut menunjukkan karakter reaktif-adaptif. Pemerintah Indonesia merespons krisis global, perubahan regulasi Pemerintah Arab Saudi seperti pembatasan usia maksimal dan keterbatasan kapasitas akomodasi di Mina, serta tekanan fiskal nasional dengan menyesuaikan kebijakan secara cepat. Meskipun bersifat teknokratis dan responsif, proses kebijakan ini menunjukkan keterbatasan dalam pelibatan publik. Keadaan ini menunjukkan bahwa kecepatan pengambilan kebijakan yang diperlukan dalam situasi krisis belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme konsultasi partisipatif yang pada akhirnya dapat menurunkan legitimasi kebijakan dan menimbulkan resistensi dari pihak yang terdampak langsung.
Dari sisi bentuk, terdapat tiga perubahan utama dalam pengaturan kuota: (1) penetapan prioritas keberangkatan bagi jemaah haji tahun 2020 yang tertunda akibat pembatasan usia, yang diterapkan kembali pada musim haji 2022; (2) penghapusan kuota pendamping lansia dan penggabungan mahram pada 2023 untuk menertibkan antrean dan mencegah penyalahgunaan sistem; serta (3) perubahan komposisi alokasi kuota tambahan pada 2024 dari 92:8 menjadi 50:50 antara jemaah reguler dan jemaah haji khusus. Dalam hal pembiayaan, kebijakan meliputi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) setiap tahun, penggunaan nilai manfaat secara darurat pada 2022 untuk menutupi lonjakan biaya layanan masyair, serta reformulasi proporsi pembiayaan dari 40:60 menjadi 60:40 antara jemaah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Perubahan-perubahan tersebut mencerminkan pendekatan inkremental yang mencakup policy maintenance, policy succession, dan policy termination. Namun, kebijakan yang diambil secara mendadak tanpa masa transisi yang memadai berisiko menciptakan ketimpangan persepsi keadilan di masyarakat, terlebih jika tidak disertai komunikasi publik yang terbuka dan inklusif.
Dalam aspek dampak, kebijakan tersebut menimbulkan implikasi yang kompleks dalam dimensi teknis, sosial, dan ekonomi. Pengetatan usia dan syarat kesehatan meningkatkan efisiensi manajemen jemaah, namun menyebabkan ribuan jemaah lansia tertunda keberangkatannya. Perubahan alokasi kuota tambahan membantu mengurangi kepadatan di Mina, tetapi menimbulkan persepsi ketidakadilan antara jemaah reguler dan haji khusus. Penghapusan kuota pendamping memperbaiki sistem distribusi kuota, tetapi menyulitkan jemaah rentan yang membutuhkan pendampingan. Reformulasi pembiayaan memperkuat daya tahan fiskal dan prinsip istitha‘ah, namun sekaligus menambah beban ekonomi bagi jemaah dari kelompok menengah ke bawah. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan teknokratis dalam kebijakan haji belum sepenuhnya diimbangi dengan kepekaan sosial yang memadai, serta belum sepenuhnya menjamin akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, dinamika perubahan kebijakan haji Indonesia periode 2022–2024 mencerminkan respons cepat terhadap tantangan berskala transnasional maupun domestik. Namun demikian, kebijakan tersebut masih menyisakan persoalan fundamental terkait partisipasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, arah kebijakan penyelenggaraan ibadah haji ke depan perlu memperkuat dimensi inklusif dan partisipatif, serta berbasis pada kebutuhan jemaah sebagai penerima manfaat utama, guna mewujudkan tata kelola haji yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Resume dari Tesis Vika Wafa Ilmi, Mahasiswa Magister Studi Islam