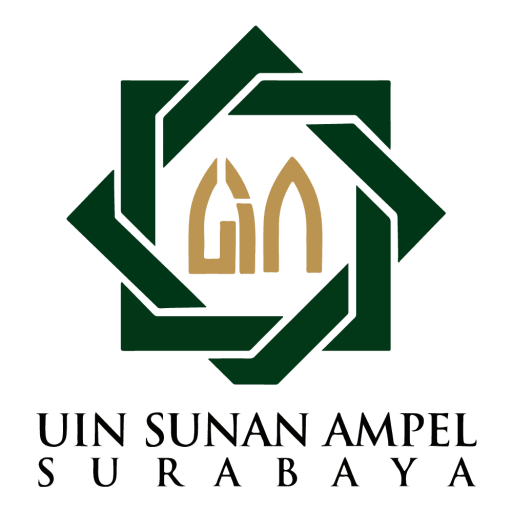Sebagai salah satu anggota Perkumpulan Program Studi Sejarah se-Indonesia (PPSI), Program Studi Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Ampel Surabaya turut hadir dalam Seminar Nasional yang dihelat di Gedung ASEEC lantai 5 UNAIR pada 23 Juni 2025 lalu, di mana penulis berkesempatan mewakili. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama PPSI bersama FIB UNAIR, UNHAS, UNAND, dan Perkumpulan Praktisi Profesi Kesejarahan (P3K). Sebuah pertemuan yang bukan sekadar seminar biasa, tapi juga suatu ruang bagi para sejarawan dan budayawan muda dari berbagai penjuru Indonesia, mulai dari akademisi kampus hingga komunitas untuk saling bertemu dan bertukar ide.
Seminar ini punya dua tujuan besar yang cukup strategis. Pertama, mempererat hubungan antar sejarawan muda, seperti membangun jejaring pertemanan dan profesional yang bisa jadi fondasi studi sejarah yang kuat dan berkelanjutan. Kedua, seminar ini ingin membekali para sejarawan muda dengan kemampuan mengkaji secara kritis asal-usul benda-benda bersejarah—benda yang tak hanya materi fisik, tetapi juga penyimpan cerita dan identitas.
Desain acaranya dibagi dalam dua sesi. Pagi hari, kita diajak memahami teori dan contoh studi provenance dari para ahli, termasuk dari Jepang dan Belanda. Sementara sesi siang hadir lebih interaktif, membahas praktik langsung soal repatriasi benda bersejarah dan bagaimana generasi muda bisa mengambil bagian dalam konservasi warisan budaya. Dengan format ini, seminar terasa lengkap, menggabungkan antara pemikiran teoretis dan realitas lapangan.
Pagi itu, tepat pukul 08.30, seminar dimulai dengan tema penting: “Repatriasi Benda Cagar Budaya dan Keahlian Provenance di Indonesia.” Tema ini membicarakan asal-usul benda juga cerita panjang tentang perjalanan barang-barang tersebut, siapa yang memilikinya, dan apa makna sosial-politik yang menyertainya.
Dr. Willian Bradley Horton dari Akita University membuka wawasan tentang bagaimana provenance ini bisa membuka kisah-kisah tersembunyi di balik benda-benda sejarah. Dr. Mayumi Yamamoto dari Miyagi University menambahkan, tanpa penguasaan ilmu provenance, kita bisa kehilangan warisan budaya karena pengaruh asing yang terlalu dominan. Ia mengingatkan kita soal resiko neo-kolonialisme yang tak hanya soal politik, tapi juga budaya.
Salah satu yang paling menarik adalah presentasi tentang program Memories of the World (MOW) dari UNESCO, serta koleksi NIOD dari Belanda. Program ini jadi contoh gemilang dalam menyimpan dan mengelola bahan sejarah dengan cara yang obyektif dan profesional, jauh dari kepentingan politik.
Para akademisi Indonesia, seperti Prof. Dr. Ismunandar dan Dr. Johny A. Khusyairi, menegaskan bahwa warisan budaya bukan sekadar benda mati. Ia adalah modal sosial dan budaya, sumber kekuatan untuk diplomasi dan membangun identitas nasional. Mereka juga mengulas tentang neo-kolonialisme yang kerap menahan kita mengakses penuh artefak bersejarah.
Dari studi kasus Pabrik Kinin di Bandung, yang mungkin dikenal sebagai lokasi syuting film horor, kami diajak menyadari betapa pentingnya menjaga situs seperti ini. Kisahnya menyentuh industrialisasi dan kolonialisme yang melekat, tapi sayangnya sering terabaikan atau dialihfungsikan tanpa memperhatikan nilai sejarahnya.
Diskusi berjalan interaktif. Peserta tak cuma mendengar, tapi aktif mengajukan pertanyaan dan kritik, membuat suasana seminar menjadi ajang dialog yang dinamis.
Memasuki sesi kedua pukul 13.00, atmosfer berubah jadi lebih hidup. Fokus bergeser ke peran akademisi muda dalam pelestarian budaya. Mereka membahas tantangan nyata repatriasi benda budaya—ruwetnya birokrasi, sengketa kepemilikan, dan masalah teknis konservasi. Narasumber utamanya adalah Dias Pradadimara, M.A, Dr. Muslimin A.R. Effendy, Prof. Dr. Agus Suwignyo, Prof. Dr. Budi Agustono, dan Prof. Alicia Schrikker.
Di sesi ini, peserta diajak memahami secara lebih mendalam tentang konsep arsitektur vernakular masyarakat Dayak, khususnya tipe “Lamin” yang tidak hanya sebagai rumah tetapi juga pusat aktivitas sosial dan ritual. Menurut Muslimin A.R. Effendy, Lamin Dayak Banuaq dan Dayak Kenyah di Kalimantan Timur memiliki struktur ruang yang kompleks dan sarat makna—terdiri dari Usei sebagai ruang tamu dan pertemuan, dapur, bilik, hingga ruang publik untuk upacara adat. Dijelaskan pula simbolisme kosmologis terkait pembagian ruang dan kaitannya dengan kepercayaan masyarakat setempat.
Selain pembahasan tentang arsitektur vernakular, sesi ini juga menyinggung aspek sejarah yang lebih luas seperti praktik “Ngayau” atau kepala buruan yang punya makna sakral dan magis dalam kebudayaan Dayak, serta bagaimana resolusi sosial berlangsung untuk mengakhiri konflik tradisional tersebut melalui pertemuan penting di akhir abad ke-19.
Informasi ini membuka perspektif baru bagi peserta seminar tentang bagaimana benda-benda dan struktur budaya yang tampak “tradisional” sesungguhnya menyimpan kekayaan makna, fungsi sosial dan spiritual yang sangat dalam, serta menjadi bagian vital dari warisan budaya yang harus dijaga.
Di sanalah terlihat bahwa proses repatriasi ini bukan sekadar mengembalikan benda, tapi juga soal membangun kebanggaan dan memperkuat identitas bangsa lewat keberhasilan mengelola warisan budaya.
Sesi ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya generasi muda untuk terus mendalami kajian provenance, etika konservasi, dan inovasi teknologi pelestarian. Seminar ini menjadi titik temu berbagai pengalaman dan jaringan kerja yang diperlukan demi konservasi yang berkelanjutan.
Secara menyeluruh, seminar ini mengajak peserta memahami bahwa menjaga warisan budaya adalah tugas bersama yang memerlukan pemahaman mendalam dan aksi konkret. Saya yakin peserta meninggalkan seminar dengan semangat segar dan gagasan baru untuk berkarya dalam studi provenance dan pelestarian budaya Indonesia.
______
Ditulis oleh Akhmad Najibul Khairi Sya’ie, Ph.D., Dosen Prodi Sejarah Peradaban Islam UINSA