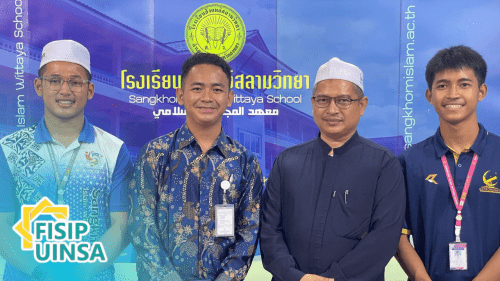Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
Tiba-tiba kuingat novel berjudul The Alchemist: A Fable about Following Your Dreams. Karya novelis kondang asal Brazil. Paulo Coelho, namanya. Terbit pertama kali tahun 1988. Kusebut frase “pertama kali”, karena novel ini lalu diterjemahkan ke dalam lima puluh enam bahasa di dunia. Terjual lebih dari dua puluh juta eksemplar. Menjadikannya sebagai salah satu bacaan terlaris di dunia. Mengapa begitu popular novel itu? Isinya tak pernah lekang oleh waktu. Karena berkutat pada kebutuhan konkret hidup manusia. Yakni, tentang langkah untuk mengejar mimpi dalam hidup. Siapa saja pasti melakukan dan membutuhkannya.
Jalan cerita novel itu memang mengisahkan lelaki anak gembala (shepherd boy) asal Andalusia, Spanyol, bernama Santiago. Dia melakukan perjalanan ke Afrika Utara menuju Mesir. Mendatangi berbagai piramida di negeri itu. Kepentingannya untuk menemukan harta karun (treasure) di sana. Langkahnya mengejar mimpi itu membuat substansi dasarnya mengenai setiap orang. Sebab, siapapun orang pasti mengalaminya. Pasti melakukannya. Terlepas dari konteks budaya dan lokasi tinggal yang berbeda-beda. Karena itu, novel itu seakan membicarakan setiap diri pembacanya meski berbeda latar belakang. Terkenallah novel itu akibat tingginya jumlah pembacanya sedunia.
Ada kutipan kalimat menarik dari novel itu yang bikin kuterngiang. Begini isinya: when you really want something, the universe always conspires in your favor. Kalimat ini tertulis enam kali di sejumlah bagian isi buku. Kalimatnya mirip-mirip. Walau sedikit ada yang beda. Seperti: when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. Meskipun sedikit ada beda redaksi, tapi substansi kalimat yang disebut berulang hingga enam kali itu memiliki substansi yang sama. Inilah pesannya: Niat baik akan membuat semesta berkonspirasi untuk membantu mewujudkan.
Tentu, niat itu diikuti dengan komitmen. Bentuknya keseriusan. Itulah yang diajarkan oleh kutipan pada buku The Alchemist di atas. Buktinya, ada kata “really” yang disematkan ke dalam kalimat yang disebut hingga enam kali, seperti pada kutipan di atas. Kata tersebut menunjukkan adanya komitmen yang tinggi. Dalam padanan Bahasa Indonesia, kata tersebut bermakna “sungguh”. Tentu komitmen ini bermakna kesungguhan atau keseriusan. Jika di sana ada kesungguhan, di sana juga akan ada hasil. Jika di sana ada keseriusan, di sana pula akan ditemukan apa yang diimpikan.
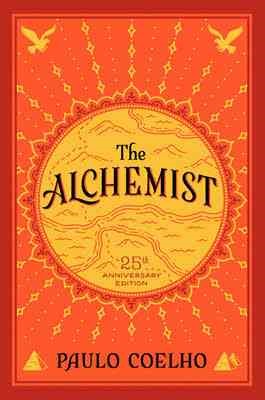
Aku betul-betul lalu teringat kembali novel di atas. Ingatanku membawaku kembali ke kisah lelaki anak gembala dalam mengejar impiannya seperti diceritakan dalam novel itu. Aku terpesona betul dengan kutipan kalimat magis yang diulang hingga enam kali dalam novel tersebut. Kusebut “magis” karena memang kutipan kalimat itu sangat berenergi. Penuh ruh yang membuat isinya selalu hidup dalam keseharianku. Hingga menjadi ingatan kuat dalam benakku. Dan setiap kali melangkah untuk kebajikan, setiap kali itu pula ingatanku pada kutipan kalimat magis itu muncul kembali.
Pertanyaannya lalu, mengapa kuingat kembali kutipan di novel itu di malam itu? Ya, sebuah malam di Hari Kamis (3 Oktober 2024). Kala itu, aku bersama sahabatku Mas Ribut pulang dari kampus. Sekitar jam 18:45 WIB. Perjalanan kala itu sedang mengantarku persis menyusuri bentangan jalanan sepanjang Jalan A. Yani. Jalur utama di ujung selatan Kota Surabaya. Kebetulan arahku malam itu sedang menuju keluar ke Kota Sidoarjo. Ada mobil ambulance dengan suara sirine yang kencang terdengar sejak dari belakang sekali. Pertanda ada yang darurat di dalamnya. Semakin mendekat ke arah kendaraanku, semakin kencang terdengar suara sirine itu.
Meski kemacetan sedang parah-parahnya, mobil ambulance berjalan dengan gegasnya. Padahal, sekali lagi, jalanan sedang macet-macetnya. Mobil ambulance itu ternyata bisa memecah kemacetan hebat itu. Padahal, lagi-lagi, kemacetan malam itu sedang parah-parahnya. Berlalu saja mobil ambulance dengan lancarnya. Persis seperti rombongan kendaraan VVIP yang sedang dikawal oleh Polisi Patwal. Rasa penasarankau lalu menelisik ke otakku. Untuk mencari jawaban kenapa mobil ambulance itu bisa berlalu dengan lancarnya. Padahal, sekali lagi, jalanan sedang macet-macetnya. Apa yang sebetulnya sedang terjadi dengan mobil ambulance itu? Begitu tanyaku dalam hati.
Menolehlah aku ke arah paling kiri jalanan ke arah keluar kota itu. Dan ternyata kudapati depan mobil ambulance itu ada motor sekelas Yamaha Nmax. Sang pengendara motor menyalakan lampu hazard beserta klakson. Meminta semua pengguna jalan di depannya untuk memberi jalan kepada mobil ambulance. Dengan tangkasnya, sang pengendara motor sekelas Yamaha Nmax itu membelah kepadatan jalan. Cakap dan tangkas sekali. Dia belokkan setir motor ke kanan dan ke kiri, lalu kembali ke kanan lagi. Begitu pula seterusnya. Kepentingannya, agar para pengendara motor dan mobil di bagian depan memberikan jalan leluasa ke mobil ambulance.
Kusaksikan kejadian seperti di atas bukan sekali itu saja. Berkali-kali. Setiap kali ada ambulance yang melintas dengan isyarat kedaruratan yang kuat, di depannya selalu ada motor sekelas Yamaha Nmax di atas. Itu yang sering kutemui. “Motor pengawal ambulan itu ada jaringannya, Pak,” komentar Mas Ribut menyambut kesan yang kuceritakan atas motor pengawal mobil ambulance itu. “Contohnya begini,” katanya lebih lanjut. “Jika mobil ambulance itu mengangkut penumpang sakit atau meninggal ke arah Kota Jombang, maka sudah pasti ada motor pengawal yang sudah standby di pintu keluar tol Jombang.” Begitu yang diceritakan Mas Ribut.
“Mereka itu punya jaringan di berbagai kota.” Begitu jelas Mas Ribut lebih lanjut.” Nah, yang di Surabaya langsung mengontak rekan sesama komunitas pengawal ambulance itu di kota yang akan dituju oleh mobil ambulance itu. Nanti mereka melakukan estafet. Yang di Surabaya mengantar hingga masuk tol Waru. Dan yang di Jombang akan menyambut mobil ambulance itu di pintu keluar tol Jombang. Lalu dikawal hingga sampai ke titik lokasi tujuan.” Demikian komentar Mas Ribut menceritakan pengetahuannya atas komunitas relawan pengawal mobil ambulance itu.
Ahaaa!!! Komunitas relawan pengawal mobil ambulance. Apa iya, ada? Jawabannya, iya. Ada. Ternyata komunitas itu ada. Lahir dan diikat oleh volunterisme yang tinggi. Mengapa begitu? “Mereka itu relawan, Pak. Semua layanan yang diberikan gratis,” jelas Mas Ribut. Dan mereka itu, ujar Mas Ribut lebih lanjut, “ada di berbagai kota.” Makanya, jika ada mobil ambulance yang bergerak ke arah selatan menuju pintu tol Waru, motor pengawal ada di depannya dan mengawalnya hingga mobil ambulance itu masuk ke pintu tol. Sementara, di pintu keluar tol yang akan dituju sudah siap siaga relawan dari komunitas relawan pengawal mobil ambulance di kota tujuan itu. Mereka semua melakukan itu secara suka rela. Tak ada paksaan. Juga lebih-lebih, tak ada imbalan pendapatan berapapun. Murni voluntir. Sebagai nama lain dari relawan.
Volunterisme. Itu kata kunci kemuliaan. Di tengah hiruk-pikuknya kota besar, masih ada praktik atas nilai volunterisme itu. Di tengah kuatnya tarikan materialisme, masih ada jiwa-jiwa yang mendermakan diri untuk kemanusiaan. Di tengah besarnya tarikan konsumerisme, masih ada hati yang mulia untuk membaktikan diri demi kebajikan sesama. Semua dalam skema sukarela. Tak berbayar. Dilakukan oleh para jiwa dan hati dalam jumlah yang tidak tunggal. Kemudian membesar hingga menjadi sebuah gerakan kemuliaan. Dengan begitu, volunterisme itu gelombang panggilan jiwa.
Lalu, apa pelajaran yang bisa ditarik dari gerakan kemuliaan volunterisme ala komunitas relawan pengawal mobil ambulance di atas? Ada dua pelajaran hidup yang penting untuk diperhatikan. Pertama, kemuliaan tidak akan pernah sendirian. Akan selalu ada kemuliaan-kemuliaan lain nan serupa yang diberikan dan dibagikan oleh sesama. Itu semua karena dalam diri setiap insan selalu dan pasti bersemayam nilai kemuliaan. Separah apapun kondisi diri seseorang, nilai kemuliaan itu tak akan pernah redup. Tetap hidup senyampang nyawa berada dalam raga. Tinggal masalahnya adalah apakah nilai kemuliaan itu dalam keadaan sleeping atau awake. Tertidur atau tersadar.
Setiap diri pasti memiliki kepentingan agar nilai kemuliaan diri itu terus hidup-tersadar. Itu prinsip utama kemanusiaan. Buktinya, tak pernah ada orang yang ingin hidup dalam keburukan dan kesengsaraan. Seburuk-buruk seseorang tak pernah ingin keburukan itu terus mendera dirinya. Juga, seburuk-buruk seseorang tak pernah ingin anaknya mengalami kondisi serupa dengan dirinya. Karena itulah kata “hope” dilahirkan. Karena itulah kata “harapan” selalu menjadi bagian dari kehidupan. Sebab, setiap diri pasti menginginkan hidup yang lebih baik nan mulia dari waktu ke waktu.
Nilai kemuliaan yang terus hidup dan tersadar memberikan tekanan kuat kepada keburukan untuk meredup. Selanjutnya, keburukan itu bisa tertekan ke bawah saat nilai kemuliaan terus hidup dan tersadar dalam diri seseorang. Dan sebaliknya, keburukan akan dapat menyeruak ke atas saat kemuliaan terus tertekan ke bawah. Itulah praktik pergerakan hidup. Meskipun begitu, bukan berarti saat kemuliaan diri terus hidup dan tersadar, maka otomatis keburukan pasti meredup. Tak selinear itu. Tak sesederhana itu. Karena nilai kemuliaan butuh lahan subur. Butuh bingkai yang mengkerangkainya untuk berkembang baik.
Karena itu, untuk tumbuhnya kemuliaan di atas, jejaring komunitas sepengharapan menjadi penting. Orang modern menyebut epistemic community. Yakni, jejaring komunitas yang ada, tumbuh, dan terbentuk di atas nilai yang dibagikan (shared) bersama. Lalu, masing-masing dari komunitas itu berjuang untuk mempertahankan nilai itu agar efektif dan tetap hidup di tengah-tengah mereka (lihat Peter M. Haas, “Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination,” International Organization, vol. 46, no. 01 (1992):3). Nah, kemuliaan butuh komunitas seperti itu sebagai lahan subur. Ibarat tumbuhan, benih yang baik perlu ditanam di lahan yang subur. Bisa saja lahan itu luas. Tapi, vas bunga yang kecil pun tetap penting bagi tumbuh dan berkembangnya nilai kemuliaan itu. Itulah ilustrasi epistemic community.

Ajaran wong kang sholeh kumpulono seperti yang lama ditransmisikan oleh Mbah Sunan Bonang dalam syair bertajuk Tombo Ati, sejatinya, menunjukkan pentingnya epistemic community di atas. Dengan bergaul bersama orang-orang saleh, akan tercipta jejaring komunitas kemuliaan yang menjadi prasyarat bagi terciptanya lahan subur untuk tumbuhnya kebajikan. Hal itu bukan berarti bahwa bergaul luas tidak penting. Tapi, lepas dari kebutuhan untuk menjaga pergaulan luas itu, tetap dibutuhkan epistemic community untuk tumbuhnya nilai kebajikan itu. Itulah yang dimaui oleh konsep jejaring komunitas sepengharapan, sebagaimana disebut di atas.
Kedua, kemuliaan itu harus diorganisir. Semua itu dibutuhkan agar nilai manfaatnya bisa makin membesar. Komunitas relawan pengawal mobil ambulance seperti diceritakan di atas memberi pelajaran dan sekaligus menjadi bukti bahwa saat diorganisir, nilai kemuliaan menjadi sebuah gelombang. Isunya, kebetulan, soal volunterisme. Isinya panggilan jiwa untuk menabur kebajikan melalui praktik relawan untuk membantu sesama yang sedang kesusahan. Mobil ambulance adalah simbol dari kesusahan itu. Hasil organisir itu sangatlah konkret. Sinergi dan gayung bersambut seakan menjadi template praktik volunterisme oleh komunitas relawan pengawal mobil ambulance di atas. Komunitas relawan itu pun lalu bergerak hingga lintas batas kota.
Kerja pengorganisasian kemuliaan di atas akan memperkuat keberadaan dan atau kehadiran nilai kemuliaan itu dalam hidup bersama. Sebab, nilai kemuliaan itu menemukan jejaringnya di tengah-tengah masyarakat hingga lintas batas wilayah. Apalagi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah kerja pengorganisasian itu. Hingga kemuliaan pun bisa segera meluas melintasi sekat sosial, ekonomi dan bahkan kewilayahan. Maka kebenaran rumus hikmah yang dikenal sebagai milik Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berbunyi اَلْحَقُّ بِلاَ نِظَامٍ يَغْلِبُهُ اْلبَاطِلُ بِالنِّظَامِ kini semakin bisa dirasakan kehadirannya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin memudahkan penyatuan barisan kemuliaan melalui kerja pengorganisasian.
Lahirnya komunitas relawan pengawal mobil ambulance lintas batas kota, sebagaimana diuraikan di atas, menjadi bukti bagaimana penyatuan barisan kemuliaan semakin dimudahkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Koordinasi menjadi semakin terfasilitasi menuju terciptanya kerja penyatuan barisan kemuliaan volunterisme itu. Hasilnya pun bisa segera didapatkan. Kemuliaan volunterisme mewujud dalam bentuk sebuah gelombang kebajikan yang kemudian berwujud perbantuan sukarela untuk pengawalan mobil ambulance, sebagaimana dijelaskan di atas.
Tentu, semua tak akan pernah menolak bahwa volunterisme adalah sebuah kemuliaan. Persis seperti yang dipraktikkan oleh komunitas relawan pengawal mobil ambulance di atas. Tapi semua juga tak bisa mengelakkan sebuah fakta bahwa volunterisme itu bisa dihadirkan di tengah masyarakat melalui kerja pengorganisasian yang baik. Bentuknya adalah koordinasi dan penyatuan barisan pada mereka yang berada dalam niat dan kehendak yang sama untuk membagikan kemuliaan diri kepada sesama melalui pemberian perbantuan sukarela atas kondisi kesusahan sesama.
Nah, belajar dari komunitas relawan pengawal mobil ambulance di atas, maka jangan pernah takut menjadi orang baik. Dua pelajaran hidup dari kisah mereka di atas bisa dijadikan sebagai referensinya. Sungguh-sungguh adalah prasyarat. Sebagaimana diilustrasikan dengan kata really dalam novel The Alchemist di atas. Kesungguhan memang menjadi pilar penting bagi kehendak untuk mendedar diri sebagai pribadi yang baik. Karena kesungguhan akan membentuk ketahanan untuk bisa bernafas panjang. Dan ketahanan untuk nafas panjang itu akan disempurnakan oleh keyakinan bahwa tak sedikit niat dan perilaku baik itu akan disambut oleh niat dan perilaku baik serupa oleh orang-orang di sekeliling. Yakinlah, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.