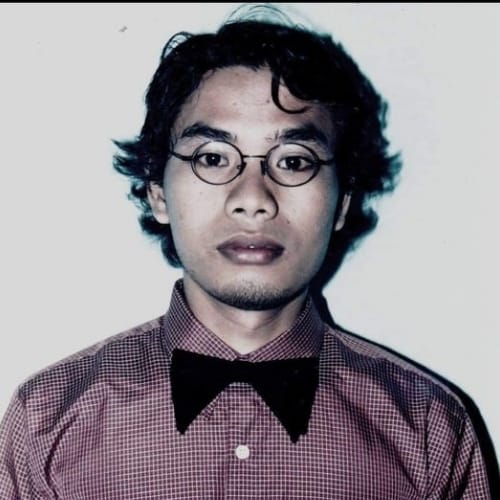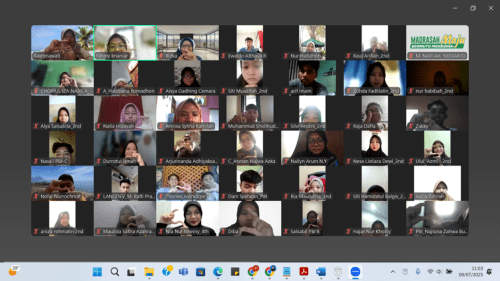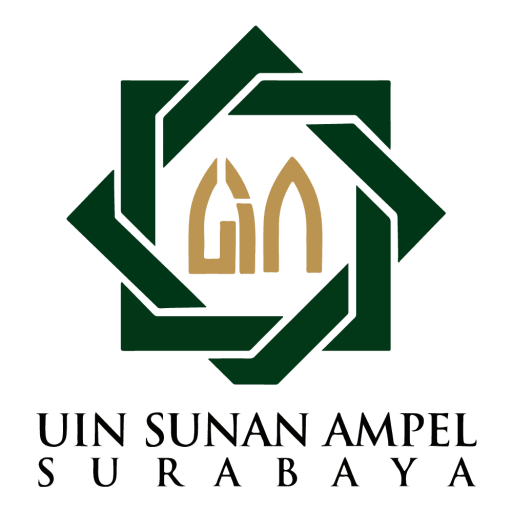Di tengah riuh nasib Bangsa Palestina dan isu keamanan global, Iran kembali menjadi sorotan karena keberaniannya melawan Israel secara langsung. Bukan pertama kalinya. Kali ini, Iran tampil sendirian menghadapi negara yang didukung penuh oleh kekuatan Amerika dan Barat. Dalam peta geopolitik umat Islam hari ini, disukai atau tidak, hanya Iran yang tampil sebagai simbol nyata kekuatan Islam yang berani berdiri tegak di hadapan tekanan Barat. Fakta kepercayaan diri ini tentu bukan sekadar soal strategi militer atau kepentingan politik, tetapi soal apa yang membentuk keberanian ini secara mendalam.
Kekokohan Iran yang mengagumkan ini tentu bukan hanya didorong kekuatan militer atau semangat keislaman biasa, tetapi jauh mendalam karena akar kebudayaan ilmu kesilaman yang tumbuh kokoh. Landasan pemikiran keislamannya bukan sekadar wacana spiritual, tetapi dibentuk dari filsafat keilmuan yang sudah matang. Yang menarik, Iran tidak menempuh jalan “integrasi ilmu” sebagaimana banyak dilakukan oleh institusi keilmuan di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Iran memilih pendekatan yang lebih tegas, bukan menyatukan atau menegosiasikan antara ilmu Barat yang sekuler dan ilmu Islam, tetapi menyempurnakan ilmu. Pendekatan ini dikenal sebagai konsep al-takamul al-‘ilmī (التكامل العلمي).
Filosofi al-takamul al-‘ilmī ini berpijak pada pandangan bahwa semua ilmu bersumber dari Allah. Ilmu bukan terbagi antara yang religius dan yang sekuler, tetapi bersifat tunggal dan utuh. Tugas muslim sebagai khalifah di muka bumi adalah menggali, mengembangkan, dan menyempurnakan ilmu ini agar dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan. Termasuk dalam hal teknologi, rekayasa sosial, hingga tata kelola negara. Iran tidak mencoba menyesuaikan ilmunya agar cocok dengan dunia Barat, tetapi justru memperluas ilmu berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mendalam.
Pijakan ini tidak muncul tiba-tiba. Iran menghidupkan kembali warisan para keilmuan Islam dari zaman keemasan Islam. Nama-nama seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, hingga Nasir al-Din al-Tusi bukan hanya dikenal sebagai ilmuwan, tapi ulama yang menjadi ilmuwan karena dorongan spiritual. Mereka tidak mempromosikan integrasi ilmu, melainkan penyempurnaan ilmu keislaman yang berdampak luas bagi peradaban. Dalam karya-karya mereka, ilmu bukan alat netral, tetapi sesuatu yang sarat nilai dan tanggung jawab keilahian.
Imam Ali Khamenei, dalam bukunya Perang Kebudayaan (Al-Ghazwu Al-Tsaqafi: Al-Muqaddimat wa Al-Khaltiyyat Al-Tarikhiyyah, menekankan bahwa kebudayaan adalah medan perang yang menentukan arah umat. Dalam buku itu, Khamenei menggambarkan bagaimana perang peradaban hari ini tidak lagi soal persenjataan militer semata, tetapi juga narasi, ideologi, dan ilmu. Ketika umat Islam hanya bisa mengintegrasikan secara kompromistis, musuh sudah lama menggunakan ilmu untuk mengendalikan arah kehidupan. Filosofi al-takamul al-‘ilmī menjadi jawabannya, sebuah jalan panjang tapi kokoh.
Pertanyaannya kini, apa yang bisa dipelajari oleh umat Islam di luar Iran, termasuk UIN Sunan Ampel Surabaya yang masih mengembangkan model integrasi ilmu? Mungkin ini beberapa hal yang layak dipertimbangkan, pertama, perlu disadari bahwa integrasi bukan satu-satunya jalan. Jalan penyempurnaan ilmu dengan pendekatan Islam yang utuh layak dijajaki lebih dalam. Kedua, perlu adanya keberanian epistemologis untuk keluar dari belenggu dikotomi ilmu yang diwariskan kolonialisme. Ketiga, sudah waktunya para sarjana Muslim menjadi ulama yang berpikir ilmiah, bukan sekadar ilmuwan yang kebingungan mencari landasan keimanan dalam keilmuannya.
Iran telah menyajikan bukti, bukan mimpi, bahwa kekuatan ilmu tidak datang dari kompromi, tapi dari keyakinan penuh pada satu sumber ilmu: Allah. Dari sinilah keberanian, kemandirian, dan peradaban lahir.