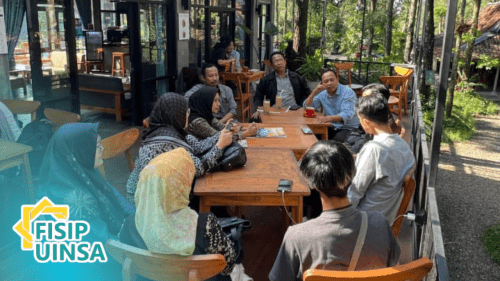Oleh: Dr. Anas Amin Alamsyah. M.Ag
Di era kontemporer, kita menemukan banyak ruang akademik Muslim yang mempertontonkan fenomena yang nyata tapi aneh, yakni “semakin banyak orang tahu tentang agama, tetapi semakin sedikit yang benar-benar berubah karenanya.” Ilmu agama tersebar luas dalam bentuk buku, podcast, video, bahkan potongan TikTok. Namun, kesan yang muncul justru paradoksal —semakin banyak akses, tetapi malah semakin dangkal makna. Ilmu tidak lagi membentuk manusia dan tidak lagi menumbuhkan jiwa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya bisa jadi terletak bukan pada isi ilmu itu sendiri, tetapi pada cara ilmu itu diwariskan dan pada apa yang hilang dari cara itu. Di masa lalu, umat Islam memiliki tradisi yang hidup, di mana struktur adab, sanad, waktu, dan bentuk simbolik tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian spiritual. Tradisi itu bukan sekadar kumpulan adat atau kebiasaan, tetapi mekanisme penyimpanan dan transmisi makna yang mengkonstruksi ilmu menjadi sesuatu yang hadir di dalam tubuh, hati, dan laku hidup.
Hari ini, tradisi tersebut terputus; dan dalam keterputusan itu, ilmu kehilangan kedalaman ontologisnya. Ilmu tetap ada secara data, tetapi mati secara ruhani. Kita mampu menghafal istilah- istilah keislaman, tetapi tidak mampu hidup bersamanya. Inilah kenyataan yang kemudian melahirkan generasi Muslim yang mahir dalam berbicara tentang agama, tetapi rapuh secara moral dan kehilangan orientasi eksistensial. Berangkat dari fenomena ini, tulisan ini hadir sebagai ajakan untuk menoleh kembali ke titik keretakan dari keterputusan tradisi, melalui pertanyaan: apa yang sebenarnya kita warisi dari tradisi Islam?, bagaimana ia dahulu menyampaikan ilmu?, dan apa akibatnya ketika tradisi itu dipotong dari akarnya?
Dalam peradaban Islam klasik, tradisi bukanlah kebiasaan turun-temurun yang kaku, apalagi semata peninggalan sejarah. Tradisi adalah cara hidup epistemik, sebuah kerangka hidup yang mengatur bagaimana ilmu diperoleh, untuk apa ia digunakan, dan bagaimana ia menuntun manusia menuju kesempurnaan akhlak dan pengenalan terhadap Tuhan. Dalam kerangka ini, tradisi Islam menyatukan dimensi spiritual, intelektual, dan sosial dalam satu irama yang utuh. Tradisi Islam tidak menyampaikan ilmu seperti mesin pencetak informasi. Ia mentransmisikan ilmu melalui bentuk, ritme, dan relasi (antara guru dan murid, antara kitab dan hati, serta antara simbol dan makna). Dalam proses transmisi ini, ilmu dipelajari dan bahkan dihidupi. Seorang murid tidak hanya membaca kitab, tetapi juga duduk, mendengar, diam, menirukan, dan menundukkan dirinya dalam proses belajar yang bertahap disertai kesabaran dan penuh penghormatan.
Ilmu bukan semata hasil berpikir. Ilmu adalah hasil dari proses transformasi. Inilah pandangan yang mendasari prinsip mendahulukan adab sebelum ilmu dalam tradisi Islam. Prinsip ini penting untuk diaktualisaikan, karena ilmu yang masuk ke hati tanpa adab tidak akan menjadi cahaya, sebaliknya justru akan menjadi beban ego. Terkait dengan hal ini, sanad (silsilah) ilmu menjadi penanda otentik bahwa ilmu tidak jatuh dari langit ke sembarang orang, melainkan diturunkan melalui jaringan ruhani yang bertanggung jawab. Selain sanad, tikrar (pengulangan) dalam belajar menjadi bagian penting dalam proses pendalaman yang membuka lapisan makna demi lapisan makna. Karena itu, tikrar dalam desain pembelajaran Islami tidak dianggap sebagai kegiatan yang membuang-buang waktu, tetapi justru menjadi metode efektif bagi pelajar untuk pemahaman optimal dan penghayatan holistik dalam proses berilmu.
Tradisi membentuk suasana di mana ilmu tidak bisa dilepaskan dari kesadaran spiritual. Tradisi mendisiplinkan bukan hanya pikiran, tetapi waktu, tubuh, bahkan cara bicara. Dalam tradisi ini, ilmu bukan sekadar mengetahui substansi konseptual tertentu, tetapi mengetahui bagaimana menjadi sesuatu melalui ilmu. Sayangnya, dalam masyarakat Muslim modern, semua struktur ilmu (adab, sanad, ritme, dan simbol) telah dipangkas habis oleh kecepatan, efisiensi, dan logika pasar. Maka, yang tersisa hanyalah potongan-potongan ilmu tanpa lingkungan ruhani yang menopangnya.
Salah satu kekuatan epistemik dalam tradisi Islam adalah bahwa ilmu tidak berdiri sendiri. Ilmu hidup di dalam struktur sosial dan spiritual yang membentuk cara ilmu itu dijaga dan diwariskan. Di pusat struktur ini ada guru. Di sini, guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai figur moral dan pembimbing ruhani. Guru bukan sekadar penyampai materi, tetapi penanggung jawab makna. Ia menyambung rantai sanad yang mengikat satu generasi dengan generasi sebelumnya —sampai ke mata air wahyu. Relasi guru dan murid tidak bersifat teknis. Relasi guru-murid justru bersifat transformatif. Di dalam relasi ini, murid tidak hanya menerima ilmu, tetapi ditempa akhlaknya, ditata kesadarannya, dan diajak masuk ke dalam dimensi makna yang tak bisa ditulis dalam buku teks. Seorang murid bisa duduk bertahun-tahun hanya untuk mempelajari satu kitab kecil, bukan karena materinya sulit, tetapi karena proses pengendapan makna memerlukan waktu, kedekatan, dan penghayatan.
Tradisi juga dibingkai oleh wadah-wadah institusional, seperti zawiyah, khanqah, madrasah, dan pesantren. Tempat-tempat ini bukan sekadar ruang belajar, tetapi ekosistem ruhani dan intelektual yang menciptakan irama hidup tertentu, seperti disiplin waktu, kebersamaan, kesunyian, repetisi, dan kontemplasi. Di sana, ilmu tidak terpisah dari ibadah; dan belajar bukan sekadar kegiatan individual, tetapi bagian dari kehidupan kolektif dalam irama sakral. Ketika sistem ini diruntuhkan oleh logika efisiensi kurikulum, kredensial akademik, dan tekanan administratif, ilmu secara otomatis menjadi kehilangan jiwa komuniternya. Guru digantikan oleh sistem, relasi digantikan oleh kelas besar, interaksi offline digantikan oleh interaksi online, dan sanad digantikan oleh sertifikat. Maka, yang hilang bukan hanya struktur sosial ilmu, tapi juga kepercayaan epistemik, sebuah rasa bahwa ilmu itu punya tempat, punya arah, dan punya jiwa. Inilah yang membuat banyak pelajar Muslim hari ini mengalami kekosongan. Mereka diajarkan isi agama, tetapi tidak diperkenalkan pada cara hidup dalam ilmu itu sendiri. Mereka tahu banyak, tetapi tidak dibentuk. Mereka bisa mengakses ribuan kitab digital, tetapi tidak pernah mengalami keheningan satu majelis bersama seorang guru sejati.
Ketika tradisi sebagai sistem transmisi pengetahuan terputus, yang hilang bukan hanya bentuknya, tetapi orientasi jiwanya. Ilmu yang dahulu hidup dalam irama kontemplatif (dalam adab dan keheningan), kini berubah menjadi sekadar kumpulan informasi yang mudah dikutip, dibagikan, dan diperdebatkan. Dalam perubahan ini, ilmu kehilangan satu hal yang dulu menjadikannya cahaya, yaitu kekuatan untuk mengubah manusia dari dalam. Ilmu yang tidak membentuk kepribadian pada akhirnya akan melahirkan dua ekstrem: keangkuhan atau kekosongan. Keangkuhan membuat individu merasa tahu segalanya dan mudah menghakimi. Sedangkan, kekosongan membuat individu merasa selalu kurang meski sudah belajar ke mana-mana. Dalam dua keadaan ini, jiwa tidak pernah tumbuh. Jiwa hanya mengonsumsi data, tetapi tidak pernah benar-benar tersentuh oleh kebenaran. Kondisi jiwa seperti ini mengonfirmasi kebenaran aksioma bahwa ilmu tanpa orientasi transenden hanyalah beban kognitif.
Di banyak ruang akademik sekarang ini, kita juga menyaksikan gejala-gejala yang menyedihkan: semakin banyak ceramah, tetapi semakin mudah mencaci; semakin banyak kelas agama, tetapi semakin sedikit kesabaran, empati, dan ketundukan kepada Allah. Semua gejala ini bukan karena ilmu itu sendiri salah, tetapi karena cara ilmu ditanamkan telah kehilangan tanahnya. Ilmu tidak lagi masuk lewat guru, teladan, dan ritme batin, tetapi lewat layar, klik, dan algoritma. Dalam konteks ini, peran tradisi sebagai “memori epistemik” menjadi jelas. Tradisi adalah cara umat Islam menjaga bukan hanya isi ilmu, tetapi cara hidup bersama ilmu. Tradisi menyimpan bentuk-bentuk —baik dalam simbol, bahasa, waktu, maupun struktur sosial— yang memungkinkan ilmu meresap pelan-pelan dan membentuk manusia secara utuh. Ketika bentuk-bentuk itu dianggap remeh atau usang, fungsi epistemiknya ikut hancur.
Ketika kita menjadi pribadi yang bisa tahu banyak tetapi tidak jadi siapa-siapa, maka sudah saatnya kita bertanya dengan jujur: apa gunanya ilmu jika ia tidak menjadikan kita lebih tenang, lebih rendah hati, dan lebih dekat kepada Tuhan? Jika jawabannya nihil, yang salah mungkin bukan ilmunya, tetapi tradisinya yang sudah kita lepaskan terlalu lama. Jika keterputusan tradisi telah mencabut akar epistemik umat Islam, maka dunia digital dan sistem pendidikan modern mempercepat kerusakan batang dan daunnya. Apa yang dahulu diwariskan secara lambat, ritualistik, dan penuh kehadiran kini dikemas ulang dalam format instan, cepat, dan dangkal. Media sosial, dengan seluruh kekuatannya dalam menyebarkan informasi, juga mempercepat proses banalitas pengetahuan.
Di ruang digital, ilmu agama berubah menjadi konten. Potongan video singkat, kutipan motivasional, atau ceramah penuh retorika mengambil alih ruang refleksi. Ulama atau guru tidak lagi dikenali melalui proses ruhani dan sanad, tetapi melalui jumlah follower (pengikut) dan engagement rate (tingkat keterlibatan). Dari gejala ini, muncul apa yang oleh banyak pengamat disebut sebagai “otoritas algoritmik”, yaitu otoritas yang lahir dari viralitas, bukan dari validitas. Sementara itu, sistem pendidikan modern belum mampu membendung arus otoritas algoritmik. Dalam banyak institusi Islam kontemporer, kurikulum dibangun dengan logika efisiensi, bukan pendalaman. Hubungan guru-murid menjadi administratif. Waktu kontemplatif digantikan oleh deadline. Tradisi tikrar (pengulangan materi) dan tafakkur (merenung, berpikir mendalam, dan mengambil hikmah) dianggap lambat dan tidak produktif. Akibatnya, pembentukan karakter ilmiah dan spiritual murid menjadi lemah. Mereka bisa menjawab soal, tetapi tidak tahu bagaimana hidup bersama ilmu yang mereka pelajari.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah hilangnya adab dalam berilmu. Kritik terhadap otoritas ulama tidak lagi dibingkai dalam kerendahan hati, tetapi dalam nada destruktif dan arogan. Generasi yang terbiasa belajar lewat gawai sering kali merasa setara dengan gurunya. Bahkan, mereka menganggap otoritas tradisional sebagai “kuno” dan tidak relevan. Padahal tanpa adab, ilmu tidak masuk ke hati. Ilmu kemudian justru menjadi alat pembenaran diri. Dalam situasi ini, kita bukan hanya kehilangan struktur lama. Kita bahkan kehilangan kemampuan untuk percaya. Tidak percaya pada guru, tidak percaya pada otoritas, dan bahkan tidak percaya bahwa ilmu bisa mengubah hidup. Dalam konteks ini, tradisi yang dahulu menjadi fondasi kepercayaan epistemik, telah digantikan oleh opini pribadi dan selera massa.
Di tengah keraguan terhadap yang lama (tradisi), sangat urgen untuk ditegaskan bahwa tradisi bukan soal kembali ke masa lalu. Tradisi bukanlah museum yang menyimpan bentuk-bentuk kuno, melainkan kerangka hidup yang menjaga ilmu tetap terhubung dengan makna. Justru di zaman yang tergesa-gesa dan terfragmentasi inilah, tradisi menjadi semakin relevan. Hal ini karena tradisi menawarkan sesuatu yang paling langka, yaitu ketenangan, kedalaman, dan kesinambungan. Yang penting untuk dihidupkan bukan sekadar bangunan madrasah lama atau penampilan simbolik, tetapi fungsi-fungsi epistemik yang dahulu pernah mendayahidupkan tradisi Islam. Fungsi kehadiran guru bukan hanya untuk menjelaskan, tetapi untuk membimbing. Dalam fungsi ini, guru bertugas untuk menciptakan kondisi keilmuan secara positif. Murid dibimbing secara perlahan untuk membentuk dirinya, bukan hanya didorong untuk menghafal materi. Murid disadarkan akan pentingnya ilmu untuk menyentuh Tuhan dan menyucikan jiwa, bukan hanya didorong untuk mengejar ilmu demi nilai atau gelar.
Tradisi mengajarkan bahwa ilmu tidak netral. Ilmu selalu bergerak menuju sesuatu: entah memperkuat ego atau menghancurkannya; entah menjauhkan dari Tuhan atau mendekatkan kepadaNya. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan arah, tradisi berperan menjaga orientasi, bukan hanya isi. Yang perlu ditanamkan oleh tradisi adalah sikap, bukan hanya pengetahuan. Warisan berharga yang harus dilestarikan oleh tradisi adalah irama batin dalam cara memahami, bukan teks semata. Dengan kesadaran ini, tradisi tidak bertentangan dengan zaman. Ia justru bisa menjadi penuntun baru di tengah kebingungan epistemik kontemporer. Tradisi bisa hadir dalam ruang pendidikan modern dengan cara yang cerdas dan esensial —asal tidak direduksi jadi formalitas. Sanad bisa dihidupkan kembali dalam bentuk mentoring yang jujur. Adab bisa diajarkan melalui keteladanan, bukan sekadar modul. Waktu sakral bisa diciptakan kembali dalam bentuk ritme belajar yang manusiawi, fleksibel, dan tidak membosankan.
Relevansi tradisi bukan karena ia sempurna di masa lalu, tetapi karena ia membawa cara mengenali ilmu sebagai jalan transformasi dan tidak sekadar mengejar prestasi. Dalam bingkai transformasi diri, selama umat masih mencari ilmu yang menumbuhkan jiwa, selama itu pula tradisi punya tempat yang tak tergantikan. Menyambung kembali tradisi tidak berarti membalik waktu. Renaisansi tradisi mempresentasikan pemikiran dan gerakan untuk membangun ulang orientasi, bukan sebatas menghidupkan bentuk lama secara mekanik. Tantangannya adalah: bagaimana nilai dan struktur epistemik tradisional bisa dihadirkan kembali dalam dunia yang berubah, tanpa kehilangan jiwa dan tanpa menjadi “tiruan yang tak bergerak”. Untuk menghadapi tantangan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah strategis.
Langkah pertama adalah menumbuhkan kembali kesadaran bahwa ilmu bukan sesuatu yang netral. Ilmu mengubah kita atau mengerdilkan kita, tergantung pada niat, cara, dan ekosistem yang membungkusnya. Untuk itu, pendidikan saat ini harus menggeser fokus dari penguasaan konten ke pembentukan watak ilmiah dan ruhani. Inisiasi ini bukan dengan menolak capaian sains atau metode modern, tetapi memodifikasinya sambil menyuntikkan kembali (ke dalamnya) adab, kontemplasi, dan kedekatan guru-murid dalam interaksi belajar yang humanistik.
Langkah kedua: memulihkan hubungan antar manusia dalam proses belajar. Hubungan guru dan murid tidak boleh jadi formalitas administratif. Ruang dialog, mentoring, dan pembinaan perlu dihidupkan kembali, bukan sebagai program tambahan tetapi sebagai inti dari proses pendidikan. Sanad bukan sekadar rantai nama, tetapi kepercayaan dan pembentukan jiwa dari satu generasi ke generasi lain. Tanpa ini semua, ilmu tidak akan pernah menghidupkan, meski diproduksi secara terus-menerus.
Langkah ketiga adalah menghadirkan kembali ritme dan simbol dalam kehidupan ilmiah Muslim. Pengulangan (tikrar) bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan untuk mendalamkan pemahaman. Waktu-waktu sakral, bentuk ritual dalam belajar, bahkan cara menyusun ruang belajar bisa difungsi-arahkan untuk memulihkan makna yang selama ini hilang. Kita butuh belajar dengan tubuh dan waktu, bukan dengan pikiran semata.
Langkah klimak adalah menghidupkan kembali tradisi sebagai kesadaran kolektif. Langkah ini perlu dilakukan sebagai ajakan kepada seluruh lapisan umat Islam untuk mengaktualisasikan kembali prinsip-prinsip primordial dalam tradisi keilmuan Islam: bahwa ilmu adalah amanah, bahwa belajar adalah tazkiyah, dan bahwa ilmu bisa menjadi alat yang menyesatkan bila tidak dikonstruksi dengan struktur yang benar.
Kita sadar bahwa kita tidak akan bisa mengulang kejayaan madrasah klasik. Kita juga tidak akan pernah kembali sepenuhnya ke majelis-majelis ulama besar di masjid-masjid kuno. Akan tetapi, satu hal yang masih mungkin, dan bahkan sangat mendesak untuk dilakukan, adalah menyambung kembali ruh belajar yang dahulu membuat ilmu itu hidup. Kita bisa membangun kembali ruang-ruang kecil, di mana ilmu tidak hanya diajarkan tetapi dihidupkan, guru tidak hanya pembicara tetapi pembimbing, dan murid tidak hanya pencari jawaban tetapi pencari bentuk diri. Tradisi tidak meminta kita menjadi seperti masa lalu. Ia hanya meminta satu hal: untuk menjadi manusia yang layak menerima ilmu. Tujuan holistik ini harus dimulai dari cara kita mendekat kepada ilmu. Kesungguhan, kesabaran, dan kerendahan hati adalah modal utama untuk mencapai puncak dari tujuan tersebut, yakni tersambungnya kembali tradisi yang pernah putus.
Di tengah dunia yang sibuk memproduksi informasi, kita butuh lebih banyak orang yang menghidupi makna. Di tengah sistem pendidikan yang terlalu cepat, kita butuh tempat untuk melambat dan menyerap. Di tengah kehilangan arah epistemik, kita butuh kompas. Semua kebutuhan ini bisa direalisasikan melalui tradisi Islam yang holistik dalam universalitas maknanya. Hal ini karena tradisi Islam —sejauh ini— adalah satu-satunya peta yang pernah dimiliki umat ini untuk menjadikan ilmu sebagai jalan pulang. Jika ruang-ruang tradisi yang holistik ini pernah tertutup, maka mari kita buka kembali ruang itu —dalam diri kita, di lingkungan belajar kita, dan dalam cita-cita keilmuan kita. Sebab, ilmu yang tidak menumbuhkan jiwa hanya akan memperluas jarak antara kita dan kebenaran; dan jarak itu hanya bisa dijembatani oleh satu hal, yaitu “tradisi yang hidup, menghidupkan, dan menghidupi.”