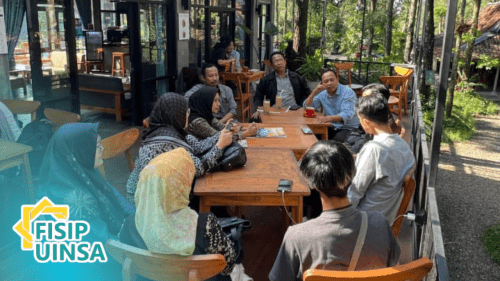Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
Berhenti total. Sama sekali tak bisa jalan. Dan memang tidak diperbolehkan. Dari arah barat tak diizinkan. Begitu juga dari arah yang berlawanan. Semua laju ditahan. Apakah itu kendaraan mobil yang dijalankan. Ataukah motor yang dikendarakan. Semua harus dihentikan. Distop. Tak ada yang bisa dinegosiasikan. Melaju berarti celaka. Berdiam di tempat akan selamat. Semua terkena pengaturan jalan itu. Bahkan, pejalan kaki pun harus menunggu. Sama saja. Apakah Anda pejabat atau bukan. Apakah Anda sedang dengan kendaraan dinas atau tidak. Semua terkena aturan yang sama. Berhenti. Jegreg, kata orang Surabaya.
Situasi itu kulihat sendiri. Kusaksikan sendiri. Dengan mata kepalaku sendiri. Bukan cerita orang lain. Bukan hasil informasi orang lain. Tentu, karena kuketahui sendiri, maka akupun bisa bercerita detil. Bahkan menggambarkan situasi yang sedang terjadi. Dengan jeli. Sesuai yang kudapati. Di pagi itu. Jumat tanggal 24 Mei 2024. Jam 10:15 WIB. Di jalanan di Desa Keloposepuluh. Gedangan. Sidoarjo. Kala itu libur bersama. Aku dan isteriku lagi ingin menikmati jalanan. Healing tipis-tipis di seputar Sidoarjo. Sambil mengenang masa pandemi Covid-19 yang membuat aktivitasku dan keluarga kecilku terbatas. Hanya bisa menikmati situasi luar rumah hanya dari kendaraan.
Nah, begitu mendapati jalanan di sekitar Desa Keloposepuluh berhenti sama sekali seperti itu, akupun mulai bertanya-tanya. Ada apakah ini? Mengapa berhenti jegreg? Mengapa distop total? Beberapat saat kemudian kumulai tahu jawabannya. Oh ternyata, saat itu jalanan sedang dikosongkan. Di-clear up. Untuk memberi kesempatan alat berat untuk bermanuver. Mulai dari meratakan tanah. Memasangkan box culvert ke galian tanah. Hingga memindahkan box culvert dari sisi kanan ke sisi kiri jalan. Alat berat itu mulai dari backhoe hingga forklift. Maka, untuk keselamatan semua orang yang ada di jalanan itu, maka jalanan itu pun harus ditutup total untuk beberapa saat lamanya.
Nah, saat semua orang dan semua kendaraan diberhentikan tanpa pilih-pilih, aku pun salut. Saat semua pejalan kaki distop tanpa pilih kasih, aku juga angkat topi. Saat semua diperlakukan sama, pula aku memberi hormat. Kubangga. Karena layanan dibuat setara. Berkeadilan untuk semua. Dan semua diperlakukan setara. Layanan di jalanan dibikin tak mengenal siapa yang sedang berada di tengahnya. Itu top bingit! Bukankah begini seharusnya ruang publik itu dibangun dan dijalankan. Sungguh senang sekali saat kumendapati kebijakan penutupan sementara jalanan itu dilakukan sekeren yang diharapkan.
Namun, semua itu tak berlangsung lama. Kekagumanku itu musnah tiba-tiba. Penghormatanku itu sirna seketika. Apresiasiku hilang begitu saja. Tak bertahan lama. Tak seperti beberapa menit sebelumnya. Yang bikin kukagum atasnya. Sebab, begitu jalan mulai dibuka setelah ditutup total hampir sepuluh menit lamanya, mataku terbelalak dengan hebatnya. Tak karuan dibuatnya. Penglihatanku dihadapkan pada pemandangan yang kontras. Atas urusan integritas. Kagetku tentu luar biasa. Sebelumnya tak kusangka. Lalu membuat nuraniku mulai terusik. Moral publikku mulai tercabik-cabik.
Mengapa? Karena tiba-tiba muncul seorang lelaki. Seiring dengan mulai bergeraknya kendaraan di bagian depan kemacetan. Seiring pula dengan mulai terbukanya jalanan. Awalnya, kupandang lelaki itu sedang mengatur pergerakan kendaraan. Yang berlawanan. Dari arah barat dan timur. Agar kemacetan mulai terurai. Kendaraan pun mulai bisa bergerak ke depan. Sesuai arah masing-masing. Di awal pandangan itu, tampak lelaki itu sangat baik sekali. Memberi manfaat yang tinggi sekali. Kepada semua pengguna jalan kala itu. Karena dia ikut mengatur laju kendaraan dan pejalan kaki di sepanjang jalan yang sempat ditutup itu.
Tapi, begitu kuperhatikan detil pergerakan lelaki itu, kekaguman dan apresiasiku itu mulai terkoreksi. Dia memang membawa sebuah alat semacam tongkat berlampu merah di tangan. Bahasa sulitnya, traffic baton. Alat itu biasa digunakan oleh aparat pengatur ketertiban lalu lintas. Dan memang lelaki itu menggunakan alat itu untuk mengatur pergerakan lalu lintas di jalanan itu. Namun di tangan kirinya, lelaki itu membuatku harus mengoreksi apresiasi tinggiku sebelumnya itu. Sebab, ternyata kulihat sekali. Sambil jalan, dia tenteng kotak kardus bekas snack atau makanan ringan. Di tangan sebelah kiri. Jadi tangan kanan memegang alat pengatur lalu lintas. Dan tangan kiri megang kardus kertas.
Absurd dan ironis. Itulah penilaianku saat itu. Mengapa? Sebab, lelaki itu tampak sekali menjadi bagian dari pengelola proyek pemasangan box culvert saluran air itu. Sebab, dia tampil sebagaimana pekerja lainnya atas proyek itu. Dia gunakan hoodie. Untuk mengamankan dirinya dari sengatan sinar matahari yang mulai terasa panasnya. Dia juga gunakan sepatu, yang dari merek dan jenisnya tampak bisa dimiliki oleh pekerja proyek. Hanya, terlepas dari tampilan semua itu, dia gerakkan kotak kardus bekas snack atau makanan ringan itu ke setiap pengguna jalan yang lewat.
Tampak sekali dengan kotak kardus itu, dia meminta atau berharap donasi. Dari para pengguna jalan yang sedang antri. Karena adanya kemacetan di sana-sini. Di jalanan dan sekelilingnya akibat jalan dan saluran air yang diperbaiki. Donasi itu dalam bahasa halusnya disebut juga dengan “bunga-bunga sosial”. Biasanya diberikan karena diminta. Atas sebuah kegiatan yang dilakukan di depan banyak warga. Bisa bentuknya menyanyikan lagu yang disuka. Atau tampilan yang diperagakan. Bisa tari. Bisa pula bermain instrumen musik yang ada. Sebagai bentuk penghargaan atas yang telah ditampilkan. Oleh beragam kegiatan yang dalam bahasa sederhananya disebut ngamen.

Memanfaatkan kesempatan adalah konteks terjadinya aksi minta donasi di atas. Padahal, tugas mengatur lalu lintas di jalanan sepanjang proyek pembangunan itu adalah menjadi bagian dari kewajiban yang melekat pada pelaksana proyek pembangunan itu. Bukan hanya melaksanakan proyek pembangunan saluran air itu, tapi juga mengatur ekses kemacetan jalan yang timbul akibatnya. Kalau pengaturan lalu lintas jalan itu sudah menjadi tugas dan kewajibannya, mengapa dilakukan aksi minta donasi? Mengapa dibiarkan ada aksi ambil untung di balik kemacetan jalanan?
Aksi minta donasi ala pengatur jalanan di atas bisa mewujud dalam beragam jenisnya. Sesuai bidang dan kewenangannya. Misal, muncul praktik ijon dalam proyek pembangunan. Satu pihak memiliki kewenangan penentuan proyek dan penganggaran, dan yang satu lagi pelaksana proyek. Muncul juga istilah NPWP. Nomor piro wani piro. Nomor berapa berani bayar berapa. Praktik ini biasanya terjadi pada momen kontestasi politik. Mulai dari Pilkades sampai Pilpres. Hal yang sama dengan istilah serupa. Mirip. Namanya tawadu’. Kepanjangannya, tau warna duit. Diplesetkan dari kata dan makna aslinya yang berarti rendah hati. Semua istilah ini berkembang di luaran untuk menggambarkan beragam praktik culas atas integritas di atas.
Itulah macam-macam praktik yang oleh manajemen modern disebut dengan istilah rent-seeking. Aksi buntung ambil untung. Praktik ambil keuntungan di balik sebuah kewenangan. Praktik berebut profit di tengah situasi sulit. Kewenangan yang seharusnya ditunaikan malah ditukar dengan keuntungan pribadi yang menyilaukan. Amanah yang harusnya dibayar lunas dengan kinerja terbaik dipertukarkan dengan aksi berburu cuan. Untuk kepentingan pribadi yang dipuja untuk dipuaskan.
Praktik berburu donasi ala pengatur kemacetan jalanan Desa Keloposepuluh di atas memang tampak kecil. Jika dilihat dari sisi jenis dan skalanya. Tapi, bukankah mental publik tak boleh jatuh oleh alasan apapun? Bukankah moral publik juga tak boleh runtuh oleh jenis kelacuran apapun? Bukankah karakter warga tak boleh hanyut oleh keburukan apapun atas alasan apapun pula? Atas kepentingan menjaga mental, moral dan karakter publik ini, maka aksi minta donasi harus dijadikan sebagai pelajaran untuk membangun tata kelola ruang publik yang baik.
Caranya? Penting memang kita mengambil pelajaran dari kejadian aksi minta donasi di jalanan di atas. Tapi penting pula untuk melakukan perluasan dari pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kejadian tersebut ke praktik hidup publik lebih luas. Maka karena itu, ada dua pelajaran penting yang harus diambil dan diperluas ke kejadian hidup bersama secara lebih luas dimaksud. Terutama untuk institusi publik yang menjadi awal bagi perencanaan dan perwujudan kebajikan bersama pula.
Pertama, bangunlah lembaga yang dicinta terlebih dulu dari integritas pengelola. Jangan anggap sepele integritas semua sumber daya manusia yang ada. Mulai dari pimpinan hingga pegawai level paling bawah. Belajarlah dari kejadian dan aksi minta donasi pada proyek pembangunan saluran air di Desa Keloposepuluh di atas. Pegawai pengatur kemacetan memang bukan pemegang kewenangan kepemimpinan di institusi pengelola proyek itu. Tapi aksinya dengan melakukan praktik ambil untung melalui koleksi donasi pengguna jalan tetap dibiarkan oleh perusahaan yang memperkerjakannya. Akibatnya, aksi ambil untung melalui koleksi donasi itu terjadi dengan leluasanya. Tanpa dilakukan pengawasan atasnya.
Praktik pembiaran atas keburukan adalah bentuk kelalaian. Dan profesionalisme tak mengenal istilah kelalaian dalam kamus kinerja. Maka, pimpinan yang membiarkan keburukan menyeruak adalah pemimpin yang lalai. Walaupun keburukan itu dilakukan oleh pegawai yang berada pada jabatan terbawah sekalipun. Tentu, pemimpin seperti ini tak masuk kategori profesional. Karena pemimpin profesional sudah barang tentu menjadikan kecakapan mitigasi risiko sebagai ukuran. Karena, manajemen risiko (risk management) diciptakan untuk menciptakan keahlian dan kecakapan yang dibutuhkan bagi profesionalisme kepemimpinan manajerial.
Kedua, iringi pelaksanaan progam kegiatan dengan pengawasan. Jadikan keduanya seperti dua sisi mata uang. Two sides of the same coin. Keduanya bisa dibedakan. Tapi tak bisa dipisahkan. Bisa dilihat berbeda. Tapi tak bisa dipandang terpisah. Sebab, keduanya pada dasarnya adalah satu kesatuan. Berbeda itu hanya soal uraian tugas pekerjaan. Tapi sejatinya kewajibannya sama-sama untuk menjamin terwujudnya kepentingan kebajikan bersama melalui pekerjaan yang berbeda uraian namun serupa tujuan. Itulah substansi managerial competence atau kecakapan pengelolaan.
Lalu pertanyaannya, bagaimana menjamin terlaksananya pelaksanaan program kegiatan dengan pengawasansecara baik? Bak ungkapan two sides of the same coin? Kecakapan pengelolaan mempersyaratkan adanya instrumen pengawasan secara berlapis. Bukan hanya di level hilir. Tapi juga di hulu. Pengawasan di level hilir mewajibkan seluruh tahapan pelaksanaan di bawah pengawasan yang rapi. Agar tak terjadi penyelewengan. Sekecil apapun cakupan. Jangan remehkan ketidakwajaran. Apalagi terjadi berketerusan. Meski kecil dan dilakukan oleh pelaksana lapangan. Apapun jenis jabatan dan kewenangan. Apalagi dilakukan oleh pemilik kewenangan kepemimpinan. Jangan kesampingkan.
Pengawasan di level hulu berarti tugas dan kewajiban pengawasan sudah harus dimulai sejak perencanaan. Nama lainnya disebut juga dengan istilah pengawasan dini. Jadi, petugas pengawasan sudah harus mendampingi kerja petugas perencanaan sejak awal sebuah gagasan dikonkretkan. Melalui sejumlah tahapan. Hingga muncul sebuah program yang diharapkan. Dengan begitu kerja pelaksanaan sudah diiringi dengan mitigasi resiko sedetil mungkin. Termasuk pengawasan atasnya.
Membangun adalah ibadah. Karena akan memudahkan orang banyak untuk menunaikan kebutuhan hidupnya. Tapi menjamin tata kelola yang baik untuk pelaksanaan program pembangunan adalah kemuliaan. Karena itu, ia juga ibadah. Sama saja walaupun beda tahapan pekerjaan. Dan karena itu pula, membiarkan keburukan menggurita sangat tercela. Termasuk membiarkan rent-seeking. Aksi buntung ambil untung. Praktik berburu cuan di balik kewenangan. Ironi bagi kita semua yang dikenal sebagai kaum beragama. Maka tak ada cara lain: Jangan bikin mental dan moral publik runtuh oleh praktik pembiaran atas keburukan. Walau itu tampak kecil dalam penglihatan. Karena kemuliaan tak mengenal besar atau kecil. Termasuk untuk urusan kebajikan publik yang mengikat kehidupan kewargaan.