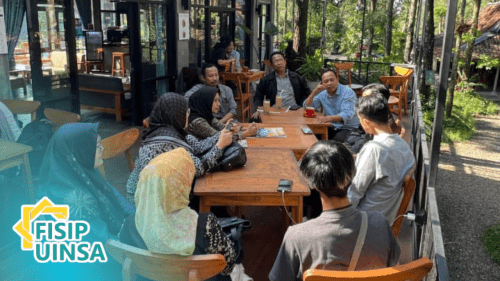Tegaknya demokrasi ditandai dengan adanya oposisi sebagai perimbangan atas kekuasaan. Sebaliknya demokrasi akan mengalami pembusukan lebih cepat ketika adanya indikasi yang kuat terhadap peniadaan suara-suara kritis yang berbasi etika-moral. Pilpres 2024 menandai adanya fenomena kompetisi yang berujung adanya penyingkiran terhadap etika-moral. Indikasi adanya kecurangan yang dilakukan secara kasat mata, namun pemenang Pilpres menganggapnya sebagai sebuah halusinasi dari pihak yang kalah. Uniknya, pemenang Pilpres berupaya merangkul pihak yang kalah, dan hal itu mendapatkan sambutan positif. Dengan alasan persatuan dalam membangun bangsa, dua pihak ini seolah melupakan pertarungan yang seru sebelumnya, dan membiarkan kalangan grassroot yang telah mengalami fragmentasi yang hebat.
Demokrasi dan Oposisi
Demokrasi mengimpikan adanya pemerintahan yang bisa mensejahterakan rakyat. Hal ini karena didasarkan pada impian lahirnya pemimpin dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan menerapkan demokrasi yang jujur dan adil diharapkan lahir pemimpin yang memperjuangkan aspirasi rakyatnya. Namun dalam kenyataan empirik, justru berbalik, dengan lahirnya pemimpin yang menjadi ancaman kehidupan demokratis.
Proses demokrasi yang bersifat ritualistik telah menutup mata terjadi praktek politik yang curang dan culas. Alih-alih menerapkan prinsip adil dan jujur, praktek politiknya justru membiarkan kedzaliman dan ketidakjujuran. Dengan kata lain, Impian untuk melahirkan pemimpin yang demokratis justru mengorbankan etika-moral.
Praktek politik nepotisme yang diawali dengan pembiaran atas politik cawe-cawe yang dilakukan rezim, dan hal itu ditonton publik secara kasat mata. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pilpres 2024 telah mendalilkan bahwa tidak ada praktek nepotisme dalam Pilpres kali ini. Hal ini berimplikasi adanya delegitimasi karena pilpres kali ini telah menjegal etika-moral dalam berpolitik.
Keluarnya Keputusan MK nomor 90 tahun 2023 yang meloloskan anak presiden, sebagai calon wakil presiden, menjadi awal petaka adanya marginalisasi etika-moral dalam kehidupan bernegara. Cawe-cawe Anwar Usman, selalu ketua MK untuk meloloskan keponakannya (Gibran) telah menjadi pintu masuk adanya kekisruhan politik yang berujung sengketa Pilpres.
Kekisruhan itu berlanjut dengan adanya praktek politik gentong babi (Pork Barrel Politic), dengan lahirnya politik Bantuan Sosial (Bansos). Praktek politik Bansos ini menggelinding menjadi bola panas yang melahirkan kecurigaan bahwa kemenangan salah satu pasangan calon (Paslon) disebabkan oleh back up yang kuat dari rezim ini. Bahkan dalam politik Bansos ini, presiden turun langsung untuk membagi-bagi bantuan, dan dibantu oleh para Menteri yang tergabung dalam koalisi pemenangan capres-cawapres.
Praktek politik yang demikian bukan hanya menyingkirkan etika-moral tetapi menginjak-injaknya untuk kepentingan sesaat. Demi meloloskan anaknya, rezim bersama elite pendukungnya ini rela menutup mata terjadinya politik nepotisme. Oleh karena itu, Prabowo-Gibran memang menang secara elektoral, tetapi mengalami cacat moral. Artinya, secara formal menang, dan terpilih sebagai presiden tetapi masyarakat akan terus mempermasalahkan karena telah mengalami cacat moral.
Pembusukan Demokrasi
Proses saling rangkul ini dari dua pihak yang sebelumnya bertarung sehingga berujung hilangnya oposisi jelas merupakan pembusukan politik (political decay) dalam demokrasi. Fenonema balik badan yang dilakukan oleh mereka yang sebelumnya berteriak adanya kecurangan. Namun begitu kalah, mereka meunjukkan sinyal untuk merangkul kembali pihak yang sebelumnya dituduh melakukan kecurangan.
Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah memberi sinyal untuk bergabung dalam pemerintahan. Hal ini ditunjukkan oleh Surya Paloh sebagai ketua Partai Nasdem yang mendatangi Prabowo, dan Muhaimin Iskandar selaku pihak PKB, yang menyambut baik ajakan Prabowo. Hal ini jelas sebagai pembusukan demokrasi.
Hal ini sangat kontras dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yang menawarkan nilai-nilai agung dalam mewujudkan tatanan atau peradaban masyarakat yang kokoh. Nabi menjanjikan masyarakat yang unggul dengan mentauhidkan Allah. Alih-alih menerima, tokoh Quraisy menentang dengan mencoba menghentikan perjuangan Nabi Muhammad yang menerapkan politik nilai. Mereka pun menawarkan kekuasaan, harta, wanita untuk menghentikan politik nilai itu. Nabi pun menolaknya dan tetap gigih dalam menjalankan etika-moral itu.
Kegigihan nabi dalam memperjuangkan politik nilai ini tidak menghentikan para elite Quraisy. Mereka meminta Nabi Muhammad untuk mengubur dalam-dalam politik nilai itu. Maka Allah pun menegur nabi, dan mengancam tidak akan dibacakan ayat-ayat agung, sehingga membiarkan masyarakat Quraisy tidak dipandu oleh nilai-nilai agung. Hal ini ditegaskan Allah firman-Nya :
قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَاۤ اَدْرٰٮكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ
“Katakanlah (Muhammad), “Jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak (pula) memberitahukannya kepadamu.” Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya (sebelum turun Al-Qur’an). Apakah kamu tidak mengerti ?” (QS. Yunus : 16)
Allah mengancam mereka dengan membiarkan hidup dengan ketiadaan nilai-nilai agung yang akan memandunya. Allah ingin menunjukkan bahwa praktek bermasyarakat atau bernegara yang tidak dipandu oleh etika-moral pasti akan melahirkan kekisruhan dan berujung pembusukan serta kehancuran dari dalam.
Apa yang terjadi di negeri ini, tidak berbeda dengan narasi di atas, dimana tindak pelanggaran yang dilakukan oleh elite politik dengan menabrak kesepakatan bersama. Mereka tutup mata terhadap praktek politik nepotisme, dan membiarkan kecurangan. Nepotisme yang terjadi secara kasat mata, dengan keluarnya Keputusan MK nomor 90, terbukti telah melahirkan kegaduhan yang berkepanjangan. Praktek kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) merupakan turunan dari politik nepotisme yang mengalami pembiaran.
Kegaduhan itu tidak berhenti ketika MK memutuskan untuk menolak permohonan para pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Pilpres. Masyarakat mengalami pergolakan berkelanjutan, kendati sengketa Pilpres telah diputuskan siapa pemenangnya. Hal ini disebabkan adanya pembusukan etika-moral dalam demokrasi dengan membiarkan atau tutup mata terhadap kecurangan.
[Slamet Muliono Redjosari; Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat]