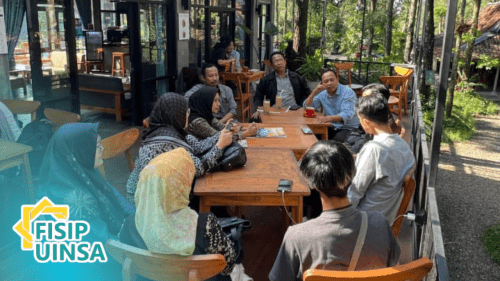MERAWAT FILANTROPI PUASA
Oleh: Dr. Wasid Mansyur, SS., M. Fil.I
(Sekretaris Pusat Ma’ad Al-Jami’ah dan Dosen FAHUM UINSA)
 Berdasarkan pada kenyataan, semua orang ingin memiliki kekayaan yang melimpah. Karenanya, menjadi wajar, bila kemudian bekerja menjadi bagian dari ikhtiyar hidup mereka untuk mencapai Impian itu. Tidak sedikit, untuk memujudkan mimpi itu jarak tempuh tidak menjadi halangan, termasuk waktupun tidak menjadi alasan untuk mundur. Intinya asal kalkulasinya jelas, dan seseorang yakin bahwa “cuan” pasti didapat, maka segala upaya selalu dilakukan siang dan malam sebab ada kepuasan tersendiri mendapat kekayaan dengan usaha sendiri daripada menyerah diri atas nama nasib dengan cara menjadi peminta-minta.
Berdasarkan pada kenyataan, semua orang ingin memiliki kekayaan yang melimpah. Karenanya, menjadi wajar, bila kemudian bekerja menjadi bagian dari ikhtiyar hidup mereka untuk mencapai Impian itu. Tidak sedikit, untuk memujudkan mimpi itu jarak tempuh tidak menjadi halangan, termasuk waktupun tidak menjadi alasan untuk mundur. Intinya asal kalkulasinya jelas, dan seseorang yakin bahwa “cuan” pasti didapat, maka segala upaya selalu dilakukan siang dan malam sebab ada kepuasan tersendiri mendapat kekayaan dengan usaha sendiri daripada menyerah diri atas nama nasib dengan cara menjadi peminta-minta.
Namun, sadar atau tidak, kekayaan yang kita kumpulkan dengan susah payah sejatinya bukanlah milik kita secara utuh yang harus kita bawah selamanya. Buktinya ketika kematian tiba, kekayaan yang kita kumpulkan mati-matian diwaktu hidup ternyata semuanya tidak menyertai kita, bahkan kekayaan itu secara otomatis menjadi harta warisan dan selanjutnya menjadi hak ahli waris untuk dibagikan. Tidak jarang, hanya karena persoalan harta waris seseorang harus bertengkar dengan saudaranya disebabkan tidak puas dengan pembagian atau bernafsu memperoleh lebih banyak. Hakekatnya, yang menyertai kita mulai hidup hingga di tempat keabadian, berdasar pada nilai-nilai Islam, adalah harta-harta yang kita infakkan untuk kebaikan, terlebih untuk “shadaqah jariyah”.
Untuk itu, jangan pernah lupa berbagi kepada orang lain atas kekayaan yang kita miliki. Apa yang kita berikan kepada orang lain adalah salah satu cara kita untuk menyelamatkan diri sendiri dimasa yang akan datang, yakni hari pembalasan. Orang yang terbiasa menumpuk harta, sementara ia mengabaikan tetangganya dalam keadaan lapar, anaknya putus sekolah, orang tua yang sakit-sakitan yang tidak mampu pergi ke rumah sakit sebab tidak ada biaya, dan lain-lainnya, maka ia termasuk bagian dari model Pecinta Dunia (Hubbu al-Dun-ya).
Bukankah, Allah SWT mengingatkan kepada kita dalam al-Qur’an tentang cerita Qorun; Sang Hubbu al-Dun-ya Sejati, yang ceritanya diabadikan dalam surat al-Qasas; 76-82. Ia adalah kaum dari Nabi Musa, bahkan masih anak dari pamannya yang diberi kekayaan yang melimpah oleh Allah SWT. Begitu banyak kekayaan yang dimilikinya, al-Qur’an menggambarkan bahwa kekayaan Qorun yang begitu banyak harus diletakkan di gudang yang sangat besar. Kunci-kuncinya yang banyak tidak cukup dibawa oleh satu orang melainkan harus dipikul oleh banyak orang.
Tapi, sayangnya melimpahnya kekayaan ternyata menjadikan Qorun lupa diri, bahkan terus berlagak sombong kepada siapapun, termasuk kepada Nabi Musa. Perilaku yang dilakukannya berbeda, ketika ia masih miskin yang selalu mendekat kepada Nabi Musa untuk “merengek-rengek” agar didoakan menjadi orang sukses dan kaya raya. Berbagai cara sudah diingatkan, agar Qorun tidak terpedaya oleh hartanya, tapi sayangnya ia semakin hubbu al-Dun-ya, sombong dan angkuh kepada Nabi Musa hingga akhirnya, iapun ditenggelamkan bersama hartanya dalam bumi oleh Allah SWT.
Qorun adalah cerita simbolik tentang manusia pecinta dunia sehingga ia melupakan hak-haknya sebagai hamba. Darinya, disadarkan tentang pentingnya cara pandang bahwa apa yang kita miliki bukan sepenuhnya hasil dari usaha kita, tapi anugerah dari Allah sehingga menjadi wajar bila kemudian anugerah itu juga harus disebarkan luaskan kepada orang lain dengan mengeluarkan infak, shodaqah atau zakat. Karenanya, jiwa filantropi muncul dari kesadaran ini, kesadaran bahwa segala kenikmatan adalah anugerah yang juga harus dibagikan kepada sesama.
Filantropi Puasa
Lantas apa hubungan puasa dengan spirit filantrofis?. Begini, puasa sebenarnya merupakan kebiasaan orang-orang terdahulu dalam rangka agar mereka menjadi manusia seutuhnya (insan kamil). Bahkan _sebagaimana dikatakan Ali Ahmad al-Jurjani dalam bukunya “Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu”- agar impiannya terwujud, orang-orang dahulu sebelum Islam berpuasa sebagai bentuk ekspresi kepatuhan dalam rangka supaya para dewa-dewa yang diyakininya, ikut memberikan kontribusi kemudahan dalam setiap proses melangkah dalam hidup. Dengan puasa, mereka menundukkan hawa nafsu sebagaimana para dewa itu tidak berkaitan sama sekali dengan hawa nafsu sehingga dengan puasa, mereka mampu mengenal dirinya secara utuh sebagai manusia sejati dan disayangi para dewa.
Oleh karenanya, kewajiban puasa dalam Islam tidak bisa lepas dari dimensi ini, walau orientasinya fokus pada Allah SWT (imanan wa ihtisaban). Itu artinya, aktivitas puasa dengan meninggalkan makan, minum dan hubungan seks suami-istri di waktu yang ditentukan memberikan pelajaran spiritual tentang pentingnya menekan nafsu hewani, yang salah satu karakternya adalah suka makan, minum dan berhubungan seks. Mengingat, ketika nafsu hewani menguat dalam diri setiap orang dapat dipastikan akan selalu muncul sikap asal dirinya senang, asal apa yang diinginkan dipenuhi, walau harus menyakiti yang lain.
Maka ketika merenungi kondisi puasa, kita sadar bahwa kondisi lapar, haus dan tidak melampiaskan hawa nafsu adalah satu kondisi yang sangat tidak nyaman dan melelahkan secara fisik. Bagaimana kemudian, jika seseorang mengalami situasi seperti ini setiap hari sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pendidikan, hidup yang nyaman dan lain-lain. Dari sini, mestinya spirit filantrofis dalam puasa tumbuh dalam diri kita semua secara alami, tapi sayangnya tidak semua orang bisa menangkap hal ini sehingga puasa yang dilakukannya masih terjebak pada ritual tahunan belaka.
Filantrofis berasal dari kata filantropi, yang dalam bahasa Yunani dari kata “philein” berarti cinta dan “anthropos” berarti manusia. Maka, filantrofis adalah seseorang yang mencintai sesama manusia sehingga ia berusaha semaksimal mungkin untuk menyumbangkan waktu, uang dan tenaganya tidak lain dalam rangka membantu orang lain. Dalam bahasa Islam, sebagai pembanding kaitannya dengan semangat filantropi kita mengenal tentang konsep infak, shodaqah, zakat, takaful dan ta’awun yang semuanya berkaitan dengan sikap peduli kepada orang lain.
Menariknya, sepanjang Ramadhan semua kegiatan berdimensi filantropi dilipatgandakan pahalanya, termasuk aktifitas kesalehan lainnya. Bahkan sekedar memberikan makan atau minum bagi yang berbuka puasa saja, masih diiming-imingi pahala _berdasarkan sabda Nabi Muhamamd SAW_ seperti pahalanya orang yang melakukan puasa tanpa berkurang sedikitpun. Untuk memperkuat anjuran ini, Nabipun memberikan contoh bahwa ia termasuk orang yang paling dermawan setiap harinya, lebih-lebih dibulan Ramadhan.
Filantropi Ramadhan harus menjadi titik start kita untuk menuju menjadi manusia yang seutuhnya, yang tidak hanya berpikir diri sendiri, melainkan juga memikirkan orang lain. Semangat berbagi di bulan Ramadhan layak diteruskan pada bulan-bulan berikutnya, dengan mempertimbangkan kemaslahatannya yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Bukan hanya itu, semangat ini sebenarnya akan merawat keseimbangan ekosistem kemanusiaan itu sendiri sehingga tidak memunculkan ketimpangan sosial yang lebih besar di negeri ini, misalnya kekayaan hanya berkutat dan dimonopoli oleh para pemodal besar, sementara pemodal pas-pasan harus memutar otak dengan keras agar modalnya tidak hangus akibat pasar yang tidak stabil.
Akhirnya, merawat kebaikan, walau tanpa mempertimbangkan pahala akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Memang spirit filantropi puasa di luar bulan Ramadhan pahala tidak sebesar dalam bulan Ramadhan, tapi kesadaran berfilantropi yang dipraktikkan setiap hari akan melahirkan kebaik-kebaikan yang menggunung; setidaknya meninggalkan jejak-jejak kebaikan dalam hidup. Pastinya, jejak ini akan menjadi catatan penting dalam kehidupan hingga kita unduh manfaatnya dimasa-masa yang akan datang, terlebih pada masa dimana amal seseorang itu menjadi taruannya. Semoga puasa kita tidak sekedar rutinan tahunan.