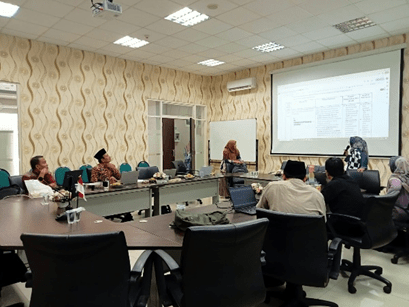Manakah postulat atau rumus dari 2 (dua) ini yang benar? Rumus kesatu; 1+1=2, 2+2=4, 3+3=6, 4+4=8, dan seterusnya. Rumus kedua; 1+1, 2+2, 3+3, dan seterusnya hasilnya TIDAK TERBATAS. Jika kedua rumus atau postulat itu ditanyakan kepada setiap individu, dengan serta merta mayoritas atau bahkan seluruhnya pasti memilih rumus pertama diklaim sebagai yang benar. Sebaliknya, rumus kedua dinyatakan salah. Kalau tidak percaya tanyakan saja pada setiap diri kita, para mahasiswa kita, orang-orang di sekitar kita. Singkatnya, dari orang pintar hingga orang bodoh, dari orang terdidik hingga orang uneducated, dari professor hingga tidak sekolah pun membenarkan postulat pertama. Jikalau, ada yang juga membenarkan postulat kedua, mungkin perbandingannya 1 berbanding 1.000, bahkan 1 berbanding 1 juta.
Rumus atau postulat pertama jelas benar. Tidak ada orang yang membantah. Justeru kalau ada orang yang membantah dikira dia tidak waras alias gila. Bagaimana dengan rumus kedua? Apakah rumus kedua juga benar? Jawaban singkatnya, rumus kedua juga benar. Bahkan, jika boleh di-grade atau dirangking, rumus kedua lebih benar. Kok bisa? Mengapa tidak bisa! Apakah dapat dijelaskan, dirasionalisasikan, atau diilmiahkan? Mengapa tidak bisa! Postulat atau rumus kedua sesungguhnya ilmiah, rasional, dan logic. Hanya saja, kita malas untuk menelisik mencari kebenaran itu.
Tulisan ringan dengan bahasa awam (ummat) ini mengajak kita semua yang membaca untuk menelusuri sekaligus mendiskusikan tentang hakekat dua kebenaran rumus atau postulat tadi. Kedua rumus itu tanpa kita sadari berlangsung dalam kehidupan kita setiap hari. Rumus itu membimbing kita dalam setiap gerak langkah kita. Bahkan, keduanya membentuk sikap, perilaku, keputusan hingga melahirkan corak pemikiran dan berakhir membentuk tabi’at
Atau akhlak budi setiap diri kita.
Rumus Dominan Beragama Kita
Dalam alam bawah sadar, sering kali tidak didasari betapa jauh kehidupan kita telah demikian dikendalikan oleh apa yang seecara ilmiah disebut sebagai rasionalitas akal, logika, maupun pikiran an sich. Sistem berfikir demikian ini dalam logika modern identik dengan logika positivistik atau sains melalui prinsip-prinsip ilmu pengetahuan modern. Logika inilah yang melahirkan kebenaran pada rumus pertama. Cara berfikir ini memang dibentuk sedari awal setiap individu mengenyam pendidikan mulai dari bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tidak terkecuali tradisi ini juga berlansung dalam sistem pendidikan di pesantren.
Cara berfikir ini juga dalam alam bawah sadar kita membentuk cara kita beragama atau ber-Islam. Sedangkan cara beragama pada akhirnya membentuk praktek maupun model kehidupan beragama. Tengoklah ke belakang hingga hari ini dalam kita beragama. Tanpa kita sadari, model beragama kita selalu di-krus-kan atau dikapitalitasi dengan untung dan rugi. Kita beribadah karena iming-iming surga dan takut neraka. Kalau tidak percaya, coba tanyakan kepada publik umat Islam; apa tujuan mereka beribadah, sebagian besar jawaban karena ingin masuk surga. Mengapa ingin masuk surga, karena sebelumnya ditakuti dengan neraka. Kalau demikian adanya, bukan kah ini termasuk dalam bagian rumus pertama; kalau anda beribadah dengan tekun, maka dijamin masuk surga. Apa bedanya dengan 1+1:2?
Logika ini berbanding terbalik dengan pengalaman seorang perempuan bernama Rabiah al-‘Adawiyah. Ia menolak rumus umum itu. Model bergamanya out of box alias keluar dari mainstream. Sebagai gantinya, ia membuat postulat atau rumus yang identik dengan rumus kedua. Model beragama yang ia bangun begitu terkenal dengan ungkapannya yang masyhur dan melegenda: “ Ya Allah, jika aku beribadah karena ingin surga-MU maka tutuplah surga itu. Jika aku beribadah karena takut neraka-MU, maka masukkan aku ke dalam neraka itu. Tetapi, jika aku beribadah karena rasa cintaku kepada-MU, maka jangan palingkan aku dari-MU.” Model al-‘Adawiyah beribadah ini tidak dilandasi atas hitung-hitungan matematis; untung dan rugi; ingin surga atau takut neraka.
Selanjutnya, mari kita tengok lagi, model beragama kita pada ibadah seputar zakat, infak, sodaqah, dan sejenisnya. Ibadah zakat misalnya, umumnya kita terjebak karena aturan 2,5%. Padahal, dalam dimensi sejarah, lahirnya perintah zakat karena manusia umumnya memiliki sifat bakhil alias hub al-Dunya, tidak ingin berbagi kepada kaum mustadafin. Angka 2,5% adalah rumus pertama dan seolah sifatnya baku. Mengapa baku, karena seseorang hanya mengeluarkan 2,5% itu. Pertanyaannya, apakah adil rezeki dari Tuhan yang melimpah ia hanya mengeluarkan 2,5%? Dibalik tindakan mengeluarkan 2,5%, setiap hamba Tuhan masih harap-harap cemas menginginkan kembali rezeki yang lebih besar. Lagi-lagi, cara berhitung ini jelas-jelas sangat matematis.
Masih terkait zakat, terdapat pelajaran penting untuk direnungkan. Dalam doktrin umum yang telah lama mengkristal terkait tujuan zakat adalah membersihkan harta kita dari KOTORAN. Dari premis ini, logikanya, kotoran itu harus dibuang. Siapa akhirnya yang menerima kotoran dalam bentuk zakat itu? Kotoran itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat disebut asnaf al-Samaniyah. Sampai di sini kita renungkan, begitu teganya kita membuang kotoran (zakat) yang akhirnya diterima dan dimakan oleh para fakir miskin. Dengan kata lain, secara hakiki, kotoran kita dimakan oleh para fakir miskin. Setuju atau tidak setuju silahkan direnungkan. Alih-alih sambil membuang kotoran, kita masih meminta imbalan berupa rezeki yang lebih banyak. Karena itu, di luar zakat dalam ajaran Islam dikenalkan model mengeluarkan rezeki dalam bentuk yang lain; infaq, sodaqah, waqaf, dan seterusnya. Konsideran ini untuk mengimbangi pembuangan kotoran dimaksud.
Selain zakat ibadah apa lagi? Mari kita contohkan ibadah shalat. Bolehkah jika kita mengatakan, ibadah shalat yang kita jalankan tidak luput dari rumus pertama di atas? Bagaimana maksud dan rasionalisasi ibadah shalat kita sebagai bagian dari rumus pertama. Sadar tidak sadar, ibadah shalat, baik shalat mahdlah beserta shalat-shalat sunnah tidak luput dari kapitalisasi maupun berbagai conflict of interest yang bersifat materi (duniawiyah). Shalat kita tidak luput dari harapan akan surga-neraka. Lebih dari itu, ibadah shalat selalu dibumbui dengan berbagai tuntutan, keinginan, maupun berbagai bentuk reward lain kepada Tuhan. Pada setiap shalat fardlu, setiap individu selalu menuntut kepada sang Khalik berupa doa-doa. Saking banyaknya tuntutan melalui berbagai doa, hingga kita tidak mengetahui lagi, apakah tuntutan itu telah dipenuhi oleh-NYA atau ditolak. Bukankah berdoa itu secara hakiki adalah menuntut. Jika tidak setuju dengan diksi menuntut diturunkan menjadi meminta atau bahasa yang lebih halus memohon. Seorang ulama sufi dengan berkelakar mengatakan: “Tuhan itu salah apa, kok setiap kita beribadah selalu dituntut.” Hakekat berdoa tidak seperti selama ini kita fahami. Bagaimana hakekat doa itu? Ruang ini tidak cukup untuk menjelaskan. Perlu ruang tersendiri untuk menjelaskan hakekat doa atau berdoa.
Tidak cukup berbagai tuntutan (berdoa) disampaikan pada shalat fardlu saja. Di luar shalat fardlu pun, yakni shalat sunnah, setiap hamba ini terus menuntut Tuhannya. Saking banyaknnya tuntutan yang disampaikan oleh kita, dinamakan beberapa shalat sunnah yang dari namanya saja berisi doa (tuntutan) dimaksud. Beberapa shalat sunnah yang didesain khusus berisi tuntutan tentunya merujuk kepada Shalat Hajat, Tahajud, Dhuha, dan seterusnya. Tercatat, hanya ada satu shalat sunnah yang tidak menuntut, justeru menyucikan dan mengagungkan sang Tuhan, yakni Shalat Tasbih. Sayangnya, kebanyakan kita tidak memilih jenis shalat sunnah ini.
Dari gambaran 3 (tiga) jenis beribadah di atas cukup kiranya mewakili cara maupun model beragama kita. Jangan-jangan landasan berfikir dalam ibadah selama ini terjerumus kepada hukum ekonomi, yakni serba perhitungan dengan Tuhan. Salahkah jika kita mengatakan ibadah kita sesungguhnya masih bersifat transaksional? Akibatnya, lagi-lagi kita abai dan lalai, Tuhan ditempatkan sebagai obyek atau maf’ul bihi. Tuhan yang begitu agung dikecilkan dan dikerdilkan. Tuhan seolah kita sembah dan diremote dengan kalkulator kita. Jika ketiga ibadah yang penting saja bersifat transaksional dengan sang khalik, tidak menutup kemungkin ibadah yang lain juga sama.
Tuhan itu Akbar
Lantas, bagaimana cara memahami sekaligus mempraktekkan rumus kedua; 1+1, 2+2, 3+3 dan seterusnya sama dengan TIDAK TERBATAS? Apakah rumus ini benar, logic, dan ilmiah. Jawabnya why not!. Rumus kedua sangat ilmiah. Bagaimana cara menerapkan atau mengoperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya secara teori sangat gampang. Iya memang gampang!. Semudah membalikkan telapak tangan. Rumus kedua dalam aplikasi kehidupan 100 persen merupakan kebalikan dari rumus pertama. Karena itu,
Mulailah dari bangun tidur untuk tidak menuntut Tuhan melalui doa-doa. Sebaliknya, justeru mulailah dengan memuji seraya bersyukur kepada-NYA. Puja-puji istilah dalam lafal (kata/kalimat) merujuk kepada Alhamdulillah. Makna Alhamdulillah (puja-puji) cakupannya begitu luas. Puja-puji (Alhamdulillah)dalam kamus pada umumnya dimaknai secara button-up, memujinya hamba kepada Tuhan. Hamba memuja-ji kepada Tuhan. Alhamdulillah yang hakiki adalah puja-puji itu milik Tuhan; prevellage dan hak prerogatif Tuhan. Sifatnya top-down, Tuhan memuji Tuhan. Tuhan pertama yang tidak tampak. Sementara Tuhan yang dipuji itu berwujud materi/jasad yang menyatu dalam setiap diri insan/manusia.
Dari start ini pelan tetapi pasti kita akan mendapati pelajaran berharga. Merubah rumus pertama menjadi rumus kedua, tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Sadar tidak sadar, jika dalam kehidupan sehari-hari kita menempatkan rumus pertama saja, posisi Tuhan tetap sebagai objek. Tuhan tidak sadar ditempatkan tidak lebih sebagai pesuruh, babu, alias pembantu rumah tangga (PRT). Tuhan kita perintah, disuruh-suruh. Pagi, siang, malam, tiada henti, yang mengalir dari mulut para hamba hanyalah kalimat-kalimat yang isinya perintah hamba kepada sang khalik. Hamba menjelma menjadi seorang bos dan Tuhan diposisikan sebagai kurir, pekerja kasar, bahkan PRT. Kalau sudah demikian, dimana letak etika, sopan-santun, unggah ungguh selama ini?
Bukankah Tuhan telah mendeklarasikan: “Jika engkau mau menghitung nikmat-KU, niscaya engkau tidak akan sanggup menghitungnya.” “Jika engkau sungguh-sungguh bersyukur atas nikmat-KU, niscaya akan AKU tambah.” Kedua potongan ayat al-Qur’an, dalam kamus kehidupan kita dicampakkan begitu rupa. Setiap kita terlena atas nama nafsu duniawi dan materi saling mengejar dan berlomba. Padahal, kedua potongan ayat di atas merupakan kode rahasia. Sebagai kode rahasia untuk memahami dan memasuki lautan nikmat yang telah Tuhan berikan maupun akan diberikan-NYA. Kedua ayat di atas tidak lain adalah maksud dari rumus 1+1, 2+2, 3+3 hasilnya bukan 2,4,6, atau berapapun angka yang dapat dihitung. Sebaliknya, hasil dari penghitungan angka-angka tidak terbatas.
Bisakah kita menjalankan shalat, puasa, zakat, haji, serta amal ibadah lainnya tanpa disertai berbagai embel-embel tuntutan kepada sang khalik?. Ibadah yang selalui disertai tuntutan pada ending-nya dipastikan akan negatif. Karena, ibadah kita penuh dengan conlict of interest. Seorang hamba akan senang, manakala menurutnya, setiap tuntutan dikabutkan oleh Tuhan. Sebaliknya, jika tuntutan merasa tidak dipenuhi, ia pasti akan kecewa. Perasaan kecewa akan menjerumuskan kepada sikap syirik (menduakan) Tuhan. Sesungguhnya, secara hakiki, tidak ada doa (tuntutan) itu ditolak atau dikabulkan.
Hakekat shalat itu tidak hanya sekedar shalat dalam bentuk gerakan yang dimulai dari takbiratul ikram dan diakhiri dengan salam. Bentuk shalat yang lebih dari itu adalah shalat dalam bentuk perbuatan. Dalam banyak ayat-ayat al-Qur’an, penyebutan kata shalat dibarengi dengan zakat; aqimu al-Shalah wa atu al-Zakah. Shalat dalam bentuk perbuatan lebih sempurna dari shalat dalam bentuk gerakan (ritual). Hakehat shalat adalah bentuk penghambaan. Penghambaan dalam istilah lain adalah pengabdian. Pengabdian seorang hamba kepada sang khalik. Sampai di sini, jika kita memahami hakekat shalat, masih beranikah kita dalam shalat disertai dengan berbagai tuntutan (doa-doa)?. Namanya saja penghambaan atau pengabdian. Logikanya, seseorang yang menghamba dan mengabdi bukan meminta, sebaliknya justeru memberi, memuji, dan berbakti.
Shalat itu merupakan proses; proses investasi seorang hamba kepada Tuhan tanpa perhitungan. Investasi panjang yang tidak pernah dihitung itu dipersembahkan kepada Tuhan. Bentuk investasi tanpa batas itu akhirnya melahirkan keikhlasan. Dari keikhlasan itu membentuk akhlaq budi pekerti. Inilah yang dimaksud dengan firman Tuhan; “Sesungguhnya (hakekat) shalat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar.” Ayat ini 100% tidak dapat dijalankan hanya melalui shalat gerakan atau ritual saja. Shalat yang dapat mencegah hamba dari perbuatan keji dan munkar hanya dapat dilalui setelah mengerjakan shalat perbuatan.
Tidak salah dalam ajaran Islam shalat disebut sebagai: “tiang agama,” “awal dari segala yang dihitung (hisab) pada akhir (kiamat) adalah shalat,” dan seterusnya. Warning makna shalat di sini, bukan sekedar shalat dalam makna gerakan, tetapi lebih kepada subtansi shalat dalam makna perbuatan. Dari shalat lah turun kepada ibadah-ibadah lain. Ibadah zakat, puasa, haji, dan seterusnya sebenarnya turunan dari ibadah shalat. Turunan di sini penekanannya lebih kepada orientasi hasil.
Bukankah inti dari zakat (termasuk inaq, sodaqah, waqaf, dan sebagainya) adalah bentuk pengabdian juga. Bentuk pengabdian seseorang yang berkelebihan harta kepada orang yang kekurangan. Menegakkan ibadah zakat sesungguhnya sama dengan menjalan sifat-sifat dari perbuatan Allah. Sifat Allah dimaksud adalah “Maha Memberi, tanpa diminta.” Karenanya, mengeluarkan zakat, infaq, sodaqah, dan sejenisnya tidak perlu dikasih embel-embel dengan berbagai tuntutan maupun permintaan. Tidak perlu juga diniati dengan membersihkan harta dari kotoran, jiwa, dan sebagainya.
Operasionalisasi rumus pertama dalam Bergama, pada inti dan subtansi bentuknya adalah penghambaan/pengabdi diri. Pengabdian diri hamba pada sang khalik. Jika seseorang dapat menempuh dan menjalani proses ini, dengan sendirinya akan keluar dari rumus 1+1: 2, 2+2:4, 3+3:6, dan seterusnya. Tanpa disadari, ia akan menjalani dan mengarungi bahtera kehidupan dengan rumus kedua. Pada rumusan kedua ini, justeru Tuhan melayani kepada hamba sebagai hukum kausalitas tanpa diminta.
Beragama di Ruang Publik
Jikalau setiap kita telah memahami kedua rumus di atas, saatnya berusaha (belajar) menerapkan rumus kedua dalam ruang publik. Ruang public artinya luas, yakni dalam kehidupan sehari-hari; hablu min al-Nas. Namun, ruang publik yang paling dekat dengan kehidupan kita sebagai insan akademis tentunya dalam kehidupan intelektual kita di institusi dimana setiap kita “ditugaskan” bahkan ditakdirkan oleh Tuhan. Salah satu institusi yang secara langsung adalah di kampus.
Implementasi dan implikasi rumus kedua menjadi sesederhana seperti diskripsi di atas. Diakui atau tidak, kita para insan akademis belum mampu menegakkan prinsip-prinsip, postulat, maupun rumusan kedua di atas. Postulat rumusan kedua sesungguhnya menjadi pintu masuk bagi berbagai pencapaian kinerja jika diawali dari prinsip pengabdian. Dari postulat ini juga akan berimplikasi bagi lahirnya gagasan, ide, pemikiran yang konstruktif. Hasil akhirnya akan diabadikan menjadi “heritage” maupun legacy bagi setiap insan akademis. Rumusan kedua, kurang lebih dapat dimaknai sebagai apa yang disebut sebagai “revolusi mental” atau “revolusi akhlaq.”
Kekurangan umum (commond false) setiap individu kita dalam cara kita berpikir dan bertindak dipandu oleh rumus pertama yang sangat positivistic. Agama yang identic dengan rumus kedua lebih ditempatkan sebagai lip servise, penyegar hiasan. Rumus kedua sesungguhnya merupakan inti beragama. Namun, rasionalis, akal, maupun hasrat (nafsu) yang lebih mendominasi mainset. Hanya sebagian kecil dari insan akademis yang benar-benar mampu menghayati seraya mengimplementasikan dalam ruang public akademis. Seseorang yang berada pada jalur ini dipastikan akan mampu melahirkan berbagai pemikiran besar yang jernih.
Inti keberagamaan ini akan indah manakala dipadu dengan berbagai pembaruan birokrasi. Birokrasi berorientasi kepada perbaikan sistem. Sementara, inti kebergamaan dengan rumusan kedua sebagai fondasi dasar sekaligus ruh spiritualitas. Sayangnya, setiap insan akademis di lingkungan kita belum sepenuhnya dapat mengimplementasi. Justeru sebaliknya, praktek integrasi antara inti keberagamaan dan pembaruan birokrasi sering kali dijumpai dalam tradisi masyarakat modern di dunia yang selama ini dicap sebagai dunia barat yang sekuler.
Integrasi antara inti keberagamaan dan birokrasi modern akan sangat membantu kampus ini menjadi kampus besar. Entry point dimulai dari kesadaran kita. Konsekwensi logis dari integrasi ini akan melahirkan pemikiran sekaligus tindakan setiap orang yang memiliki beban dan tanggungjawab tidak lagi melihat kepada siapa. Struktur hirarkis dalam birokrasi kampus sekalipun akan berjalan secara alamiah. Saya bekerja dalam unit kerja karena memang saya harus bekerja. Pekerjaan yang kita jalani dalam inti keberagamaan semata karena bentuk pengabdian atau penghambaan. Pengabdian kepada sang khalik. Mentauhidkan setiap pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kepada sang khalik dilakukan secara berjenjang. Birokrasi yang hirarkis ini akan melahirkan sistem ketertundukan yang berujung kepada sang khalik.
Budaya kerja seperti alur di atas akan melahirkan konsep kesetaraan. Semua bekerja atas inti keberagamaan dengan rumus kedua. Filosofinya adalah saya bekerja karena ingin mengabdi. Saya bekerja bukan karena hitung-tungan matamatis. Saya bekerja bukan karena ingin dipuji, reward, atau takut punishment. Konsep pengabdian tidak diukur itu semua. Mengabdi adalah mengabdi. Kosongkan logika matematis. Biarlah Tuhan yang menggunakan kalkulator matematika itu terhadap kita. Kalkulator Tuhan lebih jeli dan teliti dibanding kalkulator kita.
Penulis
Guru Besar Ilmu Tasawuf
Wakil Dekan III, Fak. Psikologi & Kesehatan