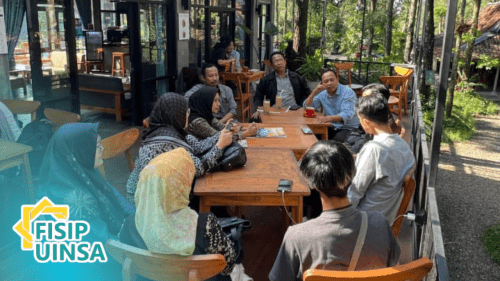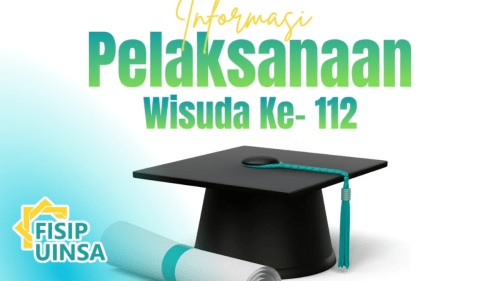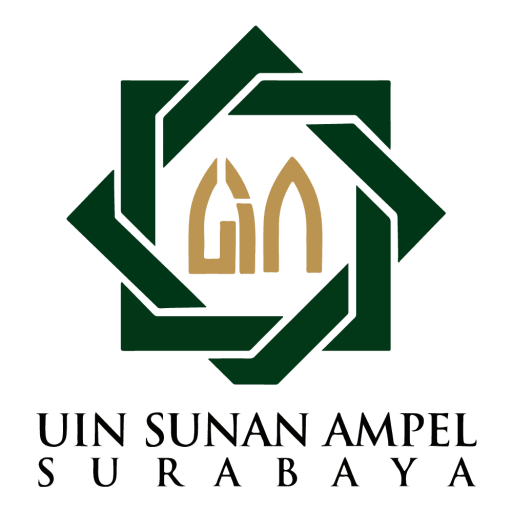Oleh: Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara FSH UIN Sunan Ampel Surabaya
Sekretaris Komisi Etik Senat UINSA Surabaya
Banyak yang berpendapat, bahwa Pendidikan Nasional kita telah kehilangan jati diri, Pendidikan Nasional kita telah kehilangan ruhnya, Pendidikan Nasional kita telah keluar dan tercabut dari akar budaya bangsa. Barangkali kali pendapat tersebut tidaklah salah, tetapi juga tidak semuanya benar. Memang ada yang terlupakan dari makna pendidikan itu sendiri, bahwa pendidikan tidaklah sekedar mencerdaskan dan memintarkan (knowledge) serta membekali keterampian (skill), tetapi jauh dari itu juga menanamkan jiwa (hati nurani), sikap (attitude), dan perilaku (behaviour) beradab, santun, ramah, dan toleran serta welas asih. Dengan bahasa yang lebih filsafatinya, bahwa tujuan utama (esensial) pendidikan adalah memanusiakan manusia itu sendiri.
Fenomena kekerasan dalam lembaga pendidikan formal maupun non formal yang selama ini terjadi cukup menjadi indikasi tentang tergerusnya akan nilai-nilai kazanah kearifan budaya lokal dalam pendidikan. Kekerasan pada Lembaga Pendidikan tidak hanya terjadi antara peserta didik senior dengan yunior, tetapi juga terjadi oleh guru (ustadz) kepada peserta didiknya. Kekerasan fisik, bullying, dan juga kekerasan verbal menjadi berita-berita viral di media masa konvensional, elektronik, maupun digital. Guru dan lembaga Pendidikan yang seharusnya mampu memberikan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan serta kehangatan peserta didik, tetapi malah menjadi momok menakutkan di mata mereka. Belum lagi kekerasan seksual, seperti pelecehan dan pemerkosaan terhadap peserta didik putri – baik antara sesama siswa maupun guru terhadap siswia Mungkin itu bisa menjadi salah satu indikator kegagalan Pendidikan Nasional kita. Lembaga Pendidikan sebagai wiyata mandala yang seharusnya mampu memberikan perlindungan, kemanan, dan kenyamanan bagi generasi muda untuk meraih cita-cita tinggi – tetapi malah menjadi sarang asusila dan asosial. Lalu apa yang salah dari Pendidikan kita?
Memang tidaklah elok, jika kita harus saling menunjuk dan menyalahkan karena pada dasarnya kita terlibat dalam lingkaran dalam membangun jatidiri pendidikan bangsa. Semua komponen bangsa harus turut andil dan mengambil posisi dalam membangun pendidikan yang membebaskan. Para pemimpin penerus yang diberikan amanah harus mampu menutup celah borok denga napa yang seharusnya menjadi bagiannya, dan bukan sebaliknya semakin menambah lebarnya celah (borok) dengan mencari kambing bitam siapa yang salah. Kita semua salah karena belum mampu membangun jati diri Pendidikan bangsa yang sesungguhntya. Para arif pernah berkata, jika kita menggunakan satu jari telunjuk untuk menunjuk kesalahan seseorang – pada dasarnya empat jari yang lain menunjuk pada diri kita sendiri. Seolah-olah empat jaribertanya (pada diri kita), emangnya kamu yang paling benar, emangnya kamu yang paling suci.
Kisah anekdot berikut mungkin dapat kita jadikan renungan: Ada seorang mahasiswa yang begitu nakalnya nggak ketulungan, lalu ia dipanggil oleh seorang dosen yang sudah tidak kuat menahan amarah karena perbuatan mahasiswa tersebut. Kemudian si dosen bertanya, siapa guru SMA/MA mu dulu emang nggak bisa didik kamu. Guru SMA/MA si aanak tersebut juga bertanya siapa guru SMP/MTs dulu emang nggak bisa didik kamu, Begitupun guru SMP si anak, siapa guru SD/MI mu dulu emang nggak bisa didik kamu. Pertanyaan yang sama dilakukan oleh guru SD/MI kepada guru TK/RA nya dulu. Lalu bagaimana dengan Guru TK/MI, ternyata mereka juga tidak mau dijadikan kambing hitam atas kenakalan si anak. Maka Guru TK/RA pun bertanaya kepada si anak, siapa sih orang tuamu – salah kali dalam berdoa ketika kamu masih di kandungan, atau bahkan tidak membaca basmalah ketika membuat kamu.
Mikul Duwur, Mendhem Jero
Mengangkat derajat leluhur, begitu kira-kira terjemahan dari sub judul tersbut. Artinya apa, generasi berikutnya haruslah menghargai kerja (karya) dari pendahulunya. Bukan, meremehkan apalagi mencemooh seolah-olah kerja (karya) kita yang paling bagus. Tidaklah demikian, sebenarnya. Itulah karakter sesungguhnya bangsa kita yang merupakan kearifan budaya lokal.
Barangkali Great Wall (Tembok Raksasa Cina), tidak akan terbangun jika para generasi (dinasti) berikutnya tidak menghargai karya generasi sebelumnya. Mengapa? Karena dinasti berikutnya akan membangun pondasi, dan kembali membangun pondasi tembok dan tidak meneruksan dari apa yang telah dibangun diansti sebelumnya. Itu pula yang menjadi gambaran desains pendidkkan nasional kita. Setiap Menteri Pendidikan akan membangun pondasi baru, dan pondasi baru Kurikulum dan tidak pernah melanjutkan desains kurikulum yang telah dibangun oleh Mentyeri sebelumnya. Alhasil, hingga saat ini belum terbangun Jati Diri Kurikulum Pendidikan Nasional – yang artinya juga BELUM TERBANGUN JATI DIRI PENDIDIKAN NASIONAL BANGSA.
Secara keseluruhan, Tembok Besar China dibangun dalam rentang waktu hampir 2.000 tahun dan melibatkan ratusan ribu pekerja dari banyak generasi dan dinasti. Yaitu mulai dari Dinasti Qin (abad 3 SM) hingga Dinasti Ming (abad 17 M). Tetapi catatan penting dari sejarah Pembangunan tembok raksasa Cina adalah: Pertama, memiliki tujuan yang sama yairtu melindungi negara Cina dari serangan bangsa lain; Kedua, dinasti selanjutnya meneruskan dari apa yang telah dibangun dinasti sebelumnya. Ketiga, mereka merasa saling memiliki (long of belonging), sehingga memiliki jiwa untuk menjaga dan membangunnya.
Melansir History, pembangunan Tembok Besar China digagas oleh Kaisar Qin Shi Huang, kaisar pertama dari Dinasti Qin yang berhasil menyatukan China, pada abad ke-3 SM. Sekitar tahun 220 SM, Kaisar Qin Shi Huang memerintahkan benteng-benteng lama dihancurkan dan sejumlah tembok yang ada di sepanjang perbatasan utara digabungkan menjadi satu, sehingga membentuk benteng yang membentang sekitar 500 meter. Tujuan pembangunan tembok tersebut adalah untuk melindungi wilayah China dari serangan bangsa barbar dari utara. Proyek ini awalnya dipimpin oleh Jenderal Meng Tian yang terkenal. Ia mengerahkan banyak tentara, narapidana, dan rakyat jelata sebagai pekerja.
Pada tahun 220, menyusul jatuhnya Dinasti Han, serangkaian suku perbatasan menguasai wilayah China utara. Dinasti Wei Utara, yang paling kuat di antara mereka, memperbaiki dan memperluas tembok untuk melindungi diri dari serangan suku lain. Sejak itu, Tembok Besar terus dibangun oleh dinasti-dinasti yang berkuasa di wilayah tersebut secara bergantian. Namun, runtuhnya Dinasti Sui pada tahun 618 dan munculnya Dinasti Tang membuat Tembok Besar China sempat kehilangan peran strategisnya sebagai benteng, karena kekuasaannya melampaui daerah-daerah yang dilindungi tembok.
Selanjutnya setelah memindahkan ibu kotanya ke Beijing pada 1421, Dinasti Ming mulai memperluas pembangunan tembok pada tahun 1474 hingga abad ke-17. Dan kita sekarang dapat melihat maha karya yang masuk dalam keajabian dunia tersebut.
Melu Rasa Handarbeni, Hangrasa Wani
Ikut merasa memiliki (sin of belonging) dapat menjadi landasan pijak dalam membangun komunitas dan atau kelembagaan, termasuk dalam membangun jati diri Pendidikan Nasional. Filosofi Jawa ini terasa amat agung dalam makna. Bagaimana tidak? Umunya dalam Masyarakat, suatu komunitas (kelompok) dan/atau lembaga (institusi) seolah-olah hanya milik siapa yang saat itu memimpin. Dan celakanya lagi, pemimpin sendiri merasa menjadi pemilik penuh dari itu.
Jika jiwa ‘milik’, yang dalam filosofi Jawa dikatakan ‘milik barang kang melok, mundhak kedulu muluk” (terhadap sesuatu yang megah/mewah manusia memiliki kecenderungan itu memilikinya secara pribadi). Mungkin ini juga semacam fitrah manusia. Dalam kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, bagaimana mereka dapat tergoda oleh Iblis karena ditipu akan diebrikan rahasia langit untuk tetap hidup di Surga dengan cara memakan “buah Kuldi” yang sebenarnya itu adalah larangan Allah (kisah ini dibadikan dalam al Qur’an Surat al-Baqarah dan al-A’raf). Adam dan hawa dengan sifat manusiawinya ‘serakah’, belum cukup diberikan kemewahan di Surga – tergoda ingin memiliki dan ambisi untuk tetap kekal di Surga dan “memilikinya secara pribadi”.
Konsep tersebut tentunya berbeda dengan “melu rasa handarbeni, hangrasa wani”, karena ini adalah rasa hati bukan wujud kehendak memiliki dalam makna pribadi, tetapi bersama-sama sebagai suatu komunitas untuk memajukan, dan membangun Bersama menuju sesuatu yang baik. Tidak egosis, bahwa pencapaian tersebut karena dan hanya karena dirinya – tetapi pencapaian tersebut didasarkan atas kerja kolektif, kolegial, dan kolaboratif. Sekecil apapun kontribusi seseorang tetap itu sebagai bagian dari suatu keberhasilan. Tentu kita juga ingat kisah-legenda pendirian Masjid Demak Bintoro di masa para wali. Soko guru atau cagak (tiang/pilar penyangga masjid) yang berjumlah 9 (Sembilan) – diceritakan 8 (delapan) sudah siap, tinggal 1 (satu) satu pilar, dan itu tugas kewajiban Sunan Kalijaga. Semua para wali sudah gelisah karena tepat hari Jum’at Masjid Demak Bintara harus berdiri, tetapi kekurangan satu tiang penyangga dapat menjadi ketidaksempurnaan. Dengan tenangnya, Sunan Kalijaga mengumpulkan sisa-sisa kayu jati yang digergaji atau tatah (dalam Bahasa Jawa disebut tatal), kemudian dirakit dan atas ijin Allah rakitan tatal tersebut menjadi tiang penyangga yang ke-9.
Pendidikan Nasional kita seharusnya dibangun atas dasar kebersamaan, konsep-konsep para pendahulu yang baik harus tetap pertahankan dan bukannya dinafikan, untuk selanjutnya para pengambil kebikan penerusnya merumuskan yang belum terlaksana dari konsep dan program yang teklah dijalankan. Jadi bukannya merobohkan bangunan, tetapi semakin mengokohkan bangunan dengan sesuatu yang lebih baik (al-muhafadhotu ‘ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah). Ingat, filsafat Matematika: ketika kita diberikan ruas garis kemudian disuruh bagaimana memperpendek ruas garis tersebut. Maka kita tidak harus menghapus panjang ruang garis tersebut sehingga menjadi pendek, tetapi kita membuat ruas garis baru yang lebih panjang dari ruas garis pertama. Artinya, para pemimpin/generasi baru jangan melupakan atau menafikan (menyalahkan) apa yang telah ditorehkan oleh pemimpin/generasi pendahulu, meski barangkali itu dianggap salah (kurang baik/kurang berhasil) – tapi berbuatlah yang lebih baik lagi sehingga dengan sendirinya Anda akan dinilai berhasil. Semoga di hari Pendidikan Nasional 2025 ini, Allah menuntun kita kembali lagi ke jalan yang benar (Sirotol Mustaqim) dalam membangun Pendidikan Bangsa yang dimulai dari kita sendiri. Aamiin.