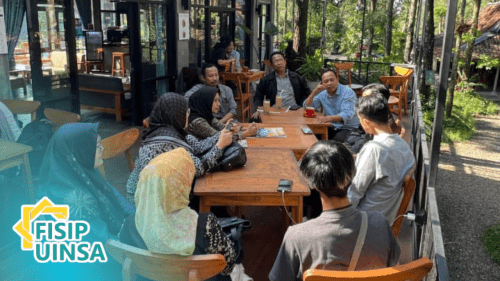Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
“Silakan, butuh penceramah seperti apa? Nanti saya siapkan. Sesuai permintaan.” Demikian kataku merespon penjelasan Ustadz Syaikhoni, asisten Mr. Abdul Salam Noh Se Ik, pejabat Korea Selatan yang datang untuk kedua kalinya ke UINSA Surabaya, Senen (12 Agustus 2024). “Di Surabaya ini, penceramah yang berlatar belakang akademisi sangat laris manis,” ujarku menjelaskan lebih lanjut fenomena akademisi UINSA yang punya kesibukan tambahan sebagai khatib di masjid-masjid. Begini lanjutku: “Hingga suatu waktu saat khatib terjadwal di masjid kampus harus absen, kami sangat kesulitan mencari pengganti. Sebab, hampir semua akademisi UINSA punya jadwal khutbah di masjid luar kampus. Sepanjang tahun. Apakah di masjid perkampungan ataukah perkantoran.”
“Nah ini yang kami cari. Sebab, sebelumnya kami sangat kesulitan saat mendatangkan ustadz dari Indonesia yang tidak punya gelar kesarjanaan. Saat membantu ngurusin visa, selalu ditanya jenjang pendidikan.” Begitu respon Ustadz Syaikhoni terhadap penjelasanku sebelumnya mengenai fenomena ustadz akademisi di Surabaya. Mendengar pernyataan Ustadz Syaikhoni yang demikian, aku pun langsung menyahut: “Ditanya soal jenjang pendidikan? Maksudnya gimana, Ustadz?” Aku merasa perlu tanya soal ini. Sebab, terasa aneh saja bagiku saat penceramah agama ditanyakan jenjang pendidikan formalnya. Apalagi, di Indonesia, sumber produksi orang-orang hebat dalam keilmuan agama tak hanya lembaga pendidikan formal, melainkan juga nonformal. Pesantren adalah contoh utamanya. Bahkan dalam banyak kasus, lulusan pesantren jauh lebih hebat.
Petugas imigrasi Korea Selatan, ternyata, kerap bertanya soal jenjang pendidikan penceramah yang didatangkan ke negeri itu. “Masa iya, warga di Korea Selatan diberi materi ceramah oleh orang yang lulus hanya jenjang pendidikan menengah?” jelas Ustadz Syaikhoni menirukan argumen yang sering disampaikan petugas imigrasi Korea Selatan kepadanya saat dia membantu pengurusan visa para ustadz untuk datang ke negeri itu. Ditanya begitu, dia sering merasa kesulitan untuk menjelaskan perihal jenjang pendidikan para justadz yang nonakademisi itu. Padahal, justeru pertanyaan itu yang hampir bisa dipastikan sering keluar dari pemegang otoritas imigrasi Korea Selatan.
“Jangankan soal itu, soal infaq dan sedekah saja mereka terheran,” sergah Ustadz Syaikhoni untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana ketidakmengertian muncul pada orang Korea Selatan saat mengetahui bahwa orang-orang Muslim Indonesia di Korea Selatan tak segan-segan untuk bersedekah lebih atas rezeki yang mereka terima untuk membantu sesama. “Gila! Gajimu sepuluh juta, tapi engkau dermakan 1 juta? Mana bisa seperti itu?” begitu contoh ungkapan keheranan warga Korea Selatan atas fenomena donasi sosial oleh warga Muslim Indonesia di Korea Selatan. Karena bagi mereka, sedekah atau donasi sosial baru bisa dilakukan saat gaji bulanan sudah di atas standar kebutuhan layak. Dan, angka sepuluh juta belum dianggap standar layak untuk hidup bermakna di Korea Selatan.
Dan, keheranan itu menjadi bagian dari ketidakmengertian yang muncul atas standar yang berbeda dalam hidup. Standar yang berbeda ini tak bisa dipisahkan dari pengalaman riil dari tata kelola kehidupan publik di negeri yang berbeda itu. Dan harus diakui, tak mudah untuk mempertemukan perbedaan itu. Termasuk dalam soal penyediaan penceramah agama dari luar Korea Selatan untuk masuk ke negeri itu dan memberikan pengajaran ilmu agama Islam kepada warga yang tinggal di Korea Selatan. Karena itu, keberadaan penceramah-akademisi dalam pengalaman di Surabaya segera ditangkap sebagai sebuah solusi atas perbedaan cara pandang melihat kecakapan keilmuan agama Islam di atas.
Maka, mendengar banyaknya akademisi UINSA Surabaya yang menunaikan tugas tambahan sebagai penceramah agama, Ustadz Syaikhoni pun berharap bisa mendatangkan panceramah-akademisi kampus ini ke Korea Selatan pada Ramadan mendatang. Bersama Mr. Abdul Salam, dia akhirnya memintaku untuk mematangkan kerjasama pengiriman ustadz-akademisi UINSA Surabaya di atas untuk menunaikan tugas sebagai penceramah agama di Korea Selatan untuk Ramadan mendatang. Kesan singkatku, mereka berdua melihat potensi kesamaan antara latar belakang pendidikan ustadz-akademisi UINSA Surabaya dan kebutuhan riil jemaah seperti yang direpresentasikan oleh pemegang otoritas imigrasi Korea Selatan di atas.
Kedatangan Ustadz Syaikhoni dan Mr Abdul Salam ke UINSA Surabaya di atas sejatinya untuk mematangkan kerjasama penguatan ekosistem industri halal di Korea Selatan dan Indonesia. Mereka berdua sudah dua kali datang ke kampus ini. Sebab, kerjasama itu dipandang sangat penting di tengah meroketnya konsumsi produk halal di Korea Selatan. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar juga mengalami tren meningkat yang sama. Bahkan, tidak hanya pada aras konsumsi halal semata, melainkan juga produksi halal. Baik produksi maupun konsumsi, keduanya memiliki kecenderungan meningkat cukup signifikan di Indonesia dalam perkembangan terakhir.

UINSA Surabaya sebagai kampus yang memberi atensi besar terhadap industri halal beserta ekosistemnya menjadi titik destinasi kerjasama penting itu. Karena itu, pembahasan mengenai poin-poin kerjasama dimatangkan secara serius. Kunjungan mereka berdua untuk kedua kalinya ke UINSA Surabaya di atas menunjukkan tingkat keseriusan mereka untuk menjalin kerjasama strategis di atas. Tentu, inisiatif kerjasama itu sudah berada pada arah yang benar. Tapi, implementasinya membutuhkan kerja ekstra agar perwujudannyaa dalam bentuk aksi konkret di lapangan bisa dilakukan dengan baik pula.
Pembicaraanku dengan Ustadz Syaikhoni dalam dialog yang kukutip di awal tulisan di atas adalah selingan saja di antara pembahasan serius mengenai kerjasama pengembangan industri halal beserta eksosistemnya di atas. Dibahas di sela-sela pembicaraan utama mengenai pendalaman kerjasama pengembangan industri halal beserta eksosistemnya dimaksud. Tapi, tetap saja aku tertarik untuk mengulasnya lebih jauh. Justeru di balik masalah industri halal dan ceramah itu, ada irisan isu yang sangat menarik untuk dibahas lebih jauh. Aku dapat menangkap adanya isu publik yang sangat mahal harganya untuk sekadar dilewatkan begitu saja. Karena itu, pembahasan mengenainya harus kulakukan.
Isu menarik yang mengemuka di balik materi pembicaraan soal industri halal dan ceramah namun penting dibahas lebih jauh di atas adalah tentang ukuran profesionalisme yang tak setara. Bagi warga masyarakat Indonesia, profesionalisme dalam bidang keilmuan agama tak bisa diukur hanya dari jenjeng pendidikan formal. Sebab, di Indonesia, sistem pendidikan nasionalnya mengakui jalur formal dan nonformal. Penguatan jalur formal tak mengabaikan pentingnya jalur nonformal. Karena itulah, pesantren sebagai lembaga pendidikan nonformal tetap dianggap penting bagi produksi keilmuan agama Islam.
Berbeda dengan yang terjadi di Korea Selatan. Mereka tak mengenal konsep jalur nonformal pendidikan. Di negeri itu, jenjang pendidikan ya satu: formal. Maka, pengetahuan dan kecakapan seseorang diukur dari jenjang pendidikan formal yang diikuti dan diselesaikannya. Inilah alasan yang menjelaskan mengapa pemegang otoritas imigrasi Korea Selatan selalu menanyakan jenjang pendidikan penceramah Indonesia yang didatangkan ke Korea Selatan. Tak gampang untuk mengubah dan meyakinkan mereka mengenai kapasitas, kecakapan dan kapabilitas para penceramah nonakademisi dari Indonesia. Karena, dalam pengalaman sosial dan administrasi birokrasi mereka, terbaca dengan jelas bahwa kapasitas, kecakapakan dan kapabilitas dimaksud diukur dengan sangat kuat dari jenjang pendidikan yang diselesaikannya.
Nah, apa pelajaran mengenai profesionalisme yang bisa ditarik dari dua pengalaman sosial dan administrasi birokrasi yang berbeda antara dua negara di atas? Ada dua pelajaran penting yang bisa diambil. Pertama, profesionalisme itu harus mengikuti dan sekaligus menjawab kebutuhan pengguna (user). Itu prinsip yang harus menjadi ruh kerja institusi. Keberadaannya sangat dibutuhkan lebih-lebih saat harus berhubungan dengan urusan jalinan kerjasama lintas institusi. Apalagi saat kerjasama itu dalam kepentingan seperti ini: yang satu sebagai penyedia layanan dan lainnya sebagai pengguna. Karena itu, semua layanan harus diukur dari, dan disandarkan pada, kebutuhan pengguna itu.
Mengikuti dan sekaligus menjawab kebutuhan pengguna adalah solusi efektif, lebih- lebih saat ukuran profesionalisme tak setara. Sebagai contoh, saat masyarakat membutuhkan penceraham agama yang cakap dengan dibuktikan oleh jenjang pendidikan yang tinggi, maka hadirnya penceramah-akademisi akan dipandang sebagai jawaban atas kebutuhan mereka. “Sebab, kita pernah kecewa bekerjasama dengan sebuah ormas keagamaaan di Indonesia dalam pengiriman ustadz ke Korea Selatan. Isi ceramahnya tak sesuai dengan kebutuhan jemaah lokal Korea Selatan. Sebab, rata-rata yang dikirim itu tak memiliki jenjang pendidikan tinggi seperti banyak jemaah di Korea Selatan. Atau tidak punya pengalaman hidup di luar negeri,” jawab Ustadz Syaikhoni.
Penjelasan Ustadz Syaikhoni di atas mengirimkan pesan sederhana. Ceramah itu bagian dari bentuk komunikasi publik. Efektivitasnya bisa diukur dari kedekatan isi yang disampaikan dengan kebutuhan riil jemaah sebagai penggunanya. Lebih-lebih saat ceramah agama dipandang sebagai bentuk layanan kepada pengguna yang bernama jemaah, maka konsep kedekatan dimaksud tak bisa ditawar-tawar. Karena itu, untuk kepentingan jaminan profesionalisme, ceramah dan isinya tak boleh jauh-jauh dari kebutuhan jemaah sebagai penggunanya. Makin berjarak, makin tak akan bisa memberikan kepuasan layanan kepada jemaah. Itu karena kebutuhan mereka tak disapa atau dipenuhi dengan baik.
Analisis kebutuhan pengguna, karena itu, menjadi sebuah keharusan bagi jaminan profesionalisme itu. Sebab, beda jemaah, akan beda pula kebutuhan mereka atas isi ceramah. Beda latar belakang jemaah beserta konteksnya juga akan berpengaruh pada preferensi mereka terhadap apa yang akan mereka konsumsi. Dalam perspektif produksi-konsumsi gagasan, produksi gagasan bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Tapi, apakah gagasan itu dikonsumsi oleh pengguna atau tidak sangat bergantung pada kedekatan gagasan yang diproduksi itu dengan kepentingan riil pengguna. Karena itu, produksi gagasan harus mempertimbangkan kepentingan dan atau kebutuhan pengguna.
Begitu pula yang terjadi dengan jemaah pengguna ceramah di masyarakat Muslim yang tinggal di Korea Selatan. Walaupun mayoritas mereka berasal dari Indonesia sekalipun, kebutuhan mereka untuk bisa bertahan hidup di Korea Selatan tentu tak sama dengan kebutuhan yang sama saat mereka tinggal di Indonesia. Atau dengan rekan dan keluarganya di Indonesia. Nah, kecakapan untuk membaca kebutuhan lokal ini di antaranya ditentukan oleh kesamaan jenjang pendidikan dan atau pengalaman hidup antara jemaah dan penceramah. Dalam koteks inilah, bisa dimengerti pernyataan Ustadz Syaikhoni yang mengungkapkan hasil kekecewaannya atas penunaian tugas ceramah oleh penceramah yang jejang pendidikan dan atau pengalaman hidupnya tak setara dengan jemaah lokal di negeri Korea Selatan sebagai pengguna gagasannya.
Kalau dalam teori pasar konsumen (consumer market), ada klausul high price equals high quality (lihat Frederick F. Wherry, “The Play of Authenticity in Thai Handicraft Markets,” dalam Daniel Thomas Cook [ed.], Lived Experiences of Public Consumption, 2008:15), maka prinsip yang sama juga bisa diberlakukan pada proses produksi dan konsumsi gagasan pada ceramah agama. Harga mahal setara dengan kualitas tinggi. Jenjang pendidikan formal yang tinggi dan atau pengalaman hidup di luar negeri itu seakan menjadi jaminan atas “harga yang mahal” dalam dunia ceramah. Itu karena, jenjang pendidikan formal yang tinggi dan atau pengalaman hidup di luar negeri itu dianggap setara dengan kualitas tinggi dalam kegiatan ceramah agama.
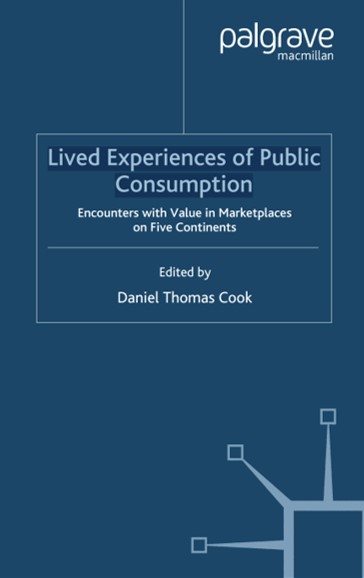
Kedua, benchmarking (atau mengambil patokan/tolok ukur) penting untuk dilakukan oleh penyedia layanan apapun dan dalam jenis apapun pula. Melalui praktik benchmarking itu, penyedia layanan bisa mengukur kinerja internalnya dengan menjadikan institusi lainnya bersama standar kinerjanya sebagai patokan atau tolok ukur. Dengan begitu, hasil kerja internal institusinya bisa segera diukur melalui pembandingan dengan hasil kerja yang menjadi standar kinerja institusi lainnya. Cara kerja seperti ini cenderung efektif untuk kepentingan percepatan pencapaian kinerja internal, dan sekaligus untuk pemenuhan ekspektasi pasar pengguna. Termasuk saat institusi lain dalam konteks benchmarking itu bertindak sebagai calon pengguna layanan.
Benchmarking adalah solusi saat ukuran profesionalisme tak setara. Bentuknya adalah kerja pengukuran kualitas sesuatu dengan membandingkannya dengan lainnya dari standar yang diterima atau diakui (accepted standard). Frase “standar yang diterima” atau “standar yang diakui” ini lazimnya merupakan ukuran yang dikehendaki oleh pihak lain yang dijadikan sebagai patokan atau tolok ukur. Apalagi saat pihak lain itu sekaligus juga bertindak sebagai pengguna layanan, maka standar yang dijadikan patokan atau tolok ukur itu adalah yang diharapkan, diterima, dan diakui oleh pihak lain dimaksud.
Untuk kepentingan itu, maka siapapun dan dalam kepentingan apapun yang ingin menjalin kerjasama untuk peningkatan kinerja institusinya penting untuk belajar dari institusi yang dituju sebagai tolok ukur dan patokan standar. Dengan begitu, akan segera bisa dicapai minimalnya titik temu, dan maksimalnya titik sepakat, atas apa yang ingin dikerjasamakan. Dan justeru pada titik inilah, kesuksesan kerjasama itu dimulai. Sederhana sekali alasannya. Ekspektasi bisa dihamparkan sejak dari awal untuk kemudian dipenuhi dengan baik. Akhirnya, prinsip “standar yang diterima” atau “standar yang diakui” dari kerja benchmarking bisa disadari sejak dari awal sekali untuk kemudian dicapai dan dipenuhi dengan maksimal.
Kasus yang dibahas dalam tulisan ini memang menyangkut layanan ceramah agama yang relevan dengan standar kebutuhan penggunanya. Tapi, substansinya sejatinya juga bisa ditarik untuk konteks lainnya. Termasuk layanan pendidikan tinggi. Bahwa perguruan tinggi tak boleh jauh-jauh dari kebutuhan penggunanya. Juga, bahwa perguruan tinggi tak boleh jauh-jauh dengan standar mutu yang dikehendaki oleh institusi di luarnya saat dibutuhkan kerjasama antara keduanya untuk kepentingan dan dalam kebutuhan bidang tertentu. Karena itu, kecakapan untuk mengikuti dan sekaligus menjawab kebutuhan pengguna pada satu sisi serta juga melakukan benchmarking dengan standar yang diterima-diakui oleh pengguna akan menentukan suksesnya jalan cerita kerjasama lintas institusi yang dirindukan.