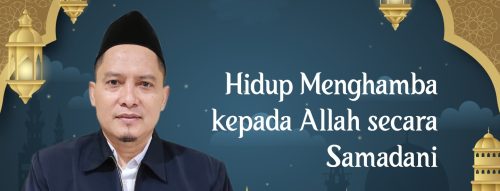Ahad, 27 April 2024 kemarin, melalui pengajian ba’da Shubuh, penulis berkesempatan silaturahim dengan jamaah salah satu masjid di Sepanjang, Sidoarjo. Mengingat masih dalam suasana Bulan Syawwal, penulis mengawali kajian bertajuk “Hidup Menghamba kepada Allah secara Samadani” itu dengan muraja’ah tentang puasa ditinjau dari kacamata Filsafat. Beranjak dari pemaknaan harfiah tentang puasa (الصيام) yang berarti pengendalian diri (الامساك), maka secara ringkas, keberadaan atau ketiadaan (ONTOLOGI) PUASA itu terletak pada eksistensi pengendalian diri pada diri seseorang. Demikian pula, hakikat (METAFISIKA) PUASA pada esensi-nya terkandung dalam kemampuan seseorang mengendalikan dirinya. Artinya, ketika seseorang tidak mampu mengendalikan diri dari sesuatu yang seharusnya dia kendalikan sesuai nilai tujuannya, maka di saat yang sama, sesungguhnya tidak ada puasa pada diri orang tersebut. Atau dengan kata lain, di detik itu, sejatinya dia sedang tidak berpuasa. Lantas bagaimana cara atau metodologi yang bisa ditempuh seseorang dalam berpuasa?
Menggabungkan pemahaman atas penjelasan dari dua kitab tafsir tentang ayat 183 surah al-Baqarah, yaitu Ruh al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an karya Isma’il Haqqi (w. 1127 H) dan al-Ta’wilat al-Najmiyyat fi al-Tafsir al-Isyari al-Sufi karya Ahmad bin ‘Umar (w. 618 H), maka EPISTEMOLOGI PUASA secara Islami bisa difahami dalam 5 (lima) tingkatan lelaku:
- Tingkat Pertama. Masani barang telu: mangan, ngombe, lan ‘nganu’ atau الامساك عن المفطرات المعهودة. Mengendalikan diri dari pembatal-pembatal keabsahan puasa secara lahiriyah, yaitu makan, minum, dan berhubungan suami-istri di waktu yang ditentukan, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.
- Tingkat Kedua. Masani barang telu: paningal, pangrungu, lan pangucap atau الامساك عن المنهيات الحسية. Mengendalikan diri dari segala bentuk kemaksiatan yang timbul dari aktivitas memandang, mendengar, dan berbicara.
- Tingkat Ketiga. Masani barang telu: cipta, rasa, lan karsa atau الامساك عن مشارب المعقولات. Mengendalikan diri segala bentuk negativitas dan bisikan jahat yang bisa mengeruhkan fikiran, perasaan, dan keinginan.
- Tingkat Keempat. Masani barang telu: riya’, sum’ah, lan kibr atau الامساك عن ملاحظة الروحانية. Mengendalikan diri untuk tidak meletakkan aktivitas penghambaan pada fondasi popularitas narsistik yang menghendaki kenikmatan ibadah pada afirmasi dan apresiasi sesama hamba: supaya didengar, dilihat, dan diakui orang lain penuh kekaguman.
- Tingkat Kelima. Masani barang telu: nyawang semat, nyawang drajat, lan nyawang kramat atau الامساك عن شهود غير الله. Mengendalikan diri dari ‘melihat’ yang selain Allah. Mengosongkan diri (nyuwung) dari segala motif dan orientasi penghambaan yang selain Allah. Apapun bentuk identitas atau tetenger yang melekatinya, apakah itu berupa asesoris fisikal (semat), status sosial (drajat), maupun kuasa publik (keramat). Mengosongkan diri dari segala yang selain Allah sehingga sepenuhnya yang ada kemudian hanyalah Dia (nyuwung supaya bisa nyawang). Seperti dikatakan Ibnu ‘Arabi (w. 638 H) dalam tafsirnya: الإمساك عن كلّ قول وفعل وحركة وسكون ليس بالحق للحق.
Ketika seseorang telah mampu laku pasa dengan kualitas penghambaan tingkat kelima, maka AKSIOLOGI PUASA-nya sudah bukan lagi terikat pada nilai-nilai duniawi maupun ukhwawi, melainkan semata nilai ketauhidan. Seseorang berpuasa bukan berhenti pada tujuan duniawi supaya sehat atau terpelihara dari godaan syahwat. Tidak pula berhenti pada tujuan ukhrawi supaya selamat dari jilatan api neraka atau menjadi bagian dari penghuni surga. Tetapi nilai kemulian yang dituju dari puasanya adalah semata keridhaan Yang Maha Disembah, Allah Ta’ala yang tiada serupa dengan makhluk-makhluk-Nya. Jadi, meski tanpa ada iming-iming pahala duniawi maupun ukhrawi, atau jikalau tidak ada surga dan neraka di kehidupan nanti, seorang hamba berpuasa karena memang itulah yang diminta oleh satu-satunya Dzat yang kepada-Nya dia sumarah seutuhnya. Secara rela maupun terpaksa, ia menghambakan diri dan menyandarkan hidup kepada-Nya (samadani). Pada titik ini, seperti diungkap oleh Imam al-Qusyairi (w. 283 H) dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat, seseorang memahami perintah صوموا وأفطروا لرؤيته bukan berpuasa karena melihat hilal bulan Ramadan atau berlebaran karena melihat hilal bulan Syawwal, melainkan karena melihat Allah. Dhamir atau kata ganti ه di nash tersebut bukan diartikan sebagai hilal, melainkan Allah, Dzat Yang Maha Cinta. Maka puasa kemudian tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dilakukan hanya ketika Ramadan tiba. Tidak pula berakhir ketika Syawwal menyapa. Puasa adalah kesadaran sekaligus kemampuan pengendalian diri seorang hamba yang terus berikhtiar sepanjang hayat untuk tetap dalam ketaatan hingga Allah memanggilnya menghadap (pasa urip).
Sepulang dari silaturahim tersebut, penulis sempat membaca status Whatsapp seorang kawan lama, tentang manfaat memaafkan bagi kesehatan. Terpantiklah sebuah lintasan pertanyaan: Apakah termasuk di dalamnya, memaafkan mantan? Jika iya, bagaimana cara mudah untuk mengetahui bahwa seseorang benar-benar telah memaafkan mantannya? Entah itu mantan teman, mantan tetangga, mantan pasangan hidup, atau mantan-mantan lainnya yang pernah meninggalkan jejak luka tak berdarah yang sangat menyakitkan? Imam Hasan al-Basri (w. 110 H), dalam muhasabah-nya, untuk mendeteksi apakah di dalam dirinya masih menari sayap-sayap kesombongan (‘ujub/kibr), beliau memakai indikator rasa linuwih yang mengerjap dalam batinnya tiap kali berjumpa dengan orang lain. Maka, setiap kali beliau keluar rumah, tiap kali bertemu dengan seseorang, jika di lubuk hatinya masih muncul perasaan ‘lebih baik’ dan lebih-lebih lainnya dari orang yang dijumpainya, maka hal itu merupakan alarm bagi beliau atas bahaya kesombongan yang dilarang oleh Tuhan. Bercermin dari cara yang ditempuh ulama besar ini, lantas, terkait memaafkan mantan, alarm atau indikator apa yang bisa digunakan? Apakah rasa lega ketika kembali mengingatnya? Rasa plong ketika berjumpa dengannya tanpa disengaja? Minimal di maqam filsafat puasa yang keberapa seseorang akan benar-benar mampu memaafkan mantan yang pernah menorehkan luka di hatinya? Belum sempat terjawabi pertanyaan itu, tulisan di bak belakang sebuah truk yang melaju di depan penulis menggoda mata untuk membaca: “Di setiap luka ada cerita.” Ilustrasinya, gambar wajah seorang perempuan. Meski tak melihat langsung, penulis yakin, sopir atau pemilik truk ini pasti seorang lelaki. “Dalam yang tersurat tampak yang tersirat bahwa dongeng mengandung filsafat,” kata Buya Hamka (w. 1981 M) dalam bukunya, Dari Perbendaharaan Lama.
_________
Ditulis oleh Dr. Nyong Eka Teguh Iman Santosa, M.Fil.I., Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Ampel Surabaya