
Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
“Asam lambung saya langsung naik
Saat kuketemu kembali di Jakarta dua bulan berikutnya (24 April 2024) di forum serupa untuk penyelenggara negara lainnya, pernyataan di atas diulang kembali. Dilontarkan lagi. Kudengar langsung! Ya, sendiri secara langsung. Bukan hasil cerita. Bahkan saat kusentil lagi kisah di Surabaya sebelumnya itu untuk memastikan apa yang sedang digundahkan, pernyataan “Asam lambung saya langsung naik
Jadi, tampak sekali, beliau pimpinan penyelenggara pelatihan penguatan integritas penyelenggara negara di atas sungguh-sungguh sedang menunjukkan keresahannya. Kaget. Terkejut. Plus gundah. Atas respon sejumlah peserta pelatihan di Surabaya itu. Kesan kuatku, beliau menangkap keganjilan yang mendalam atas kejadian itu. Kala pelatihan itu, setiap kali pemateri menyampaikan presentasi materinya, sergahan langsung muncul. Yang sering bukan dalam bentuk pertanyaan semata. Tapi kerap dalam bentuk sanggahan dan bahkan penentangan. Seakan pemateri pun tak diberikan keleluasaan untuk menyelesaikan penyampaian materi yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Apalagi, soal urutan sekuensial presentasi materi, itu tentu urusan strategi penyampaian. Bisa beda antara satu orang pemateri dan lainnya. Tapi semua itu tak jadi pertimbangan.
Penyebutan “asam lambung naik” di atas menandakan bahwa fakta-fakta yang dijumpai dari para peserta selama pelatihan itu sudah pada taraf menggelisahkan. Tak lazim. Seperti pada pelatihan-pelatihan pada umumnya. Bagaimanapun, siapapun yang bertugas sebagai pemateri adalah guru untuk para peserta kala itu. Sebaliknya, para peserta pun juga menjadi murid saat itu. Apapun pangkat dan jabatannya. Juga apapun gelar akademiknya. Maka, sudah sewajarnya jika masing-masing antara guru dan murid itu bisa menampilkan diri secara baik. Dengan memantaskan diri bahwa pemateri adalah sang guru, dan penerima materi adalah sang murid. Masing-masing penting untuk tahu diri. Apapun jabatan dan kepangkatan yang disandang di tempat kerja masing-masing.
Meskipun begitu, aku masih menyimpan cadangan rasa senang. Mengapa begitu? Karena kudapati pimpinan penyelenggara pelatihan untuk para pejabat penyelenggara negara di atas masih menyampaikan komentarnya dimaksud dengan senyum. Gelisah, iya. Terkejut, pasti. Gundah, betul. Begitu yang kutangkap. Atas kesanku pada situasi batin beliau itu kala itu. Tapi, beliau masih merespon fakta-fakta dari respon sejumlah peserta pelatihan di atas dengan santai. Itu meskipun kalimat “asam lambung naik” tak bisa menyembunyikan kegalauan, kekagetan dan keterkejutannya terhadap kenyataan sikap peserta sebagaimana bisa dinyatakannya dalam kalimat dimaksud. Hanya senyum kecil yang masih mengembang di bibirnya masih membuka ruang maaf dan pemakluman tertentu atas kejadian itu.
Kujadi ingat lagu berjudul Panggung Sandiwara. Inilah penggalan liriknya:
\Dunia ini panggung sandiwara\
\Ceritanya mudah berubah\
\Kisah Mahabrata atau tragedi dari Yunani\
\Setiap kita dapat satu peranan/
\Yang harus kita mainkan/
\Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura/
Lagu itu mudah diingat. Liriknya sangat ilustratif. Apalagi, dinyanyikan oleh kelompok musik rock beken banget. Bernama God Bless. Mereka para pekerja seni musik top. Mulai gitarisnya Ian Antono. Hingga penyanyinya Ahmad Albar. Semua tokoh beken. Hingga grup bandnya pun sangat ternama. Semua lagu yang dibawakannya selalu hits. Termasuk lagu di atas. Saking terkenalnya, lalu lagu itu dinyanyikan ulang dengan sedikit ada perubahan aransemen. Oleh penyanyi muda berbakat kala itu. Namanya Nike Ardilla. Jadilah, lagu itu lagu yang akrab di telinga segala usia.
Lirik dan isinya memang sangat dekat dengan kehidupan. Siapapun. Dan di manapun. Terasa dekat di hati. Saat luka atau bahagia. Karena itu, frase Dunia ini panggung sandiwara pada lagu di atas memiliki semangat yang mirip dengan frasa All the world’s a stage yang diutarakan oleh karakter Jaques dalam karya William Shakespeare berjudul As You Like It (lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_ini_panggung_sandiwara). Kemiripan itu terjadi karena dekatnya substansi dengan realitas sehari-hari. Oleh siapapun saja yang menjalani. Di manapun hidup itu dilalui. Dijalani dan dialami. Maka, pengalaman kemanusiaan yang menjadikan substansi dunia sebagai panggung sandiwara dialami dan dirasakan bersama oleh setiap insan.
Aku pun lalu teringat pula dengan teori Dramaturgi. Sebetulnya, teori ini mengandung substansi teori panggung. Riilnya, hidup diteoretisasi laksana teater. Relasi satu orang dengan lainnya bak drama di atas panggung. Dalam interaksi antar individu di tengah masyarakat. Masing-masing orang memainkan peran spesifiknya. Hingga sebuah perubahan pun bisa diawali dari permainan peran di panggung kehidupan nyata itu. Teori yang dikembangkan oleh Erving Goffman tahun 1959 dalam karyanya The Presentation of Self in Everyday Life ini mengidealisasikan kekuatan peranan masing-masing individu dalam mempersembahkan dirinya di ruang bersama dalam kehidupan sehari-hari. Dan karena itu pula, mudah ditemui orang main panggung.
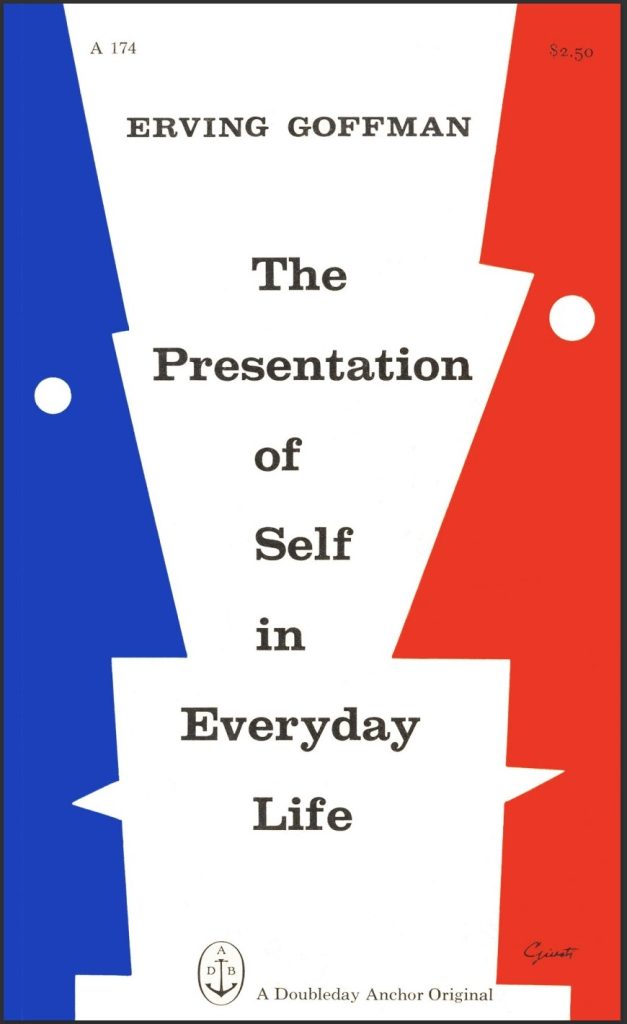
Tentu, teori panggung yang bernama dramaturgi di atas dikembangkan oleh Erving Goffman dengan berbasis pada realitas sosial tertentu. Utamanya pada masyarakat yang tinggal di Shetland Island, kepulauan di Skotlandia. Hanya, karena mengena ke semua gugus sosial di belahan manapun di dunia, maka teori tersebut dipandang dan dirasa relevan digunakan untuk melihat praktik persembahan citra diri ke gugus sosial manapun. Goffman, karena itu, membedakan panggung (stage) dan kehidupan (life). “Panggung menyajikan hal-hal yang bersifat khayalan (make-believe),” kata Goffman (1995:xi), sedangkan kehidupan “agaknya menghadirkan hal-hal yang nyata dan kadang-kadang tidak dilakukan pelatihan atasnya dengan baik (not well rehearsed).” Karena itulah, sangat wajar lalu orang bermain panggung dalam kehidupan senyatanya.
Karena itu pula, panggung penting dipahami sebagai medan untuk mencitrakan diri. Penyebabnya sederhana. Itu karena, meminjam ungkapan Goffman (1995:xi), “di panggung seorang pemain menampilkan dirinya dalam kedok karakter tertentu ke karakter yang diproyeksikan oleh pemain lain.” Seseorang berada di panggung dalam rangka untuk memainkan lakon tertentu. Orang lainnya yang juga berada di panggung itu juga memainkan lakon dan peran lainnya. Artinya, masing-masing orang yang berada di panggung, meminjam lirik lagu Panggung Sandiwara Oleh God Bless di atas, “dapat satu peranan”. Dengan begitu, masing-masing sedang memainkan peran dan lakonnya. Tak bertabrakan peran antara satu dan lainnya. Itu di panggung sandiwara.
Dalam konteks inilah, Goffman (1995:xi) memandang bahwa penonton hanya menjadi pihak ketiga (third party) terhadap interaksi antar lakon di atas. Hanya lacurnya, kata Goffman (1995:xi), saat pertunjukan panggung (the stage performance) terjadi secara nyata; satu pun audiens itu tak akan pernah berada di sana. Semua hanya diperankan semata. Tidak dialami. “Diperankan” berarti, sesuatu hanya dilakukan untuk memenuhi harapan tertentu dari lakon yang sedang dijalani. Ia tidak riil terjadi dalam kehidupan senyatanya. Itu yang membedakannya dengan konsep “dijalani”. Sebab, kata “dijalani” pasti berarti “dialami”. Tentu dalam kehidupan nyata. Bukan sekadar dilakukan untuk memenuhi harapan lakon yang diperankan.
Itulah ilustrasi yang dibuat oleh Goffman untuk menggambarkan, memahami, dan memaknai perbedaan antara panggung sandiwara dan kehidupan nyata. Maka pelajarannya untuk kita semua minimal meliputi dua poin utama. Pertama, hidup itu ada saatnya dan ada panggungnya. Saat, itu ada panggungnya. Dan panggung, itu ada saatnya. Maka, jangan bermain panggung hanya untuk menunjukkan kelebihan diri sendiri dan pada saat yang sama ingin melakukan tekanan kepada sesamanya. Baik melalui sindiran maupun cacian. Hingga pembunuhan karakter pun tak ketinggalan untuk dilakukan.
Upaya merendahkan sesama melalui praktik buruk hingga pembunuhan karakter di atas semakin tampak lacur lebih-lebih saat dilakukan pada figur sesama yang sedang berada dalam posisi yang seharusnya memang berada di atas panggung. Minimal untuk mengisi ruang panggung kala itu. Buruknya praktik itu tak bisa disembunyikan. Karena jelas menimbulkan praktik “tidak sadar posisi”. Frase ungkapan yang pernah ngetop oleh Happy Asmara. Saat ditinggal menikah oleh sang mantan, Denny Caknan. Praktik ini cenderung negatif karena pelakunya akan cenderung main panggung. Padahal itu bukan jatahnya.
Karena itu, tak perlu berebut panggung. Jika kepentingannya hanya untuk berebut kuasa jabatan. Tunggulah saatnya. Akan ada panggung yang tersedia. Tak perlu “sundul-menyundul” di atas panggung. Tak perlu saling “pukul” di atas panggung. Tak perlu baku unjuk kelebihan di atas panggung. Lalu ada di antara kita yang kehilangan nalar budi. Kehilangan akhlak. Dengan cara merendahkan sesama. Apalagi melakukan oembunuhan karakter atasnya. Hanya untuk kuasa yang diasa. Hanya untuk jabatan yang didamba.
Teori panggung ala dramaturgi Goffman penting menjadi pengingat. Goffman saja mengingatkan bahwa jika panggung dimaksudkan dalam cakupan makna sandiwara, maka bermain panggung untuk berebut kuasa jabatan hanya membuat pelakunya bak bermain drama. Tidak riil. Dan cenderung hanya melakukan representasi saja atas kenyataan ideal. Semua lalu mainnya serba pencitraan. Itu semua dilakukan karena panggung kuasa jabatan diperebutkan sedemikian rupa melalui aksi panggung pencitraan diri. Hingga nilai-nilai kebajikan dan kepatutan sosial pun diterabas habis.
Akhirnya, banyak hal akan berjalan tidak normal. Tidak alami. Dan nalar pun bisa terkebiri. Sebab, jika terjebak dengan praktik haus kuasa, normalitas bisa terancam. Kewarasan jadi tertawan. Alih-alih, orang bisa melampaui kewenangan. Minimal, menabrak standar nilai yang dipersyaratkan. Ujung-ujungnya, semua akhirnya dinegosiasikan. Untuk kepentingan sesaat yang kerap membahayakan. Akhirnya kinerja pun akan bisa jadi bulan-bulanan. Oleh aksi kuasa yang dinegosiasikan. Minimal, kinerja akan ditarik-tarik oleh kepentingan-kepentingan penanam saham politik kuasa yang menekan.
Karena itu, sebagai pelajaran yang kedua, berproseslah dari bawah. Jalani apapun tugas pekerjaan yang menjadi amanah. Jangan pilih-pilih tugas yang diberikan. Jangan ambil langkah suka atau tidak suka pada tugas jabatan yang diberikan. Lakukan dengan baik semua tugas pekerjaan. Karena setiap pekerjaan adalah anak tangga. Jika dilakukan dengan baik, maka sukses pelaksanaan pekerjaan itu berarti capaian keberhasilan untuk membangun satu anak tangga. Karena itu, jika satu anak tangga itu dilengkapi lebih jauh dengan anak tangga berikutnya, maka sesungguhnya investasi sedang ditanamkan untuk masa depan. Jika investasi sudah terjaga, terbentang pula di hadapan peluang untuk melompat ke kinerja yang lebih membanggakan.
Sampai pada titik ini, tiba-tiba kuingat sebuah film drama keluarga. Judulnya Sejuta Sayang Untuknya. Dirilis tahun 2020. Satu plot dari film itu kuingat betul. Dialognya pun ku tak pernah lupa. Digambarkan, seorang perempuan muda bernama Gina (yang diperankan oleh Syifa Hadju) meraih piala penghargaan atas prestasinya bermain film. Saat menerima piala itu di panggung, dia bercerita tentang sosok sang ayah yang menjadi inspirasi hidupnya. Sosok sang ayah yang bernama Aktor Sagala itu diperankan oleh artis film gaek, Deddy Mizwar. “Ayahku tidak pernah pilih-pilih peran. Semua dia jalani.” Begitu dengan bangganya Gina menceritakan keteguhan sikap hidup sosok ayahnya. Bahkan, dia menirukan pandangan hidup ayahnya yang dia kutip kembali seperti ini: “Tidak ada peran yang kecil, kecuali aktor yang kerdil.”
Pandangan di atas mengajarkan, betapa semua peran pasti punya makna. Karena itu, jangan pernah menurunkan makna dari sebuah peran. Apapun peran itu. Karena, apapun peran akan membentuk ekosistem kinerja. Maka, menurunkan makna sebuah peran sama dengan mengawali runtuhnya kinerja diri dan lembaga. Dan jika itu yang terjadi, maka sejatinya seseorang telah menurunkan makna dirinya di hadapan kemuliaan. Di sinilah sikap kerdil itu bermula. Karena nilai yang begitu mulia dari apapun peran yang ada di balik sebuah organisme kinerja dinihilkan begitu saja. Oleh sikap hidup yang memandang sebuah peran rendah dan lainnya tinggi nan mulia.
Karena itu, bagi sosok Deddy Mizwar yang memerankan figur Aktor Sagala dalam film di atas, saat diminta menjadi tokoh figuran, peran itu tetap diambil. Tak disia-siakan. Apalagi ditolak. Dan saat harus memainkan peran tokoh utama pada saatnya, juga diterima dan dilakoninya dengan serius. Intinya, tak ada satupun peran yang ditawarkan kepadanya ditolak. Atas alasan apapun. Termasuk suka atau tidak suka atas peran yang ditawarkan itu. Sosok Aktor Sagala yang digambarkan di film itu memang menggambarkan bagaimana sepak terjang Deddy Mizwar dalam kehidupan nyata sebagai aktor yang tanpa pilih-pilih peran hingga kemudian menjadi artis kenamaan itu.
Pendek kata, peran apapun yang diberikan kepada Deddy Mizwar selalu diambil dan dilaksanakan dengan baik. Hingga saat terhormat pun datang. Yakni saat harus memainkan peran sebagai tokoh sentral. Berbasis pengalaman yang kaya lintas peran, dia pun akhirnya tak pernah canggung saat harus berperan sebagai pemain utama. Alasannya sederhana. Karena dia aktor yang sangat berpengalaman. Selalu mengalami dari posisi bawah. Deddy Mizwar, seperti yang dilukiskan oleh tokoh Aktor Sagala di atas, lalu dalam sejarahnya menjadi aktor yang sukses lintas zaman. Karena memang dia berangkat untuk sukses dari bawah.
Maka, untuk sukses, yang penting bukan berebut panggung. Tapi menjalani proses dari titik paling awal sekalipun. Sikap hidup seperti ini penting. Sebab, menjalani proses sedari awal sekalipun akan muncul pengalaman. Dari pengalaman, akan lahir kedewasaan. Tandanya adalah kematangan dalam berpikir dan bertindak. Termasuk dalam mengambil Keputusan. Sebuah tugas pekerjaan yang harus ditunaikan oleh kepemimpinan. Berebut panggung itu pertanda prosesnya tak selesai. Bahkan mungkin kerap di-bypass. Lalu muncullah yang serba instan. Akhirnya panggung pun diperebutkan. Padahal, sekali lagi, panggung itu ada saatnya, dan saat pasti ada panggungnya.
Pengalaman menjalani proses dari bawah di atas akan membuat seseorang terampil menjalankan tugas sebagai pegawai pengikut (follower) pada titik awal karir. Saat dia sudah bisa menjadi follower yang baik, maka dia akan tahu dan memahami bagaimana menjadi leader yang baik. Mengapa begitu? Karena leader yang baik hanya lahir dari pengalaman menjadi follower yang baik. Tak akan pernah menjadi leader yang baik jika tak pernah mengalami capaian sukses menjadi follower yang baik. Maka, menghormati yang sedang berada di panggung adalah kemuliaan. Pertanda diri penuh kematangan.
















