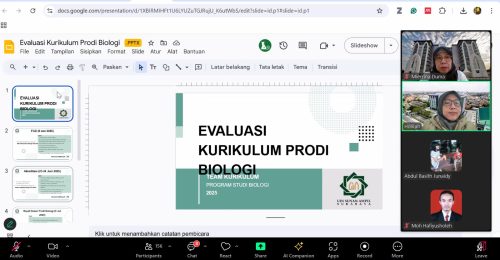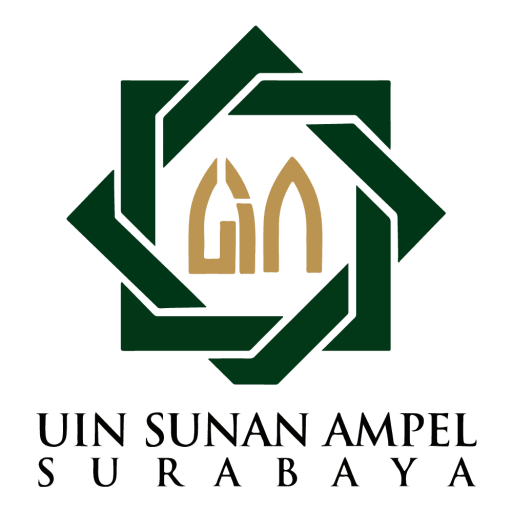Bayangkan sejarah bukan sekadar catatan masa lalu yang tertulis rapi dalam buku pelajaran. Namun, sebuah arena tarik-menarik kekuasaan. Inilah cara Michel Foucault, filsuf asal Prancis, membaca sejarah. Ia tidak percaya bahwa sejarah adalah kisah kemajuan umat manusia. Sebaliknya, sejarah menurutnya sering kali hanya menunjukkan bentuk-bentuk baru dari kontrol yang semakin rapi dan tersembunyi.
Melalui pendekatan genealogi, Foucault tidak mencari asal-usul murni sebuah peristiwa. Ia menelusuri bagaimana kekuasaan bekerja membentuk cara manusia berpikir, berbicara, bahkan merasa. Ia mempertanyakan asumsi yang kita anggap wajar: mengapa orang dengan gangguan jiwa harus dirawat di institusi tertentu? Mengapa seksualitas diatur begitu ketat? Mengapa penjara dianggap sebagai solusi keadilan? Semua itu, menurutnya, adalah hasil dari kekuasaan yang bekerja melalui institusi, bahasa, dan norma sosial.
Dalam pandangan ini, pengetahuan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Kebenaran bukan sesuatu yang objektif dan netral, tetapi dibentuk oleh siapa yang paling berkuasa menentukan narasi. Sejarah pun bukan milik mereka yang menang perang secara militer, melainkan milik mereka yang berhasil menentukan apa yang patut dikenang dan apa yang harus dilupakan.
Pandangan Foucault ini terasa sangat relevan ketika kita mendengar wacana Kementerian Kebudayaan untuk menulis ulang sejarah nasional. Sebuah langkah ambisius yang, di satu sisi, patut diapresiasi karena berupaya memperbarui dan melengkapi narasi sejarah Indonesia. Namun di sisi lain, rencana ini mengundang pertanyaan krusial: sejarah versi siapa yang akan ditulis ulang?
Selama Orde Baru, kita mengenal betapa sejarah ditata sedemikian rupa untuk melegitimasi kekuasaan. Narasi sejarah dikonstruksi untuk memusatkan peran negara dan militer, sambil mengesampingkan, bahkan menghilangkan, peran kelompok masyarakat lain. Peristiwa-peristiwa seperti pembantaian 1965, konflik agraria, atau perlawanan komunitas adat terhadap ekspansi negara nyaris tak terdengar dalam buku pelajaran.
Kini, ketika negara berencana menyusun ulang sejarah nasional, kita tidak bisa tidak bertanya: apakah sejarah akan dibuka untuk narasi-narasi alternatif? Apakah kisah perempuan, komunitas adat, kelompok minoritas, dan korban kekerasan negara akan diberi ruang? Ataukah sejarah akan kembali menjadi proyek pembakuan narasi dominan yang lebih halus dan modern?
Menulis sejarah bukan semata kerja akademik. Ia adalah kerja ideologis. Pemilihan peristiwa, tokoh, dan sudut pandang sangat dipengaruhi oleh nilai dan kepentingan tertentu. Jika proyek ini hanya menjadi upaya teknokratis semata—disusun oleh segelintir akademisi tanpa keterlibatan publik yang luas—maka risiko pengulangan pola lama sangat besar.
Kita perlu bertanya: siapa yang diberi hak untuk menyusun ulang narasi ini? Apakah para penulisnya merepresentasikan keberagaman perspektif, daerah, dan pengalaman hidup? Apakah masyarakat sipil, sejarawan kritis, pegiat budaya, dan komunitas korban turut dilibatkan dalam prosesnya?
Sebagai bangsa yang plural, sejarah Indonesia seharusnya memuat keragaman narasi. Ia tidak hanya tentang kemenangan, tetapi juga luka. Tidak hanya tentang para pahlawan besar, tetapi juga tentang mereka yang selama ini tak terdengar. Sejarah yang demokratis adalah sejarah yang memberi tempat bagi semua suara, termasuk yang tak nyaman didengar.
Foucault mengingatkan kita bahwa sejarah bukan soal mencari siapa pahlawan dan siapa pengkhianat. Tapi soal siapa yang diberi hak bicara, dan siapa yang dibungkam. Siapa yang menentukan apa yang dianggap normal, dan siapa yang menanggung akibat karena dianggap menyimpang.
Penulisan ulang sejarah nasional adalah momen penting yang menentukan arah ingatan kolektif bangsa. Ini bukan semata soal memperbaiki data atau memperindah narasi. Ini adalah pertaruhan besar: apakah kita memilih mengulang sejarah sebagai alat legitimasi kekuasaan, atau menjadikannya sebagai ruang bersama untuk mengingat, belajar, dan memperbaiki masa depan.
Dalam semangat itu, sejarah seharusnya tidak ditulis untuk mengukuhkan siapa yang paling berkuasa, tetapi untuk menghidupkan kembali suara-suara yang pernah dibungkam. Sejarah yang adil adalah sejarah yang berani jujur, bahkan jika itu membuat kita tidak nyaman.
Tentang Penulis:
Dr. Mohammad Isfironi
Dosen Antropologi Ekologi, UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: [moh.isfironi@gmail.com]
HP/WA: [085257643284]