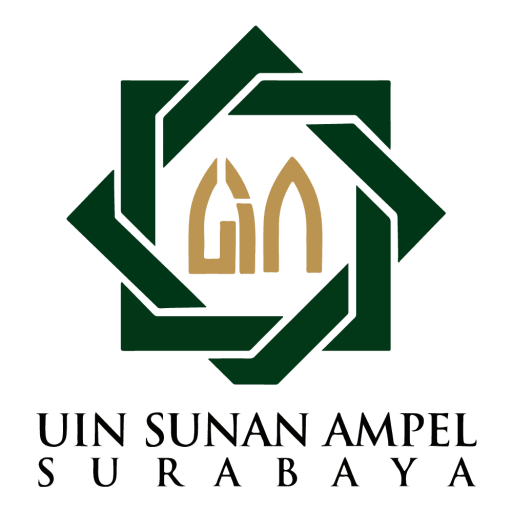Beberapa waktu (atau bulan) yang lalu, kita dihebohkan dengan adanya pagar laut. Konon, pagar yang membentang sepanjang 30 km di sepanjang pesisir Tangerang ini menghabiskan biaya dan sekaligus merugikan nelayan milyaran rupiah. Tak hanya di Tangerang, di beberapa tempat di Jawa Timur juga ditemui kasus serupa, meskipun tak semasif disana, sebutlah di Bangkalan dan Gresik. Di Sidoarjo lebih ‘sakti’ lagi, konon lautnya malah sudah terbit HGBnya (dan legal!) walaupun pada akhirnya dibatalkan oleh Pak Menteri ATR/BPN.
Salah satu hal menarik yang kemudian mengilhami lahirnya tulisan ini adalah komentar Zabur, kepala desa Tanjung, kecamatan Pademawu, Pamekasan; “Itu kan laut, ngapain masih izin.” Senin (10-2-2025) sebagaimana dikutip dari Pamekasan Channel. Lantas sebenarnya, bagaimana sih ngurusin laut itu? Ketidakpahaman mengenai aturan-aturan yang berlaku kemudian membuat seolah-olah izin tata kelola ruang laut ini menjadi rumit dan yang paling ajaib ya itu: Laut e Gusti Allah, kok!
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan beberapa aturan terkait ruang laut seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 yang salah satu amanahnya adalah menjadikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagai dasar berusaha. Aturan terkait KKPRL sendiri telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021. Singkatnya, KKPRL wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut, baik pada perairan pesisir, wilayah perairan dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap yang dilakukan terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) hari.
KKPRL sendiri, menurut penulis, merupakan sebuah itikad baik dari pemerintah untuk mengkrongkretkan prinsip Integrated Coastal Zone Management (ICZM). Sesuai namanya, ICZM sendiri berdiri atas dasar prinsip keterpaduan yang setidaknya terdiri dari beberapa unsur antara lain: unsur kelembagaan, unsur kewenangan, unsur ekosistem (darat/laut) dan unsur multi keilmuan. Gampangnya, pemerintah ingin supaya tidak ada tumpang tindih dan penyalahgunaan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan zonasi kawasan.
Terlepas dari segala teknis pengurusan KKPRL dan urgensi harmonisasi pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini peran vital civitas akademika perguruan tinggi sangat dibutuhkan, terlebih yang memiliki keilmuan terkait. Insan akademia sudah seharusnya lebih peka dan bisa lebih aplikatif keilmuannya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan riil seperti ini. Sebagai contoh, sekelompok masyarakat budidaya mengajukan ijin untuk keramba ikan di lokasi yang bersebelahan atau beririsan dengan daerah kerja pelabuhan atau daerah kepentingan pelabuhan yang ternyata masih ada zona ekosistem disana atau rencana pemasangan pipa bawah laut yang ternyata beririsan dengan jalur migrasi spesies ikan tertentu. Kepakaran dan kejernihan insan akademia (dalam hal ini dosen) akan sangat diuji disini karena meskipun perijinan sangat tergantung pada pemerintah pusat dan daerah, seringkali akademisi juga dimintai masukan sebagai tim pakar.
Terakhir, penulis teringat pesan paman Ben ke Peter Parker, bahwa semakin kuat semakin besar tanggung jawab. Selain tanggung jawab (kata teman penulis) minterno anak e wong, meneliti dan beban administratif, insan akademisi UIN Sunan Ampel Surabaya harus siap dengan kepakaran ilmu dan kejernihan hatinya dalam membantu masalah-masalah riil di masyarakat. Karena meskipun darat dan laut ini milih Allah, kitalah yang bertugas sebagai khalifah untuk mengelolanya.