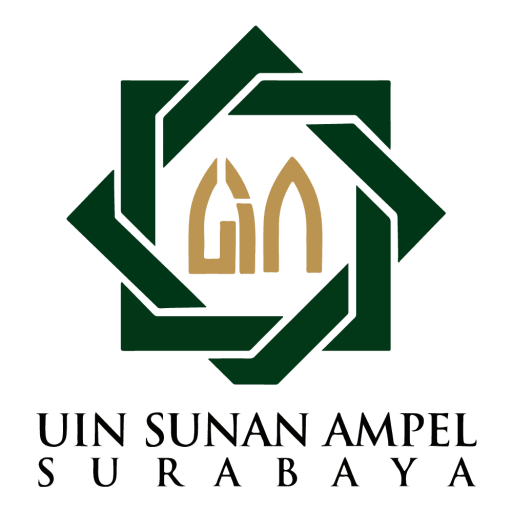Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara FSH UINSA Surabaya
Akhir-akhir ini kita diperkenalkan dengan istilah retret (sebenarnya retreat) bagi pejabat negara dan/atau pejabat publik. Sebenarnya istilah retreat tersebut sudah biasa, dan dilakukan oleh para pejabat negara dan/atau pejabat publik saat setelah dilakukannya pelantikan jabatan. Yang menjadi permasalahan adalah ketika retret yang rencananya diperuntukkan bagi 505 kepala daerah yang dilantik pada gelombang pertama, ternyata terdapat 53 kepala daerah yang tidak hadir ‘boikot’ karena ‘patuh’ pada instruksi pimpinan partai.
Tulisan ini bukan hendak menghakimi, tetapi hanya sekedar ingin berbagi (share) dari aspek hukum, bagaimana sebenarnya dasar pelaksanaan retret kepala daerah tersebut dan apakah boikot terhadap retret tersebut sebagai wujud ‘kudeta politik’ atau sekedar ‘ketidakpatuhan hukum’.
Aspek Hukum Retret Kepala Daerah
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), retret adalah memisahkan diri dari dunia ramai untuk mencari ketenangan batin. Dalam bahasa Inggris, retreat berarti “mundur” atau “mundurnya” atau “tempat pengasingan diri”. Istilah retreat ini banyak dikenal oleh gereja, yang juga diambil dari bahasa Prancis “La retraite” dengan makna yang sama, yaitu pengunduran diri, menyepi, dan menjauhkan diri dari kesibukan sehari-hari.
Menurut Kamus Cambridge, retret adalah menjauh dari suatu tempat atau orang untuk melarikan diri dari pertempuran atau bahaya. Dalam e-journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang ditulis Sumantri, dikutip Jumat (21/2/2025), retret merujuk pada salah satu kegiatan rohani yang dilakukan oleh suatu agama untuk membina dan meningkatkan iman dalam diri setiap umat.
Dalam konteks kerohanian, tradisi retret sudah dilakukan secara terorganisir dari 1491-1556 Masehi. Sejak itu, kegiatan retret kemudian populer, tak hanya di lingkup kerohanian tapi juga diadopsi ke berbagai bidang, seperti retret mahasiswa baru, retret dokter, retret perawat, dan profesi lainnya.
Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa retret secara bahasa berarti mengundurkan diri, menyendiri, menyepi, menjauhkan diri dari kesibukan sehari-hari, meninggalkan dunia ramai.
Lepas dari istilah dan pengertian tersebut, retret bagi pejabat negara dan/atau pejabat publik memiliki landasan yuridis sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemrintahan Daerah (baca UU Pemda 1999). Hal ini terutama terkait dengan Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Bermula pemerintaah ingin melihat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mencari model ideal dalam kerangka otonomi daerah. Untuk itu pemerintah perlu terlebih dahulu melihat dan memahami perkembangan konsep pembinaan dan pengawasan itu sendiri yang terwujud dalam pilihan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan dari masa ke masa. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka otonomi daerah mengalami dinamika, utamanya setelah lepas dari masa orde baru. UU Pemda 1999 merupakan peraturan penanda di era titik balik yang bertolak belakang dengan konsep kebijakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (baca UU Pemda 1974) yang sentralistik pada masa orde baru.
UU Pemda 1999 meletakkan otonomi yang luas kepada daerah di mana semua urusan pemerintahan adalah urusan pemerintahan daerah, kecuali urusan pemerintahan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat serta kewenangan lain seperti kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Selain itu, UU Pemda 1999 menempatkan daerah otonom tidak memiliki hubungan hierarki dengan satuan pemerintahan di atasnya. Kondisi kebijakan tersebut menyebabkan disharmoni hubungan antarsatuan pemerintahan pusat dan daerah. Hal ini berimplikasi langsung pada tidak efektifnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sebagai contoh adanya keengganan bupati/wali kota untuk dibina oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Selain itu, pemahaman yang tidak sesuai dengan konsep otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membuat kepala daerah menghendaki otonomi yang seluas-luasnya yang juga menimbulkan egosentris antardaerah dan satuan pemerintahan lebih tinggi, sehingga pembinaan dan pengawasan tidak berjalan dengan baik. Pilihan kebijakan dan praktik otonomi luas dalam UU Pemda 1999 dapat dipahami sebagai upaya pemerintah pada masa reformasi untuk mengendalikan situasi politik pascaorde baru yang sentralistik. Kebijakan tersebut juga tampaknya dipilih untuk meredam gejolak separatisme. Hal baik terjadi ketika satuan pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang berani dan kreatif sehingga kewenangan besar yang dimiliki dapat bermanfaat baik bagi daerahnya. Namun lebih banyak daerah yang belum memiliki kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sangat besar untuk ditangani sendiri.
Dengan adanya berbagai permasalahan yang timbul, diskursus dan evaluasinya menghasilkan penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (baca UU Pemda 2004) untuk menggantikan UU Pemda 1999. Dalam UU Pemda 2004, diatur penegasan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi dan setiap tingkatan satuan pemerintahan merupakan satu kesatuan. Penegasan juga meliputi peran dan posisi masing-masing satuan pemerintahan sehingga dapat dikatakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan berjalan relatif lebih baik dibandingkan dengan masa berlakunya UU Pemda 1999. Pembinaan dan pengawasan oleh internal diberikan kewenangan yang lebih besar. Namun demikian masih tetap terjadi disharmoni. Visi dan misi kepala daerah yang berbeda-beda, ditambah pilihan serta kepentingan politik yang tidak terkendali menyebabkan ketidakpatuhan sehingga pelaksanaan pembinaan dan pengawasan juga belum efektif. Kewenangan yang besar dari pengawas internal secara praktik juga belum menambah kekuatan dan terhindar dari penyimpangan, sehingga dilakukan evaluasi terhadap UU Pemda 2004.
Selanjutnya, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (baca UU Pemda 2014) yang berlaku hingga saat ini dengan dominasi kewenangan pemerintah pusat lebih besar dibandingkan masa UU Pemda 2004. Dalam UU Pemda 2014, urusan pemerintahan dibagi secara rigid, pembinaan dan pengawasan juga diatur lebih jelas, rinci, dan tegas. Hal ini sebagai ikhtiar normatif agar relasi antarsatuan pemerintahan dapat berjalan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi satu kesatuan termasuk dalam program pembangunan. Visi dan misi pemerintah daerah dapat berbeda-beda namun tetap mengacu pada program dan kegiatan pemerintah pusat, dalam hal ini visi dan misi Presiden. Dalam tataran kebijakan, pembinaan dan pengawasan sudah diatur dengan baik, segala potensi kebocoran sudah diantisipasi termasuk dalam hal pengawasan yang diatur dilakukan oleh internal melalui inspektorat dengan kelengkapannya dan eksternal oleh lembaga independen seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan Kejaksaan.
Namun persoalan terjadi dalam tataran implementasi. Posisi inspektorat daerah yang menjadi bagian dari pemerintah daerah sebagai pihak yang diawasi, masih menjadi penyebab belum efektifnya pengawasan internal pemerintah daerah. Kultur/budaya juga mempengaruhi relasi ini, berbeda dengan pengawasan yang bersifat eksternal yang dapat dikatakan lebih efektif. Hal ini menjadi salah satu faktor masih maraknya kepala daerah yang korupsi. Persoalan berikutnya yakni masih terjadi pemahaman yang belum selaras mengenai peraturan perundang-undangan terkait pembinaan dan pengawasan di masing-masing satuan pemerintahan, masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang ahli di bidangnya, serta koordinasi antarlembaga pengawas internal dan eksternal (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPK, dan inspektorat kementerian) yang masih perlu ditingkatkan efisiensinya. Permasalahan dalam tataran implementasi juga terjadi dari sisi pemenuhan pelayanan publik yang tercermin dari pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM), tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, serta belum optimalnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Idealnya, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah harus berorientasi pada tujuan otonomi daerah itu sendiri yakni kesejahteraan rakyat, penyediaan pelayanan publik yang memadai, dan kemandirian. Berikutnya, hal terpenting adalah harus tercapai satu kesatuan pendapat bahwa otonomi daerah yang ideal semestinya tidak hanya mampu merencanakan atau membuat perencanaan program dan kegiatan dan kemudian melaksanakan program dan kegiatan dimaksud namun juga harus mampu membiayai. Pemahaman otonomi harus disatukan bahwa keluasaan otonomi daerah harus tetap dalam kerangka NKRI. Pada prinsipnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan hukum dan bersifat demokratis serta berprinsip pada penyelenggaraan pemerintahan baik dapat tercapai jika terdapat check and balance yang baik dan dijalankan sebagaimana mestinya.
Diharapkan pengaturan pembinaan dan pengawasan dalam UU Pemda 2014 dapat diterapkan secara optimal dengan terus memaksimalkan kualitas pelaksanaannya. Evaluasi diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan kata lain UU Pemda 2014 merupakan dasar pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembinaan dan pengawasannya yang saat sekarang ini diwujudkan dalam bentuk penyelengaraan retret (retreat).
Retret Kepala Daerah: Antara Kepatuhan Hukum dan Belenggu Politik
Retret bagi pejabat negara dan/atau pejabat publik, khususnya para gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 direncanakan diselenggarakabn pada 21 sampai dengan 28 Februari 2025 dan digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Dari 505 kepala daerah yang dilantik pada gelombang pertama sebanyak 53 kepala daerah tidak hadir (absen), 6 (enam) di antaranya menyampaikan surat izin sedangkan sebanyak 47 kepala daerah tidak ada konfirmasi. Dengan tidak hadirnya 53 kepala daerah tersebut peserta yang telah terdaftar dan resmi mengikuti acara retreat berjumlah 450 kepala daerah. Sedangkan gelombang kedua diperuntukkan bagi 40 kepala daerah lainnya yang pelantikannya masih menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketidakhadiran 53 kepala daerah/wakil kepala daerah dari PDIP tersebut sebagai imbas dikeluarkannya instruksi langsung Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, melalui surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis 20 februari 2025. Yang menjadi pertanyaan apakah ini sebuah ‘kudeta politik’ atau sekedar ‘ketidakpatuhan hukum’.
Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa retret kepala daerah memiliki landasan hukum yang kuat yaitu sejak diundangkannya UU Pemda 1999 sampai berlakunya UU Pemda 2014 yaitu undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembinaan dan pengawasannya.
Pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pembinaan dan pengawasan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, penyediaan pelayanan publik yang memadai, dan kemandirian. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut harus berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sesuai dengan Asas otonomi daerah, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan tiga asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan demikian perayuran daerah (perda) yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Selain itu Perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, termasuk terhadap UU Pemda yang mengatur tentang Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Sebagaimana tujuan utama dari retret yang membangun konsolidasi kelembagaan dalam hal ini komunikasi dan konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka kegiatan retret dirancang untuk membangun Building Learning Commitment (BLC) atau untuk membangun kompetensi peserta. Building Learning Commitment (BLC) dktandai dengan beberapa indicator yaitu: (1) Proses membangun komitmen untuk mengikuti proses belajar; (2) Membangun kekompakan antar peserta; (3) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif; (4) Membangun komitmen bersama dalam mencapai tujuan pembelajaran; (5) Membentuk perangkat kelas; (6) Menumbuhkan sikap disiplin, kerjasama, peduli, toleransi, dan aktif; (7) Membangun kompetensi peserta; (8) Membangun kompetensi peserta dalam membangun aplikasi mobile; dan (9) Membangun pembelajaran berkualitas melalui pemahaman psikologi peserta didik
Adapun tujuan retret secara khusus adalah: (1) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap; (2) Meningkatkan kompetensi peserta; (3) Memfasilitasi peserta untuk melaksanakan tugas jabatan secara professional; (4) Memfasilitasi peserta untuk mencapai kinerja yang efektif dalam setiap kegiatan; (5) Memfasilitasi peserta untuk menyerap materi dengan baik; dan (6) Memfasilitasi peserta untuk berkomitmen dalam mengikuti pelatihan.
Berorientasi pada tujuan yaitu meningkatkan kompetensi, maka retret hendaknya didesian tidak sekedar untuk ‘omon-omon’ tetapi benar-benar untuk mencetak para kepala daerah yang ‘wasis lan waskito’ (cerdas dan kritis dalam merespon segala sesuatu). Mencetak kepala dearah yang mempu menyusun visi (good will) atau beretorika, tetapi mereka harus mampu mewujudkannya dalam kenyataan (action will). Sebuah kebijakan yang berpihak pada rakyat, untuk kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama dari negara/pemerintahan kesejahteraan (welfare state). Saat kepala daerah ‘lulus’ dari retret, ia ibarat seorang brahmana (pertapa) yang sepi ing pamrih rame ing gawe – tidak sekedar pandai berbicara tetapi kaya dengan prestasi nyata.
Dengan mengambil filosofi kepompong, retreat ibarat awal ulat yang rakus, menjijikkan dan dibenci orang, kemudian melakukan pertapaan (kepompong) menjauhkan dari segala gemerlap duniawi (megeng raga = menahan keakuan diri, menahan ego) untuk bisa mencapai derajat tertinggi seekor kupu-kupu yang indah, cantik dan disukai banyak orang. Kupu-kupu makanya nectar (sari madu) bunga, dan mendamaikan (membantu penyerbukan). Saat kupu-kupu singgah dirantingpun – ranting itu tidak bergoyang (tidak menimbulkan masalah/mengusik). Dalam konteks demikian maka terciptalah khoirun naasi ahsanuhum khulukon wa anfa’ahum linnaas. Insyaallah.