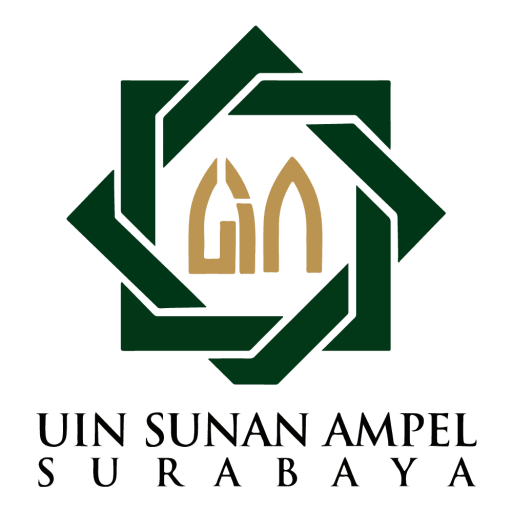Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
Mataku menyaksikan sendiri. Bukan kata orang. Kala itu aku sedang berdiri dalam antrean. Sesuai dengan ketentuan yang disampaikan di lembar konfirmasi janji temu. Di ruang pelayanan visa. Di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Di Jl. Merdeka Barat, Jakarta. Rabu, 19 Maret 2025. Kala itu, di kelompok waktu giliranku, terdapat sekitar 30 orang. Mereka telah berproses dalam antrean dari depan untuk menunggu giliran wawancara. Kami semua berdiri mengular. Mengikuti tali biru yang dibuat mengular agar diikuti oleh para pelamar visa itu (tali biru itu lebih dikenal dengan nama panjang Krisbow tiang pembatas antrean tali biru). Dengan begitu, antrean selalu tertib. Karena dikanal oleh tali biru itu.
Tiba-tiba, ada petugas keluar dari ruang dalam gedung pemeriksaan dokumen pengurusan visa itu. Petugas itu berseragam resmi sekuriti Kedutaan Besar AS. Begitu melihat rekannya yang berseragam sekuriti keluar dari ruang dalam pemeriksaan dokumen visa, seorang petugas perempuan yang berada di bagian check point depan langsung memberi tahu. Isinya, ada seorang perempuan yang sedang berada dalam antrean itu. Perempuan itu berada di atas kursi roda. Posisinya persis di barisan depanku. Ada pendamping di sampingnya. Lalu, pegawai perempuan itu memberikan isyarat butuhnya afirmasi layanan khusus untuk perempuan pelamar visa yang berkebutuhan khusus itu.
Dalam hitungan detik, petugas sekuriti kedutaan itu membuka tali biru. Lalu dia meminta perempuan berkebutuhan khusus yang berada di atas kursi roda itu untuk segera bergeser maju. Dan lalu keluar dari baris antrean. Untuk selanjutnya usai keluar dari baris antrean itu, dia diuruskan oleh petugas sekuriti itu untuk mendapatkan pelayanan khusus. Mulai didahulukan tanpa antrean hingga pendampingan masuk ke ruang proses wawancara visa di gedung bagian dalam kedutaan itu. Semua proses itu dibikin mudah. Perempuan itu pun didahulukan untuk mendapatkan pelayanan. Hingga seluruh rangkaian proses wawancara pun purna dilaksanakan.
Intinya, proses pelayanan pengurusan visa yang diberikan kepada perempuan berkebutuhan khusus yang berada di atas kursi roda itu dibuat tidak sama dengan umumnya. Ada kemudahan. Ada fasilitasi. Ada percepatan. Untuk menunjukkan perhatian dan afirmasi kepada perempuan berkebutuhan khusus itu. Kondisi fisik sang perempuan menjadi pertimbangan utama. Keterbatasan fisiknya mendorong diberikannya perlakuan khusus kepadanya. Para petugas sekuriti Kedutaan Besar AS itu tampak sangat memahami prinsip mendesaknya pelayanan afirmasi kepada mereka yang sedang dalam kondisi berkebutuhan khusus. Mengabaikannya akan segera dimaknai sebagai ketidakmuliaan perilaku. Termasuk kepada perempuan itu.
Itulah akhlaq pelayanan publik. Semua dibikin tertib. Dalam antrean. Sesuai dengan urutan. Tak peduli siapa Anda, mengantre tetap menjadi prosedur standar. Dan memang dengan prinsip itu, semua pelamar visa di Kedutaan Besar AS itu mengantre dan menunggu giliran dilayani. Laki-perempuan secara tertib mengikuti antrean. Anda sendirian atau berombongan, tetap harus sesuai antrean. Dan, tak pernah terdengar juga ada di antara mereka yang meminta untuk didahulukan atas yang lain. Apalagi hingga harus berbisik dan atau me-lobby petugas sekuriti kedutaan besar itu. Untuk meminta perlakuan khusus. Tak pernah terjadi sama sekali.
Itulah prinsip standar pelayanan publik. Berlaku sama. Untuk semua pemohon layanan publik. Mereka semua diperlakukan setara. Tak ada perlakuan diskriminatif satu atas lainnya. Atas dasar preferensi apapun. Dan juga tak ada permintaan untuk diberikannya perlakuan khusus. Karena menganggap dirinya lebih dari lainnya. Tak ada sama sekali. Tak kutemukan semua itu selama aku berproses untuk wawancara pengurusan visa itu. Namun, kepada yang berkebutuhan khusus seperti perempuan yang berada di atas kursi roda di atas, perlakuan khusus diberikan. Karena keterbatasan fisiknya, mereka yang berada dalam kondisi seperti perempuan itu pun dihadapkan pada terbatasnya kemampuan fisik untuk menunaikan kebutuhannya secara mandiri. Karena itulah, afirmasi sudah sewajarnya diberikan. Dan, itulah salah satu bentuk pula dari akhlaq pelayanan publik.
Dan akhlaq pelayanan publik seperti di atas, bahkan, sudah menjadi bagian dari perilaku publik secara internasional. Pergilah ke banyak negara. Di sana hampir bisa dengan mudah didapatkan praktik akhlaq pelayanan publik seperti di atas. Kepada mereka yang dalam kondisi lemah dan atau tidak berkeuntungan, seperti perempuan hamil, individu berkebutuhan khusus, dan orang tua renta selalu mendapatkan afirmasi pelayanan seperti itu. Pasti di sana ada berbagai bentuk afirmasi, mulai dari pemberian prioritas layanan hingga perbantuan khusus. Kelompok individu yang seperti itu pasti mendapatkan afirmasi pelayanan di ruang publik.
Lalu, apakah afirmasi seperti itu bisa dibilang diskriminasi? Jawabannya: Ya betul, itu diskriminasi juga. Tapi itu diskriminasi positif. Sekali lagi bahwa afirmasi itu berarti diskriminasi positif. Yaitu bentuk perlakuan khusus yang dibedakan dari selainnya. Diberikan hanya kepada orang-orang yang sedang dalam posisi membutuhkan. Bisa karena melemahnya fisik akibat usia tua. Bisa pula karena kehamilan. Bisa pula karena kebutuhan khusus menyusul keterbatasan dan atau perbedaan kecakapan fisik. Frase yang disebut terakhir ini kini lebih dikenal dengan istilah difabilitas. Berasal dari frase different ability. Kecakapan yang berbeda. Sebagian memang masih ada yang menyebut dengan istilah lain: disabilitas.
Akhlaq pelayanan publik memang memiliki prinsip normatif yang universal. Di antaranya tak menjadikan keyakinan atau agama sebagai faktor pembeda perlakuan. Pelayanan publik tak boleh diberikan secara memudahkan kepada individu warga yang berkeyakinan dan atau beragama tertentu. Lalu menyulitkan mereka yang berkeyakinan dan atau beragama yang berbeda selainnya. Mayoritas atau minoritaskah keyakinan atau agama yang sedang dihadapi itu. Individu warga yang menganut keyakinan atau agama mayoritas bukan berarti kemudian diberikan perlakuan khusus. Begitu pula sebaliknya. Atas nama keyakinan atau agama minoritas, lalu pemeluknya diberikan perlakukan khusus. Tentu saja tidak.
Tapi, akhlaq pelayanan publik senantiasa memberikan ruang yang lebar bagi lahirnya perlakuan khusus kepada mereka yang dalam posisi berkebutuhan khusus. Atas latar belakang yang berbeda-beda. Seperti yang kuuraikan sebelumnya. Dan mereka yang berada dalam kondisi regular tak boleh menuntut adanya perlakuan khusus serupa seperti yang diberikan secara partikular kepada mereka yang dalam kondisi berkebutuhan khusus di atas. Akhlaq pelayanan publik sangat empatik terhadap mereka yang berkebutuhan khusus. Sebagai bentuk dan ukuran langsung atas prinsip afirmasi yang harus ditunaikan.

Nah berangkat dari kisah di atas, ada dua pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman menyaksikan langsung afirmasi layanan kepada yang berkebutuhan khusus di Kedutaan AS di Jakarta di atas. Pertama, jangan tinggalkan akhlaq, termasuk saat berada dalam pelayanan publik. Itu karena akhlaq itu universal. Berlaku umum. Terlepas dari sekat-sekat negara dan gugus masyarakat. Kasus pelayanan publik yang dipertunjukkan oleh sekuriti Kedubes AS di Jakarta kepada seorang ibu yang sedang berada di atas kursi roda di atas menjelaskan bahwa akhlaq publik berlaku universal. Afirmasi pelayanan kepada mereka yang dalam kondisi lemah fisik dan atau tidak berkeuntungan adalah akhlaq pelayanan publik yang harus dijunjung tinggi.
Akhlaq pelayanan publik itu berlaku merata di banyak kawasan di dunia. Anda yang bepergian ke Australia akan menemukan pemandangan seperti itu dalam pelayanan publik yang diselenggarakan. Di manakah pelayanan publik itu diselenggarakan. Di kantor pemerintahan. Di pusat keramaian. Semua pasti menerapkan akhlaq dalam pelayanan publik itu. Saat Anda ingin pergi yang lebih jauh lagi juga akan menemukan pemandangan serupa dalam pelayanan publik. Ke Kanada, sebagai misal dari kawasan Amerika Utara, pemandangan yang serupa juga begitu mudahnya ditemukan. Mungkin saja ditemukan kasus tertentu di sebuah kawasan di dunia. Tapi gambar besar pelayanan publiknya tak akan jauh-jauh dari akhlaq seperti kuuraikan di atas.
Karena itu, abai terhadap akhlaq pelayanan publik itu akan sama dengan lemahnya akhlaq publik. Saat tidak ada pengetahuan atas akhlaq publik, kata “abai” tentu tak bisa digunakan. Namun, kata “abai” bisa segera dikenakan saat pengetahuan sudah didapatkan, namun pengetahuan itu tidak terkonversi ke kesadaran. Akibat lemahnya kesadaran, maka praktik lemah akhlaq pun akhirnya terjadi. Dan, itu tentu saja merupakan ironi besar bagi penyelenggara layanan publik. Dan jika itu terjadi, maka sudah barang tentu pula itu sebuah kesalahan besar dari sebuah institusi yang mempekerjakan pejabat dan penangung jawab layanan publik itu.
Semua pelaku dan penangungjawab pelayanan publik tak sepatutnya mengabaikan akhlaq publik. Baik akhlaq dalam pengertian penjaminan kesetaraan pelayanan kepada semua penerima layanan di tengah-tengah Masyarakat, maupun afirmasi pelayanan kepada individu tertentu dalam masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik maupun kecakapan yang berbeda. Seperti kumaksudkan di atas. Praktik pengabaian atas akhlaq pelayanan publik di atas bisa saja berbentuk verbal, gesture, maupun tindakan. Pelayanan di Kedutaan AS di Jakarta seperti yang kutemukan di atas memberi kita pelajaran untuk tak melupakan akhlaq pelayanan publik. Afirmasi adalah salah satunya saja. Kesetaraan adalah contoh lainnya dalam gambar besarnya.
Kedua, perbaikan pelayanan tak perlu ditunda-tunda. Begitu diketahui atau teridentifikasi adanya kekurangan, tindakan koreksi dan perbaikan langsung patut untuk kontan dilakukan. Pengalaman pemberian layanan di Kedutaan AS di Jakarta yang kutemukan di atas memberi pelajaran penting. Bahwa diketahuinya adanya perempuan berkebutuhan yang sedang dalam antrean langsung dilakukan afirmasi. Diberikan kemudahan. Juga difasilitasi untuk terjadinya percepatan layanan. Dengan begitu, yang berkebutuhan khusus pun segera mendapatkan pelayanan afirmatif dibanding yang regular pada umumnya.
Tentu untuk kepentingan realisasi koreksi dan pelayanan di atas, SOP menjadi penting. Kita butuh adanya standard operating procedure. Kita butuh prosedur standar operasional dalam pelayanan publik. Semua tahapan diidentifikasi. Semua bagian dimitigasi. Dan semua komponan serta langkah ditelaah secara menyeluruh. Semua itu harus dilakukan untuk memastikan semua tahapan, bagian, dan langkah dalam kontrol penuh agar berjalan efektif dan efisien. Dengan SOP ini, maka setiap ada yang kurang dalam praktik di lapangan selalu bisa diketahui untuk diberikan perbaikan secepat mungkin.
Ketiga, pengembangan akhlaq pelayanan publik itu butuh sinergi yang kuat di internal penyelenggara. Memang semua nilai berangkat dari individu-individu. Dan itu prinsip utama dalam pengembangan kualitas diri sumber daya manusia. Namun, semua nilai itu butuh pelembagaan. Nama lainnya, institusionalisasi. Bagian sentral dari pelembagaan ini adalah sinergi yang kuat di internal penyelenggara pelayanan publik itu. Sebab, sebuah nilai tak akan bisa menggerakkan praktik perubahan jika hanya berhenti pada diri individu semata. Dibutuhkan kebersamaan sebagai wujud dari sinergi untuk lahirnya praktik baik di kehidupan publik.
Kebersamaan dalam sinergi yang kuat di atas memiliki kontribusi yang besar agar nilai baik yang sudah berkembang di masing-masing individu (private virtues) bisa menguat menuju nilai kebajikan bersama (civic virtues). Dan untuk itu, dibutuhkan kesadaran bersama yang tumbuh dan berkembang di antara individu-individu dalam gugus sosial itu. Lalu, kesadaran itu dilanjutkan ke dalam praktik bersama. Dengan begitu, nilai kebajikan bersama akan dengan cepat terwujud. Sebab, yang dibangun bukan hanya mental diri individu, melainkan mental bersama di ruang publik.
Praktik baik akhlaq pelayanan publik yang kutemukan di Kedutaan Besar AS di Jakarta seperti kuuraikan di atas memberikan pelajaran penting betapa kesadaran bersinergi dan berkebersamaan di internal pegawai penyelenggara pelayanan publik di kantor kerjanya mampu menggerakkan terwujudnya akhlaq pelayanan publik yang baik. Sinergi dan kebersamaan itu ditunjukkan oleh kerjasama yang apik antara pegawai di bagian check point depan kantor kedutaan dimaksud dan rekannya yang berseragam sekuriti yang bertugas di ruang dalam pemeriksaan dokumen visa. Seperti dijelaskan di atas, sinergi yang kuat itu akhirnya melahirkan pelayanan yang tertib, termasuk afirmasi terhadap mereka yang berkebutuhan khusus.
Masihkah ada di antara kita yang belum yakin dengan prinsip akhlaq pelayanan publik? Rasanya penting untuk menilik kembali ajaran nubuat. Bukankah Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan akhlaq pelayanan publik. Begini nasihatnya: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا. “Tidaklah termasuk bagian dari golongan kami, orang yang tidak mengasihi anak-anak kecil dan tidak pula menghormati para orang tua,” begitu arahan Nabi yang mulia itu. Penyebutan kalimat لَيْسَ مِنَّا (“tidaklah termasuk bagian dari golongan kami”) menunjukkan tingginya perhatian Islam terhadap akhlaq pelayanan publik. Dan, penyebutan مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا (“orang yang tidak mengasihi anak-anak kecil”) dan يَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا (“tidak pula menghormati para orang tua”) adalah ilustrasi partikular atas akhlaq publik itu.
Tentu, salah satu bentuk dan cara “mengasihi anak kecil” dan “menghormati orang tua” seperti yang dicontohkan secara partikular oleh ajaran nubuat di atas adalah memberikan afirmasi layanan. Memprioritas, memfasilitasi, dan mempercepat layanan adalah di antara contoh afirmasi layanan yang bisa diterimakan kepada mereka yang masuk kategori rentan itu. Dan, afirmasi atas dasar kondisi fisik, seperti yang dicontohkan oleh para pegawai kedutaan AS di Jakarta di atas, adalah salah satu yang utama.