
Kritik terhadap episode program XPOSE Uncensored Trans7 berjudul “Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok, Emang Gini Kehidupan di Pondok?” bukanlah bentuk serangan terhadap kebebasan pers, melainkan ajakan untuk melakukan refleksi etis dan sosiologis. Tayangan tersebut memperlihatkan bahwa media masih gagal belum sepenuhnya memahami dinamika kebudayaan lokal serta pluralitas religius yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.
Jika pola framing semacam ini terus dibiarkan, maka akan tercipta jarak simbolik antara masyarakat pesantren dan masyarakat umum. Akibatnya, pesantren yang sejatinya memiliki peran penting dalam membentuk karakter, spiritualitas, dan nasionalisme dapat dipersepsikan secara negatif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi media yang lebih kritis dan pemahaman mendalam tentang dunia pesantren khususnya di kalangan jurnalis dan rumah produser konten. Dengan begitu, mereka dapat melihat pesantren bukan sebagai objek eksotisme budaya, melainkan sebagai subjek sosial yang memiliki nilai-nilai unik, tradisi luhur, serta kontribusi besar dalam pendidikan agama, pembentukan karakter, budi pekerti, dan adab generasi bangsa.
Masalahnya bukan pada kebebasan pers, melainkan pada ketidakmatangan epistemologis; media gagal membedakan antara apa yang aneh, dan apa yang bermakna. Judul provokatif mungkin menjual, tapi tidak mendidik. Ia menambah jarak antara masyarakat urban-rural dan pesantren, seolah dunia pesantren adalah ruang asing yang perlu ditertawakan, bukan dipahami. Yang lazim dan seharusnya pesantren menjadi kebanggaan tersendiri dan perlu pemahaman secara mendalam bagi yang tidak tahu apa itu Pondok Pesantren.
Menjadi sorotan publik bukan karena keunikan informasinya, tetapi karena kesalahan fundamental dalam cara memaknai realitas sosial pesantren. Judul yang provokatif itu menggiring persepsi seolah kehidupan di pondok adalah bentuk keterbelakangan dan irasionalitas. Padahal, di balik tindakan sederhana seperti berjalan merunduk santri sambil jongkok, tersimpan makna adab, etika, dan spiritualitas yang sangat tinggi, nilai-nilai itu yang justru menjadi inti kebudayaan pesantren.
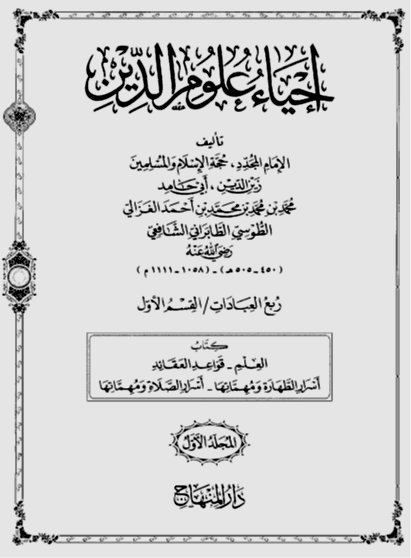
Dalam tradisi pesantren, adab bukan sekedar sopan santun lahiriah, melainkan sistem nilai yang membentuk karakter, moral, dan spiritualitas seorang santri. Imam al-Ghazali dalam Ayyuha al-Walad (2012: 11), menegaskan bahwa ilmu dan adab menjadi penting; janganlah engkau merugi dalam beramal, tidak hampa spiritual, serta senantiasa berupaya mengamalkan ilmu yang dimiliki. Karena itu, sebelum seorang santri belajar kitab kuning, ia terlebih dahulu belajar tata krama mencari ilmu.
Pada karya lain, Ihya’ ‘Ulumuddin, (2011: 14-15, Jilid-I) menjelaskan bahwa ilmu terbagi menjadi dua macam, yaitu ilmu lahir dan ilmu batin. Bagian batin berkaitan dengan keadaan hati dan akhlak jiwa (adab) yang terbagi menjadi dua, yakin yang terpuji dan yang tercela. Menurut Zakiy Mubarak dalam al-Akhlaq ‘inda al-Ghazali (2017: 148) menjelaskan bahwa akhlak yang baik didefinisikan sebagai bentuk penyempurnaan terhadap tiga kekuatan utama (الميزان), yaitu kekuatan berpikir (قوة التفكير), kekuatan nafsu (قوة الشهوة), dan kekuatan amarah (قوة الغضب). Akan tetapi, akhlak adalah kondisi batin yang membuat jiwa siap untuk menahan atau memberi, berbuat atau meninggalkan sesuatu. Maka, akhlak pada hakikatnya adalah keadaan dan bentuk batin dari jiwa manusia.
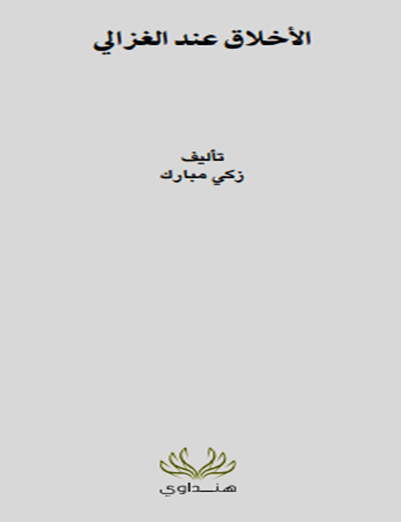
Adab atau akhlak di pesantren mengajarkan penghormatan terhadap kiai-nyai, guru, sesama, dan lingkungan. Misalnya, aturan tidak boleh minum sambil berdiri, atau tidak boleh bersikap serampangan di depan guru, bukanlah bentuk paksaan buta, tetapi latihan menundukkan ego dan melatih kesadaran spiritual. Minum sambil merunduk adalah simbol kerendahan hati di hadapan nikmat Tuhan; tindakan kecil yang bermakna besar dalam pembentukan karakter.
Peristiwa semacam ini seharusnya tidak terulang kembali dalam penyiaran media televisi. Media sebagai ruang publik yang berperan membangun kesadaran sosial, tidak semestinya menyoroti tradisi pesantren hanya sebagai keanehan budaya. Bila hal itu terus berulang, bisa jadi media tengah kehilangan kepekaan dalam memahami dimensi adab, etika, dan spiritualitas yang menjadi ruh kehidupan pesantren. Dalam tulisan Abuya Kiai Said Aqil Siroj berjudul Kembali Ke Pesantren (2015: 28-31), mengatakan fungsi pesantren mampu melahirkan sikap-sikap yang tasamuh (lapang dada), tawazun (seimbang), dan i’tidal (adil). Pendidikan pesantren seperti ini tidak akan memproduksi sikap radikal yang berpunggungan dengan kultur asli moderat ajaran Islam.
Dalam perspektif sosiologi, tayangan XPOSE Uncensored Trans7 tentang pesantren adalah cermin bagaimana media modern masih bergulat dengan bias kultural dan komersial. Melalui teori konstruksi sosial, representasi, dan kekuasaan simbolik, kita memahami bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar citra santri, melainkan citra kebangsaan dan kemanusiaan.
Sudah saatnya media berhenti melihat pesantren dari kejauhan, dan mulai belajar mendengar dari dalam. Sebab di balik konten tersebut, penulis menginterpretasikan bahwa berjalan dengan jongkok oleh santri, minum sambil merunduk, tersimpan nilai adab, kesederhanaan, dan penghormatan; sesuatu yang justru sedang hilang dalam kehidupan modern kita.

Karena itu, pandangan filosofis tentang adab bagi seorang santri di pesantren menjadi sangat penting dan utama. Imam Ḥujjat al-Islam al-Ghazali (2012: 12-13) dalam Ayyuha al-Walad nasihatnya yang mulia, beliau berkata:
قال الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي : أيُّها الولدُ, … ولوقرأت العلم مائة سنةٍ وجمعت ألفَ كتابٍ لاتكون مستعداً لرحمة اللهِ تعالى إلاّبالعملِ (۱۲-۱٣)
(Wahai anakku, … sekalipun engkau mempelajari ilmu selama seratus tahun dan mengumpulkan seribu kitab, engkau tidak akan siap menerima rahmat Allah kecuali dengan amal).
Didalam Syarah Ayyuhal Walad ditulis oleh Muhammad Hadi Asy-Syamarkhi Al-Mardini (2016: 9-10) tentang keharusan mengamalkan ilmu, dan memperoleh kekuatan penuh dalam menguasainya, serta menghimpun seribu kitab, baik dengan menulis, menghafal, atau melalui kemampuan yang sangat mendalam, engkau tetap belum siap untuk mendapatkan rahmat Allah, keridaan-Nya, pahala, serta keselamatan dari rasa takut dan kebinasaan, kecuali dengan amal perbuatan yang saleh. Karena itu penting keselamatan di akhirat bukan karena banyaknya pengetahuan, tetapi karena amal yang didasari ilmu dan ikhlas.

Senada dengan pesan Abu Zakariyya al-‘Anbari, dalam Min Waṣaya al-‘Ulama’ li Ṭalabati al-‘Ilmi, ditulis ‘Abd al-‘Aziz bin Muḥammad bin ‘Abd Allah as-Sadhan (2016: 9-10), fungsi interkoneksi antara ilmu dan adab, beliaunya mengatakan melalui ungkapan :
قال أبو زكريا العنبري: علمٌ بلاأدب كنارٍبلا حَطَب, وأدبٌ بلا علم كرُوحٍ بلا جِسم (٩-۱۰)
(Ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar, sedangkan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh).
Ungkapan-ungkapan diatas menegaskan bahwa pencarian ilmu dalam tradisi pesantren tidak hanya berorientasi pada pengembangan kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan moral dan spiritual melalui penanaman adab yang luhur, seperti memuliakan kiai-nyai, guru, serta seluruh keluarga besar pondok pesantren sebagai wujud amal dan cerminan ruh adab bagi para santri.
Dalam kehidupan pesantren, ketawaduan santri menjadi cermin kemuliaan akhlak dan kekuatan spiritual yang tumbuh dari tradisi panjang para Ulama. Sikap hormat dan rendah hati kepada kiai-nyai, keluarga pondok, serta para guru bukan sekadar tata krama, melainkan bagian dari amal saleh yang lahir dari kesadaran akan keberkahan ilmu.
Para santri meneladani nilai-nilai adab melalui perbuatan-perbuatan sederhana namun sarat makna: mencium tangan kiai dan nyai, berjalan dengan menunduk penuh hormat di hadapannya, tidak mendahului saat berjalan bersamanya, berebut untuk lebih dahulu menata sandalnya, bahkan memberikan bisyarah sebagai bentuk ungkapan terima kasih. Semua itu bukan simbol kepatuhan buta, melainkan wujud cinta dan penghormatan terhadap sumber ilmu secara istiqamah dalam mengaji, beradab, dan beramal.
Pengabdian santri dijalankan tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan duniawi. Sebab mereka memahami, pemberian yang paling mulia adalah pemberian yang tulus, yang tidak menuntut balasan. Dari ketulusan itulah insya Allah terpancar keberkahan, sebuah rahmat yang tak tampak, tetapi dirasakan dalam perjalanan menuntut ilmu. Santri menuntut ilmu, bahwa doa kiai-nyai, restu guru, dan ridha Allah adalah anugerah terbesar yang hanya dapat diraih dengan adab dan pengabdian yang ikhlas.
Perkuat Literasi Media Kepesantrenan
Kritik ini ditujukan Trans7 dalam tayangan program XPOSE Uncensored berjudul “Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok, Emang Gini Kehidupan di Pondok?”, pesan ini sebagai ajakan reflektif bagi media televisi agar lebih memahami konteks budaya lokal pesantren sebelum menayangkan konten keagamaan dan sosial. Terdapat tiga langkah strategis yang dapat dilakukan media untuk memperbaiki hal tersebut.
Pertama, penguatan literasi kultural bagi jurnalis, reporter, dan produser. Para pelaku media perlu memiliki pemahaman dasar mengenai etika epistemologis pesantren dan nilai-nilai islam tradisional. Upaya ini dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren-pesantren besar di Jawa.
Kedua, penerapan etika framing dan penggunaan bahasa media yang berimbang. Judul dan narasi berita harus mencerminkan penghormatan terhadap objek liputan, bukan menimbulkan stigma sosial atau kesalahpahaman publik.
Ketiga, perlu adanya dialog yang berkelanjutan antara media dan pihak pesantren. Pesantren hendaknya dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan liputan, mulai dari penentuan tema tayangan, proses pengambilan gambar di lapangan, hingga tahap monitoring dan evaluasi tayangan. Dengan demikian, akan tercipta pertukaran makna yang setara, bukan sekadar liputan sepihak dari pihak media. Agar kekeliruan dalam memframing keragaman budaya pesantren tidak lagi terulang dalam praktik pemberitaan media.

Tantangan dalam konteks masyarakat modern yang sering kali kehilangan arah moral, pesantren justru hadir sebagai ruang pembentukan moral self manusia yang berilmu sekaligus beradab. Ketika sebagian pihak menertawakan hal-hal kecil yang sarat dengan nilai kesantunan, tanpa disadari mereka sebenarnya sedang menertawakan akar budaya mereka sendiri.
Dalam kajian disertasi Zamakhsyari Dhofier dari Australian National University (ANU) berjudul The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java (1980: 49, 82). Ada bentuk aksentuasi peran penting kiai dalam perkembangan tradisi pesantren sebagai pusat pendidikan dan pelatihan Islam di Jawa, termasuk salah satunya ulasan mengenai pesantren Lirboyo. Pesantren di berbagai wilayah di Jawa terbukti mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika serta transformasi kehidupan modern di Indonesia.
Peran kiai menurut Dhofier, terlihat dalam upaya melestarikan tradisi pesantren, mengembangkan lembaga pendidikan Islam agar senantiasa adaptif terhadap kebutuhan zaman, serta dalam kontribusinya membentuk ideologi Ahlussunnah wal Jama‘ah (yakni pengikut tradisi Nabi dan para ulama) di kalangan umat Islam Jawa. Bandingkan karya Martin van Bruinessen (2012: 85-86) dalam Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat; mengatakan salah satu tradisi agung (great tradition) di Indonesia adalah tradisi pengajaran agama Islam yang muncul di pesantren Jawa dan di luar Jawa serta Semenajung Malaya. Kunci islam tradisional adalah lembaga pesantren sendiri, peran dan kepribadian kiai yang sangat menentukan. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, penulis memandang bahwa para santri menumbuhkan tradisi ta‘dzhim, yaitu sikap penghormatan, pengagungan, dan pemuliaan yang mendalam kepada kiai-nyai, guru, serta seluruh keluarga besar pondok pesantren sebagai wujud adab dan spiritualitas dalam proses menuntut ilmu.
Sebagaimana kritik yang dikatakan oleh sosiolog Anthony Giddens dalam The Consequences of Modernity (1990: 21-24); Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age (1991: 4-6) modernitas membawa risiko dislokasi makna, di mana tradisi dianggap ketinggalan zaman. Padahal, tradisi seperti di pesantren adalah mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara ilmu dan adab.

Tayangan program XPOSE Uncensored Trans7 memicu kemarahan demontrasi kalangan santri seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai sumber sensasi, melainkan dijadikan cermin introspeksi bersama bagi media. Media perlu memahami bahwa perbedaan tradisi pesantren bukanlah sesuatu yang aneh, melainkan manifestasi dari kekayaan nilai luhur yang sarat makna kesantunan (humanity) dan kedalaman akhlak (tamadun, tsaqafah, hadharah).
Adab dalam tradisi pesantren bukanlah tanda keterbelakangan, melainkan wujud pendalaman spiritual yang menumbuhkan kesantunan sosial dan keseimbangan batin. Di tengah arus modernitas yang kian mengikis sopan santun dan etika publik, justru tradisi pesantren hadir sebagai penyangga utama bagi tegaknya kembali adab, etika kesantunan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang utuh dalam kehidupan berbangsa. Karena itu adab jadi perhatian publik di tengah tantangan masyarakat modern.
Pesan nasihat ‘Abdullāh bin Muḥammad al-Qaḥṭani dalam al-Maḥfuẓat asy-Syi‘riyyah ditulis Ibnu Hadi al-Wada’iy (2008: 53) mengatakan,
قال عبدالله بن محمد القحطاني: كُن طَالبًا للعلِم واعمَل صالِحًا, فَهُماإلى سُبُلِ الُهدى سَبَبَانِ (٥٣)
(Jadilah penuntut ilmu dan beramallah saleh, sebab keduanya merupakan dua jalan yang menuntun menuju petunjuk kebenaran). Dengan demikian, adab dalam tradisi kepesantrenan mengajarkan pesan luhur; pencari ilmu yang tulus dan pengamal kebajikan yang ikhlas, karena dari keduanya terpancar cahaya petunjuk menuju kebenaran sejati.
* Muchammad Ismail, Dosen FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya.

