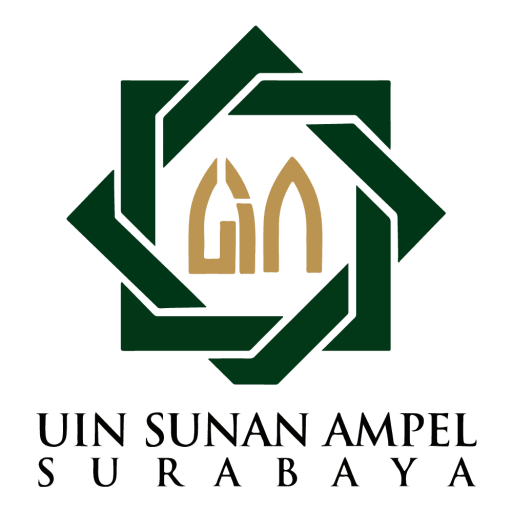Oleh: Dr. Ida Rochmawati, M.Fil.I
Hari Kartini selalu diidentikkan dengan Kebaya. Peringatan sederhana untuk mengenang perjuangan Kartini di Indonesia sering kali dilakukan dengan memakai kebaya di tanggal 21 April. Kebaya sebenarnya tidak hanya milik Kartini. Perempuan Jawa sejak masa Hindia Belanda hingga tahun 1970-an mayoritas masih memakai kebaya sebagai pakaian keseharian.
Bukan hanya soal kebaya. Baju hanyalah simbol. Ia hanya tanda yang tidak akan bermakna apa pun jika tidak dikorelasikan dengan penanda. Kebaya adalah pakaian adat Jawa yang sebenarnya mencerminkan simbol budaya Jawa tentang perempuan. Saat kebaya dipadukan dengan jarik sebenarnya menyimbolkan keterbatasan ruang gerak perempuan pada masyarakat Jawa. Seperti nada kritik Kartini dalam suratnya kepada Stella Zeehandelaar,
“…Jalan kehidupan gadis Jawa itu sudah dibatasi dan diatur menurut pola tertentu. Kami tidak boleh punya cita-cita. Satu-satunya impian yang boleh kami kandung ialah; hari ini atau esok dijadikan istri seorang pria yang ke sekian!.. dalam masyarakat Jawa, persetujuan pihak wanita tidak perlu. Ayahku, misalnya, memberitahu aku: “Kau sudah kawin dengan si Anu’, lalu aku harus ikut dengan suamiku…(Surat kepada Stella Zeehandelaar, 23 Agustus 1899)
Melalui Kartini, simbol pengaturan gerak perempuan Jawa didobrak melalui sikap kritisnya terhadap berbagai hal, meski tubuhnya terpenjara oleh adat dan budaya Jawa yang sulit dia kendalikan. Dalam keterpaksaan ia menerima semua tatanan dan aturan masyarakat Jawa yang memingit dan menikahkan perempuan dengan pilihan orang tua, tidak bisa menolak pernikahan poligami dan menerima kekecewaan tidak bisa berangkat sekolah ke Belanda hanya karena dia seorang perempuan. Hal ini tidak membuatnya berhenti melakukan pengembaraan nalar. Pikirannya tetap bebas mengembara dengan menuliskan semua pikirannya ke dalam surat yang ditulisnya kepada para sahabatnya di Belanda.
Kartini berontak melalui tulisan-tulisannya yang mengkritisi banyak hal yang terjadi pada dirinya, perempuan di sekitarnya hingga masyarakat pada umumnya. Kartini melakukan upaya perubahan melalui pendidikan. Melalui pendidikan inilah dia yakin orang akan berubah secara nalar pikir. Sikap kritisnya yang diungkap dalam tulisan maupun perkataannya menunjukkan betapa besar pengaruh pendidikan pada sikap kritis yang dia miliki.
Pola pendidikan Belanda untuk bangsawan saat itu menuntun Kartini memiliki kesempatan membaca yang luas dan membangun jaringan intelektual dengan para sahabatnya. Surat menyuratnya menjadikan Kartini pribadi yang kritis. Pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan dalam tulisan yang dia kirim pada sahabatnya di Belanda menyiratkan keresahan sosial bangsanya. Sehingga dia meminta syarat pada suaminya untuk mendirikan sebuah sekolah perempuan untuk mendidik para perempuan di sekitarnya. Dia yakin pendidikan adalah gerbang membuka cakrawala pikiran untuk bisa berubah. Meski dia bukan perempuan pertama yang mendirikan sekolah untuk perempuan, namun tulisanlah yang membuat dia melesat menjadi ikon agen perubahan bagi perempuan.
Kesadaran kritis Kartini juga membawanya pada kesadaran spiritual. Di saat mendengarkan pengajian Kyai Sholeh Darat yang membacakan Surat Fatihah, dalam bahasa Arab, Kartini merasa ada yang kurang pas dengan transfer pengetahuan agama pada masyarakat muslim di Jawa. Kenapa memakai bahasa Arab bukankan orang Jawa tidak mengerti maknanya?
“Di sini, orang belajar Alquran tapi tidak memahami apa yang dibaca. Aku pikir, adalah gila orang diajar membaca tapi tidak diajar makna yang dibaca. Itu sama halnya engkau menyuruh aku menghafal bahasa Inggris, tapi tidak memberi arti. Aku pikir, tidak jadi orang saleh pun tidak apa-apa asalkan jadi orang baik hati. Bukankah begitu Stella?” (Surat Kartini kepada Stella Zihandelaar, 6 November 1899)
Kesadaran kritis ini ditangkap oleh Kyai Sholeh Darat untuk melakukan sebuah transformasi pengetahuan agama yang sebelumnya tidak terpikirkan. Dalam pertemuannya dengan Kyai Sholeh Darat setelah sebelumnya mengikuti pengajiannya yang menjelaskan tafsir al Fatihah dengan menggunakan bahasa Jawa, deretan pertanyaan dia sampaikan ke Kyai Sholeh Darat,
“Bukan buatan rasa syukur hati ini kepada Allah. Namun, aku heran mengapa selama ini para ulama melarang keras penerjemahan dan penafsiran Alquran ke dalam Bahasa Jawa. Bukankah Alquran adalah bimbingan hidup bahagia dan sejahtera bagi manusia?”
Kesadaran spiritual Kartini menyentak Kyai Sholeh Darat, bahwa alquran seharusnya bisa dipahami oleh umat Islam yang menjadikannya dasar tuntunan hidup. Sementara masyarakat Jawa mayoritas belum memahami Bahasa Arab yang menjadi bahasa Alquran. Inilah yang menggugah Kyai Sholeh Darat untuk menulis Tafsir al fatihah ke dalam bahasa Jawa pegon. Kitab ini kemudian diberi nama Kitab Faidhur-Rohman, yang konon menjadi kitab tafsir pertama berbahasa Jawa.
Kartini tidak hanya sosok perempuan yang menginginkan perubahan pada perempuan sebangsanya. Kartini juga menjadi sosok inspiratif bagi perkembangan spiritualitas masyarakat Jawa yang mendambakan menjadi hamba salih dengan memahami alquran sebagai pedoman hidup. Melalui terjemahan alquran berbahasa jawa kartini membayangkan masyarakat Jawa bisa membaca Alquran sekaligus memahami isinya. Bukan hanya membaca Alquran tanpa memiliki pengetahuan tentang isinya seperti yang terjadi pada masyarakat Jawa saat itu.
Pada akhirnya, penghormatan pada Kartini jangan hanya sebatas kebaya. Kartini adalah sosok inspiratif yang merawat daya kritis, tradisi menulis dan kecerdasan spiritualnya yang seharusnya kita teruskan perjuangannya. Bukan soal perempuan saja namun soal martabat bangsa Indonesia.
Dr. Ida Rochmawati, M.Fil.I