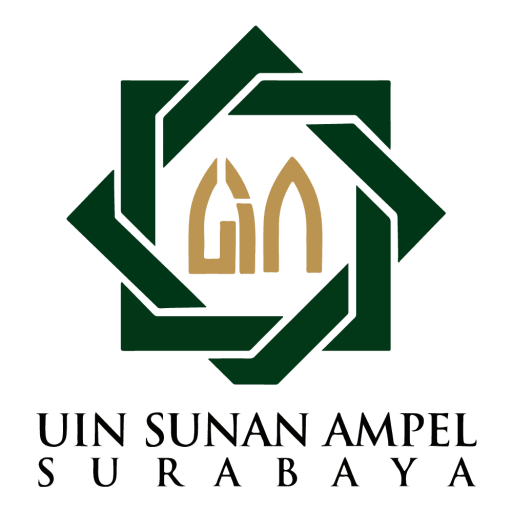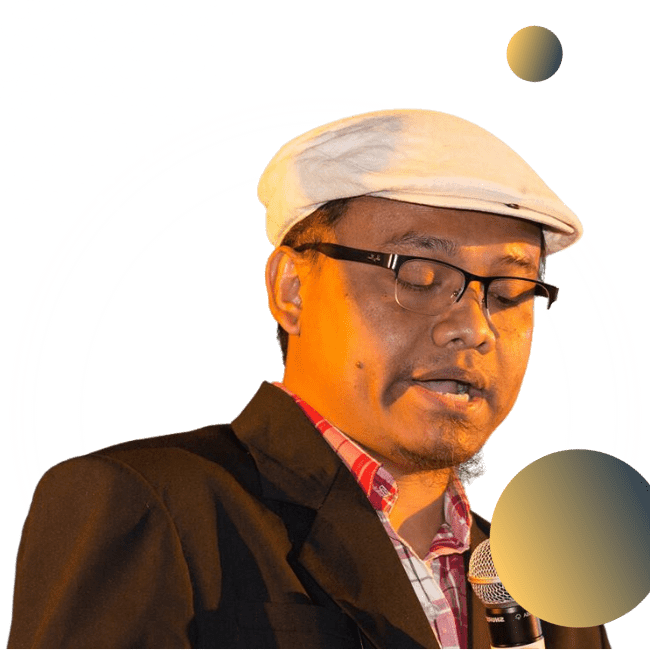
Ramadhan merupakan bulan penuh berkah yang mengajarkan Muslim untuk menahan hawa nafsu, memperbanyak ibadah, serta meningkatkan kepedulian sosial melalui zakat dan sedekah. Puasa Ramadhan bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga sarana untuk membentuk disiplin diri serta mengontrol perilaku konsumtif. Namun, di tengah modernisasi dan perubahan sosial ekonomi, fenomena konsumerisme justru semakin terlihat dalam praktik Ramadhan dan Idulfitri.
Fenomena Konsumerisme Saat Ramadhan dan Idul Fitri
Puasa mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan, termasuk dalam pola makan. Namun, dalam praktiknya, iftar atau berbuka puasa sering kali menjadi momen “balas dendam” setelah menahan lapar seharian. Tradisi berbuka puasa dengan menu lengkap, mulai dari hidangan pembuka, berbagai minuman manis, hidangan utama yang berlimpah, hingga pencuci mulut yang jarang ditemui sehari hari, menunjukkan adanya pergeseran dari nilai spiritualitas puasa menuju perilaku konsumtif. Fenomena ini sejalan dengan teori Conspicuous Consumption (Veblen, 1899), di mana konsumsi dilakukan bukan sekadar memenuhi kebutuhan, tetapi juga sebagai simbol status sosial. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga di sektor makanan dan minuman meningkat drastis selama bulan Ramadhan. Riset dari McKinsey & Company (2022) juga mencatat lonjakan belanja hingga 20-30% pada sektor makanan dan minuman selama Ramadhan.
Lebih lanjut, setelah sebulan berpuasa, Idulfitri seharusnya menjadi refleksi atas pencapaian spiritual menjadi bertaqwa. Namun, terlihat bergeser dari momentum penyucian diri menjadi ajang konsumsi berlebihan.
Fenomena Lebaran Sale yang ditandai dengan pembelian baju baru, makanan, kue-kue khas Idulfitri, hingga kebutuhan konsumsi lainnya menunjukkan bagaimana Idulfitri telah menjadi momentum puncak dalam perilaku konsumsi masyarakat Muslim. Dalam konteks Idulfitri, membeli baju baru sering kali diikuti dengan belanja perhiasan, sepatu, tas, bahkan renovasi rumah agar tampak lebih “mewah” di hari raya. Berdasarkan Survey Bank Indonesia (2023), terjadi peningkatan belanja rumah tangga sebesar 40% menjelang Idulfitri, dengan sektor pakaian dan makanan menjadi kategori utama pengeluaran masyarakat. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Diderot Effect (McCracken, 1988), di mana pembelian satu barang baru memicu pembelian barang lain agar sesuai dengan standar atau estetika yang sama.
Ramadhan, Idulfitri, dan Keseimbangan Konsumsi
Di sisi ekonomi, meningkatnya konsumsi selama Ramadhan dan Idulfitri berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Keynesian Consumption Theory (Keynes, 1936), peningkatan konsumsi rumah tangga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan barang dan jasa, terutama di sektor ritel dan makanan. Dalam konteks Indonesia, peningkatan konsumsi selama Ramadhan dan Idulfitri berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, terutama di sektor ritel dan makanan.
Namun demikian pola konsumtif yang tidak terkendali bisa berimplikasi pada ketidakseimbangan finansial individu dan keluarga. Perilaku konsumtif yang berlebihan sering kali membuat masyarakat terjerat dalam utang konsumtif pasca-Idulfitri. Fenomena ini disebut dengan Post-Ramadhan Financial Stress, di mana banyak individu mengalami tekanan finansial akibat pengeluaran berlebihan selama Ramadhan dan Idulfitri (Al-Harbi, 2021). Dalam Islam, keseimbangan dalam konsumsi sangat ditekankan. Surah Al-Isra’ ayat 27 menyebutkan bahwa “Orang-orang yang boros adalah saudara setan,” menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak.
Membangun Kesadaran Baru: Konsumsi Bijak dan Spiritualitas
Ramadhan dan Idulfitri mengajarkan keseimbangan antara spiritualitas dan ekonomi, Untuk menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan konsumsi, perlu ada edukasi dan kesadaran sosial yang lebih luas. Diantaranya melalui Household Financial Planner menjadi langkah awal dalam menanamkan literasi keuangan berbasis syariah, membantu umat Muslim mengelola keuangan dengan bijak dan menghindari konsumsi berlebihan selama Ramadhan dan Idulfitri.
Kedua, perlu didorong kesadaran berkelanjutan dalam konsumsi, seperti berbuka puasa dengan menu sederhana dan menerapkan zero waste guna mengurangi pemborosan makanan, sejalan dengan ajaran Islam yang menentang israf (pemborosan).
Terakhir, membangun kesadaran Filantropi Islam yang terus diperkuat melalui zakat, sedekah, dan berbagai program sosial, seperti berbagi makanan dan sedekah pakaian layak pakai. Upaya ini berkontribusi pada pemerataan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.
Dengan mengedepankan konsep konsumsi berkelanjutan, literasi keuangan Islami, dan penguatan nilai berbagi, kita dapat menjaga esensi Ramadhan dan Idulfitri sebagai momen pembelajaran spiritual, bukan sekadar ajang konsumsi yang tidak terkendali. Sebagai umat Muslim, kita dituntut untuk tidak hanya beribadah secara ritual, tetapi juga menata pola hidup yang lebih bijak dan sesuai dengan prinsip Islam.