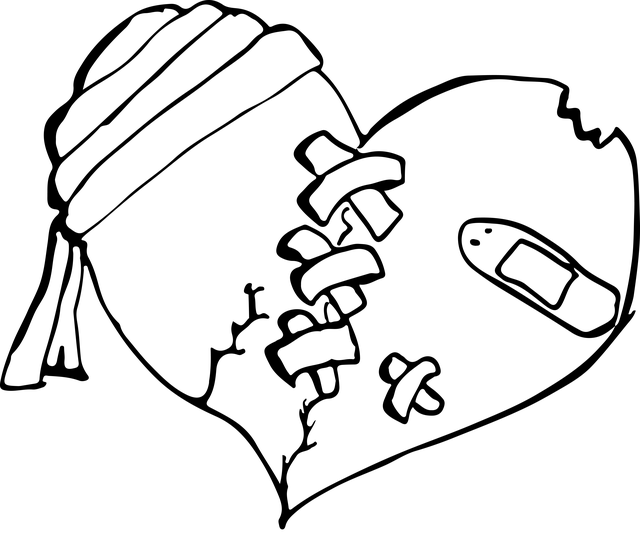Faith – the Pierless Bridge
Supporting what We see
Unto the scene that We do not –
Larik tersebut adalah bagian dari senandung puitik Emily Dickinson yang dikutip oleh Elizabeth Drescher untuk memungkasi bukunya Choosing Our Religion: The Spiritual Lives of America’s Nones (2016). Drescher menyaksikan sebuah tren perkembangan keagamaan di Amerika Serikat yang mendorong pertumbuhan kelompok Nones. Yaitu mereka yang memilih jalan hidup ‘menjadi salih’ dengan tanpa terafiliasi pada entitas lembaga keagamaan tertentu (Unaffiliated). Menghadapi fenomena ini, menurut pandangannya, alih-alih menghabiskan energi untuk merengkuh (to recapture) mereka agar bisa kembali ke gereja, sinagog, atau masjid, Drescher menyarankan sebaliknya. Mayoritas orang Amerika Serikat yang masih memilih berafiliasi (Somes; Affiliated) semestinya justru harus lebih banyak mendengarkan (to listen) kisah dan cerita para Nones. Mereka perlu berani melangkah maju dengan penuh keyakinan, menyambut tantangan untuk membangun jembatan penghubung ke dunia baru. Suatu kehidupan keberagamaan yang semakin kaya selaras dengan kompleksitas jiwa Amerika.
Harapan masa depan semacam yang dikemukakan Drescher itu juga dijumpai pada bacaan Geneive Abdo satu dekade sebelumnya. Hanya saja kali ini dalam konteks keagamaan di kalangan Muslim Amerika Serikat. Abdo merasa optimis ketika menjumpai lanskap perkembangannya pasca peristiwa 9/11. Setelah bercermin pada sejarah panjang komunitas Muslim di negeri itu, ia melihat bahwa generasi baru Muslim akan terlahir dengan identitas yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Mereka mewakili citra Muslim yang mampu merekonsiliasi dua puak peradaban besar yang dalam lintasan zaman kerap berseteru, yaitu dunia Muslim dan dunia Barat. Mereka dapat digambarkan jelas berbeda dari “Islam Budak” (Slave Islam), generasi rapuh yang direpresentasikan oleh para budak yang kebanyakan didatangkan dari Afrika Barat di awal abad ke-16. Mereka juga berbeda dari “Muslim Padang Rumput” (Prairie Muslims) yang terisolasi. Mereka pun berbeda dari “Islam Kulit Hitam” (Black Islam) yang telampau berfokus pada persoalan rasial. Sementara generasi baru Muslim tersebut merupakan sosok-sosok yang berani speak-up tentang agama dan identitasnya di ruang publik. Menghadapi beragam stigma dan stereotipe miring tentang diri mereka dan agamanya secara percaya diri. Menegaskan bahwa untuk menjadi moderen dan maju, tidak harus dengan menyembunyikan atau merubah jati dirinya sebagai Muslim (Mecca and Main Street: Muslim Life in America After 9/11, 2006).
Karya dua perempuan tersebut merupakan contoh bagaimana manusia terdidik memiliki perhatian tidak hanya pada kekinian. Tetapi keseriusannya dalam membaca, menganalisis, serta menafsirkan data-data yang ia temukan, baik dari penelaahan sumber yang tengah ‘berbicara’ di hari ini maupun sumber yang masih ‘berbisik’ dari masa lampau, adalah untuk menyalakan terang bagi langkah kemanusiaan kita menuju hari esok dengan segala kemungkinannya. Sebagaimana sosok sejarawan, yang oleh penulis bahasakan dalam Reenacting Sukarno’s Aji Pancasona in Learning History (2024), ia tak hanya mengkaji ‘sejarah terarsip’ (archived history) dan ‘sejarah terpendam’ (hidden history), pun tak berhenti menamati ‘sejarah bergerak’ (in-the-making history) di keseharian hidupnya, tetapi ingin bisa mengintip opsi-opsi lintasan ‘sejarah terbayang’ (imagined history) yang terhubung melalui ‘the pierless bridge’ dalam istilah Emily Dickinson dengan masa depan.
Ketika umumnya manusia terjebak dalam normalisasi fenomena keseharian, di mana sikap dan perilaku mereka sudah terbiasakan dengannya, manusia terdidik terus berusaha setia melangkah di bawah terang lentera zamannya (lumen veritatis). Terang kebenaran, bukan gelap kedustaan. Bagaimanapun juga, mereka menginsyafi jika kemungkinan terjadinya kesesatan dan distorsi dalam memahami suatu peristiwa historis akan selalu ada. Khyati Y. Joshi dalam White Christian Privilege: The Illusion of Religious Equality in America (2020) menyebutnya sebagai optical illusion. Ilusi yang bisa mempengaruhi dan menghalangi seseorang untuk melihat kebenaran. Di titik ini, manusia terdidik seharusnya juga menginsyafi bahwa tanggung jawabnya tidak hanya sekedar untuk memahami, memenuhi rasa keingintahuannya sendiri, tetapi juga menyuarakannnya agar didengar dan diketahui oleh yang lainnya. Bahkan, menurut Michel Foucault, jikalau hal itu harus berhadapan dengan resiko yang tidak menyenangkan. Sebagaimana pilihan parrhesiastes dalam tradisi Yunani Kuno, maka manusia terdidik tak enggan dan tak segan “to tell the truth […] to power” (Fearless Speech, 2001). Tanggung jawab kaum terdidik adalah memastikan bahwa ruang publik tak membungkam kebenaran untuk disuarakan atau menjadikan kedustaan untuk tetap dilanggengkan. Kata Noam Chomsky, “It is the responsibility of intellectuals to speak the truth and to expose lies” (The Responsibility of Intellectuals, 1967).
Pernyataan-pernyataan tersebut senada dengan apa yang telah Rasulullah Muhammad saw wasiatkan sejak 14 abad lalu, “قل الحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا” atau nyatakanlah kebenaran itu sekalipun terasa pahit. Pesan kenabian ini bisa dikaitkan dengan perintah Allah di Surah al-Nisa’ (ayat 135) dan al-Maidah (ayat 8) kepada mereka yang mengaku beriman agar menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan kebenaran dan saksi yang adil atasnya.
Sembari menyaksikan banyak kendaraan melintas di ujung selatan Jalan Dr. Ir. H. Soekarno, penulis masih terbawa aura beberapa pemberitaan yang tengah viral di negeri ini. Tentang Sukatani yang sempat harus klarifikasi kepada Polisi. Lalu terbaru tentang mega korupsi Pertamina yang bikin kecewa dan marah hampir semua pengguna BBM Pertamax selama ini. Teringat oleh penulis, masih ada mahasiswa Prodi SPI yang terancam tak lulus kuliah karena belum mampu bayar UKT di semester ini. Aih, jika saja triliunan rupiah itu dikonversi jadi beasiswa bagi manusia kampus yang terkendala biaya, alangkah manisnya. Tetapi para koruptor itu, bukankah dulunya mereka manusia kampus juga? Ketika mereka dulu dididik, apakah minyak Pertamax oplosan yang dipakai untuk menyalakan lentera kemanusiaannya?
Melihat hari ini, begini. Melihat kemarin, begitu. Hari esok? Makin terang atau justru tambah gelap?
_____
Ditulis oleh Nyong Eka Teguh Iman Santosa, Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Ampel Surabaya
Kolom lainnya oleh penulis:
– Tiga Siti di Sisi Tiga Lelaki
– Demonisasi Maskulinitas di Balik Sakralitas Tubuh Perempuan
– Efek Janda dalam Pendidikan
– Cara Guru/Dosen Menikmati ‘Hadiah’ dari Kekasih
– Tiga Alasan Ngeri Menjadi Guru/Dosen Hari Gini
– Dilema Cinta Prodi SPI UIN Sunan Ampel Surabaya
– Segitiga Cinta Pengabdian Para Pegawai di UIN Sunan Ampel Surabaya