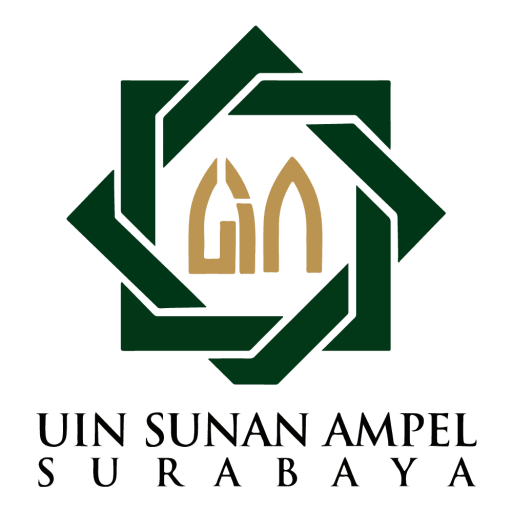Esoteris Adab Beribadah
Oleh: Muchammad Ismail, Dosen FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya
Agama-agama besar di dunia, baik yang bersumber dari wahyu ilahi (agama langit) maupun yang lahir dari tradisi dan budaya masyarakat (agama bumi), senantiasa menekankan pentingnya adab sebagai perisai agama. Selain itu, adab juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai keagamaan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui etika dan tata cara beribadah. Adab merupakan cerminan kesempurnaan dalam beragama, yang menghubungkan antara kedalaman pemahaman dan perilaku seseorang terhadap ajaran agamanya.
Adab secara bahasa berasal dari dialek Arab, aduba, ya’dubu, adaban. Secara istilah berarti aturan kesopanan atau tata krama. Istilah ini sering diidentikkan dengan istilah etika atau akhlak walaupun ketiganya tidak sama persis. Ada perbedaannya antara etika dan adab. Etika bisa jadi menjelaskan yang berhubungan dengan nilai baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Sedangkan istilah adab digunakan untuk memberikan kriteria perbuatan yang sedang dinilai. Karena itu adab lebih mengacu pada perbuatan manusia. Dengan demikian, perbedaan antara etika dan adab adalah terletak pada sifat dan wilayah pembahasannya. Jika etika lebih banyak bersifat teoritis sedangkan adab lebih banyak bersifat praktis. Etika memandang tingkah laku manusia secara umum, sedangkan adab bersifat lokal bisa individual dan komunal. Etika menjelaskan ukuran baik buruk, sedangkan adab menyatakan ukuran tersebut dalam bentuk perbuatan.
Konsep adab dalam pandangan tasawuf sebagai buah dari sebuah proses pembentukan akhlak (perangai) baik secara lahir atau batin. Syaikh Syiab al-Din Umar al-Suhrawardi (1939: 62), mengatakan bahwa jika seseorang hamba telah membentuk akhlaknya lahir dan batin, maka dia akan menjadi seorang sufi yang beradab. Tidak sempurna adab seorang hamba kecuali dengan memiliki akhlak yang sempurna. Kesempurnaan akhlak terjadi dengan cara memperbaiki perangai.
Ada dua kisah menarik tentang adab yang mencerminkan pengalaman esoterik dalam beribadah, baik dari sisi religius maupun spiritual:
Pertama, antara ahli tasawuf hujjatul islam Imam Al-Ghozali dengan adiknya sendiri, ketika Al-Ghozali yang menjadi imam Shalat Ashar di sebuah Masjid. Beliau baru saja mengajarkan hukum thaharrah bagi wanita yang sedang haid. Tanpa disadari pikiran beliaunya saat Shalat teringat kepada wanita yang sedang haid. Salah seorang yang menjadi makmun Shalat adalah adik kandung Imam Al-Ghozali sendiri. Setelah selesai Shalat adiknya menegur, dengan adab lemah lembut bertanya, “kenapa Abang dirakaat kedua mengingat wanita yang lagi haid ?. Imam Al-Ghozali terkejut, selaku imam yang sangat ahli dalam hukum Islam, telah hafal al-Quran dan ribuan Hadis telah berpuluh tahun menjadi imam, baru sekarang mengetahui kekeliruannya selama ini. Imam Al-Ghazali berkata kepada adiknya, “Tajam sekali mata hatimu, mulai saat ini aku berguru kepada mu”.
Kedua, antara ahli hikmah dan sufi ternama, pada suatu hari Hasan Al-Basri pergi memuji si Fulan, seorang sufi ternama. Pada waktu shalatnya, Hasan Al-Basri mendengar si Fulan banyak melafalkan bacaan shalatnya dengan keliru. Oleh karena itu Hasan Al-Basri memutuskan untuk tidak shalat berjamaah dengannya. Ia menganggap kurang pantas, adab bagi dirinya untuk shalat bersama orang yang tak mengucapkan bacaan shalat dengan benar. Di malam harinya, Hasan Al-Basri bermimpi. Ia mendengar Tuhan berbicara kepadanya, “Hasan, jika saja kau berdiri di belakang si Fulan menunaikan shalatmu, kau akan memperoleh keridhaan-Ku, dan shalat kamu itu akan memberimu manfaat yang jauh lebih besar dari pada seluruh shalat dalam hidupmu. Kau mencoba mencari kesalahan dalam bacaan shalatnya, tapi kau tak melihat kemurnian dan kesucian hatinya. Ketahuilah, Aku lebih menyukai hati yang tulus daripada pengucapan tajwid yang sempurna.”
Dalam perjalanan spiritual dan ibadah, sering kali manusia dihadapkan pada pengalaman esoterik yang menguji kedalaman kesadaran batin dan ketulusan hati. Dua kisah yang telah dipaparkan tentang Imam Al-Ghazali dan Hasan Al-Basri bukan hanya memperlihatkan bagaimana adab dan akhlak menjadi kunci dalam perjalanan ibadah, tetapi juga bagaimana perubahan perilaku menjadi indikator dari penyempurnaan spiritual seseorang.
Kisah pertama menggambarkan pengalaman Imam Al-Ghazali yang mendapatkan koreksi dari adiknya sendiri dalam shalat. Sebagai seorang yang telah mencapai tingkat keilmuan tinggi, Imam Al-Ghazali tetap terbuka terhadap kritik yang membawanya pada kesadaran baru.
Perubahan perilaku yang terjadi dalam dirinya merupakan refleksi dari prinsip tasawuf tentang tazkiyatun nafs (pensucian jiwa). Pengalaman ini menegaskan bahwa ilmu, sekalipun luas dan mendalam, tetap harus disertai dengan mata hati yang tajam dan kepekaan batin. Kesalahan kecil dalam ibadah yang sebelumnya tak disadari menunjukkan bagaimana seorang ahli ibadah masih terus dalam proses penyempurnaan, dan kesediaan untuk berguru pada adiknya merupakan bentuk penghancuran ego(fana’), yang merupakan inti dari tasawuf.
Kisah kedua memperlihatkan bagaimana Hasan Al-Basri, seorang yang dikenal sebagai ahli hikmah, mengalami perubahan perspektif setelah mendapat teguran dalam mimpinya. Awalnya, ia menilai kualitas ibadah seseorang berdasarkan ketepatan dalam bacaan shalat, sebuah pendekatan yang lebih cenderung bersifat legalistik. Namun, melalui pengalaman mistiknya, ia menyadari bahwa hakikat ibadah tidak hanya terletak pada ketepatan hukum, tetapi juga pada kesucian hati.
Dalam tasawuf, pengalaman ini merupakan transisi dari syari’at menuju hakikat, yakni dari sekadar menjalankan aturan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang spiritualitas ibadah. Hal ini juga mengajarkan tentang keadaban dalam menilai orang lain, di mana kesalahan lahiriah tidak selalu mencerminkan kekurangan batiniah. Perubahan perilaku Hasan Al-Basri setelah mimpinya menunjukkan peningkatan maqam spiritual, di mana ia belajar untuk melihat seseorang dari aspek batin dan bukan sekadar dari aspek lahiriah semata.
Kedua kisah diatas mencerminkan bagaimana perubahan perilaku dalam ibadah dapat terjadi ketika seseorang mengalami pengalaman esoterik yang mengguncang kesadaran batinnya. Imam Al-Ghazali dan Hasan Al-Basri sama-sama mengalami momen pencerahan yang mengubah cara mereka memandang ibadah dan adab terhadap sesama.
Dalam perspektif sosiologi tasawuf, ibadah bukan hanya soal kepatuhan lahiriah terhadap aturan, tetapi juga tentang perjalanan batin yang terus menerus mengarah pada pensucian diri dan kesadaran akan hakikat Tuhan. Perubahan perilaku yang lahir dari pengalaman spiritual semacam ini menegaskan bahwa adab dan ketulusan hati adalah inti dari ibadah yang sejati.
Ada pengalaman lain dari Muhammad Ibn Sirrin, (2007: 318) dalam Risalah al-Qusayiriyah, ketika ditanya oleh seseorang, adab apa yang dekat dengan Allah dan dapat mensucikan seorang hamba ?, Ia menjawab, “Mengenal (ma’rifat) akan rubbûbiyyah Allah, taat terhadap perintah-Nya, serta sabar ketika susah”. Senada dengan pandangan kritis Ibnu Athaillah (2011: 78) didalam Farhat al-Nufûs Bišarh Taj al-‘Arûs al-Hâwi li Tahdzȋb al-Nufûs, mengatakan “Jika kau tenggelam dalam bangkai dunia, kau tak layak memasuki hadirat-Nya. Sebab, hadirat Allah tidak bisa dimasuki manusia yang mengotori diri dengan najis maksiat. Karena itu, bersihkan hatimu dari aib, niscaya Allah akan membuka pintu gaib. Bertobatlah dan kembalilah kepada Allah dengan hati yang selalu ingat kepada-Nya. Siapa yang terus mengetuk pintu, pasti akan dibukakan untuknya. Seandainya bukan karena cinta, kami tidak akan menyampaikan hal itu kepadamu karena keadaannya seperti yang dikatakan oleh Rabiah al-Adawiyah r.a, “Kenapa gerbang pintu ditutup sehingga harus dibuka.”?!
Karena itu Nasir al-Din al-Sarraj al-Tusi berpandangan didalam al-Lumâ’ (1960: 365), mengatakan bahwa seorang sufi telah membagi manusia dari segi adab menjadi tiga tingkatan; ahli dunia, ahli agama, ahli agama yang lebih khusus (al-khawwâs). Ahli dunia lebih menekankan adab, mereka dalam hal kefasihan, balâghah dan pengetahuan ilmu-ilmu lahiriyah. Pada ahli agama, adab lebih ditekankan pada riyâdah al-nafs (pelatihan jiwa) mensucikan batin, menjaga batas-batas syariat dan meninggalkan syahwat, menjauhi syubhat, serta membiasakan taat dan segera berbuat kebaikan. Pada ahli agama yang lebih khusus (khawwâs), adab mereka adalah usaha membersihkan hati, menjaga rahasia, tepat janji, menjaga waktu dan tidak tertarik kepada kecenderungan nafsu.
Mengenai pentingnya adab dalam kehidupan seorang Muslim, Rasulullah Saw dalam sebuah hadistnya yang diriwayatkan ‘Âisyah mengatakan “Hak sorang ayah kepada anaknya adalah memperbaiki namanya, memperbaiki tempat tinggalnya, dan memperbaiki adabnya.” Hubungan adab dan tasawuf memang sangat diperhatikan. Dalam hadis Rasulullah Saw yang mengatakan “Hassinû Akhlâqakum” yang artinya perbaikilah akhlakmu, ini menunjukkan bahwa akhlak seseorang manusia dapat menjadi berubah. Hal ini disebabkan karena Allah menciptakan manusia dengan memiliki kecenderungan terhadap kebaikan dan keburukan, di samping sebagai subjek dari akhlak dan adab, seperti firman Allah dalam (QS al-Syam: 8) “Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan”, dapat dipahami bahwa dalam jiwa manusia ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan baik dan tidak baik. Kecenderungan ini dapat diatasi dengan jalan mensucikan diri (tazkiyat an-nafs) yaitu berupa mendidik perangai ke arah perbuatan yang di Ridhoi oleh Allah, seperti firman Allah dalam (QS al-Syam: 9-10), “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”.
Mari kita renungkan, keterkaitan adab dalam pelaksanaan syariat, menjadi unsur yang sangat penting dalam tasawuf. Salah satu contoh hubungan adab dalam syariat dengan tasawuf, dapat dilihat dalam adab berwudhu. Menurut al-Suhrawardi (1939: 111,112) didalam ‘Awârif al-Ma’ârif, Jilid II, Adab yang harus mereka lakukan setelah mengenal hukum-hukum syariat adalah adab dalam wudhu, yaitu menghadirkan hati ketika membasuh anggota badan. Orang-orang saleh, kata Suhrawardi, jika hati mereka merasakan kehadiran Allah ketika wudhu, maka dalam shalat mereka juga akan menjadi tenang; tetapi jika terdapat kelalaian dalam wudhu, maka masuklah rasa was-was dalam shalat mereka. Karena itu mereka selalu melihat bahwa dengan membiasakan wudhu akan membuat hati mereka menjadi tenang. Hal ini karena anggota badan yang telah tersirami dengan air wudhu, dapat memperkecil jalan setan masuk ke dalam dirinya. Adab berwudu bagi seorang sufi, menurutnya ada 13 doa’ nafilah yang harus dijalankan secara tertib saat berwudhu, mulai membasuh dari atas hingga akhir ke bawah; berwudhu bukan hanya sempurna lahir secara (eksoteri) tata cara ritual, akan tetapi bagaimana berwudhu menjadi sempurna secara bathin (esoteris) hadirnya rasa antara alam pikiran dan alam hati melebur pada lii rabbi. (1939: 115) Li rabbi dapat dimaknai sebagai pengetahuan atau penyaksian langsung terhadap kehadiran Allah melalui hati yang suci saat bersuci. Wudhu menjadi sarana untuk membuka hijab antara diri seorang hamba dengan Allah, di mana setiap basuhan dalam iringan doa’ wudhu merupakan bentuk penyaksian Ilahi.
Semoga ada hikmah di balik pengalaman esoteris pensucian jiwa dari para Sufi diatas dapat membawa pemahaman dan pengetahuan kita ke arah yang lebih bijak, sehingga pada akhirnya mengantarkan pada pendidikan akhlak dan pembentukan adab. Dengan demikian, adab dapat dipahami sebagai manifestasi dari potensi manusia yang terwujud dalam perbuatan. Ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari aspek esoteris dalam adab beribadah, sebab tanpa dimensi ini, Islam hanya akan menjadi kerangka keformalan semata sebuah institusi yang dapat ditafsirkan berdasarkan perspektif keilmuan. Namun, jika Islam dipahami sebagai suatu ajaran esoteris, maka ia akan memiliki kekayaan rohani dan kedalaman jiwa. Kekayaan ini dapat melahirkan semangat untuk menempuh kesempurnaan akhlak sosial dan kesalehan agama.
Sebagai penutup tulisan, syaikhul islam Imam Syafi’i (2013: 277) mengingatkan pada kita, adab dikala saat memberikan nasihat, beliaunya mengatakan :
تغمّد ني بنصحك في انفردي # وجنّبني النّصيحة في الجماعة
فإنّ النّصح بين الناّس نوع # من التّوبيخ لا أرضى استماعة
وإن خالفتني وعصيت قولي # فلا تجزع إذا لم تعط طاعة
- Sampaikan nasihatmu kepadaku saat aku sendirian # dan jangan katakan nasihat itu dikala banyak orang.
- Karena memberi nasihat di hadapan banyak orang adalah satu dari kelemahan # aku tidak senang mendengarnya.
- Apabila saran dan ucapanku ini tidak kau perhatikan # janganlah menyesal jika sekiranya nasihatmu tidak ditaati.